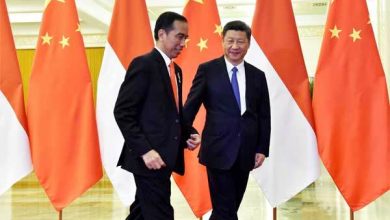Karena itu, kebijakan sosial masa depan perlu juga bertransformasi menuju Digital Poverty Alleviation System — sistem terpadu berbasis big data yang mampu mendeteksi, menarget, dan memantau kondisi rumah tangga miskin secara real-time. Integrasi data BPS, Kemensos, BPJS, dan platform fintech dapat membangun arsitektur kebijakan sosial yang lebih presisi dan adaptif.
Oleh : Perdana Wahyu Santosa*
JERNIH– Agaknya selama dua dekade terakhir, Indonesia menempuh perjalanan panjang dalam upaya menurunkan kemiskinan, dengan berbagai pendekatan yang mencerminkan perubahan filosofi dan dinamika politik-ekonomi nasional. Dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ke Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di era Joko Widodo (Jokowi), hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto — di mana tiap kebijakan merefleksikan cara berbeda dalam memahami kemiskinan pada zamannya.
Namun pertanyaannya tetaplah sama yaitu: seberapa efektif strategi-strategi ini dalam mengatasi akar ketimpangan sosial terutama memasuki era digital?
Fase Konsolidasi Sosial Pasca Krisis
Pada periode yang cukup krusial yaitu 2004–2014, pemerintahan SBY memimpin Indonesia keluar dari trauma krisis ekonomi 1998 menuju stabilitas makro yang relatif kuat dan stabil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan angka kemiskinan dari 16,66 persen pada 2004 menjadi 10,96 persen pada 2014–rerata penurunan 0,57 poin persentase per tahun. Keberhasilan ini tidak datang hanya dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi dari inovasi kebijakan sosial berbasis transfer tunai seperti BLT dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
Menurut pengamatan, kebijakan tersebut berperan penting dalam menstabilkan konsumsi rumah tangga miskin ketika harga minyak dunia melonjak pada 2005 dan 2008. BLT menjadi jaring pengaman sosial efektif dalam menahan guncangan inflasi terhadap daya beli masyarakat bawah. Namun, model bantuan ini masih bersifat charity-based — sejatinya belum sepenuhnya menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi produktif. Masyarakat miskin masih menjadi penerima pasif, bukan pelaku aktif.
Meski demikian, era SBY menandai titik penting: kebijakan sosial menjadi bagian dari strategi fiskal nasional, bukan sekadar proyek karitatif. Pendekatan ini membuka jalan bagi desain sistem perlindungan sosial yang lebih sistematis di masa berikutnya.
Era Digitalisasi Bansos
Memasuki masa Jokowi (2014–2024), paradigma dan konsep berubah: dari bantuan darurat menuju social inclusion economy. Angka kemiskinan berhasil turun lagi, dari 11,22 persen pada 2015 menjadi sekitar 9,03 persen pada 2024. Meskipun laju penurunan melambat — sekitar 0,27 poin per tahun — konteks global jauh lebih berat: pandemi COVID-19, krisis energi, dan disrupsi rantai pasok.
Kekuatan utama pemerintahan Jokowi adalah kemampuan mengintegrasikan kebijakan sosial dengan infrastruktur digital. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menjadi pionir digitalisasi bansos berbasis data registry terpadu. Pendataan masyarakat miskin melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi fondasi bagi sistem targeting berbasis bukti (evidence-based policy).
Namun di sinilah paradoks muncul. Ketika digitalisasi membuka efisiensi distribusi bantuan, persoalan data accuracy dan data exclusion sering kali muncul. Banyak warga miskin baru pasca-pandemi yang belum terdaftar, sementara sebagian penerima tetap berasal dari kategori lama. Masalah klasik inclusion–exclusion error ini menandakan perlunya integrasi lebih dalam antara data fiskal, kependudukan, dan sosial ekonomi.
Selain itu, kebijakan sosial Jokowi semakin diarahkan pada human capital development. Fokusnya bergeser dari bantuan tunai ke peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Secara makro, dampaknya terlihat: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 72,81 (2020) menjadi 75,02 (2024). Namun pertumbuhan IPM ini tetap belum sepenuhnya menurunkan kesenjangan pendapatan, terutama antarwilayah dan antarkelompok sosial.
Era MBG dan Koperasi Desa
Ketika Presiden Prabowo Subianto mulai memimpin pada Oktober 2024, lanskap sosial-ekonomi telah jauh berubah. Tantangan bukan lagi sekadar mengurangi jumlah orang miskin saja, tetapi memperkuat ketahanan ekonomi keluarga miskin terhadap gejolak global yang semakin intens. Di sinilah program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi simbol konsep baru karena menggabungkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan kedaulatan pangan dalam satu kebijakan inklusif.
Program MBG menargetkan puluhan juta siswa di seluruh Indonesia dengan penyediaan makanan bergizi gratis setiap hari sekolah. Secara ekonomi, seharusnya kebijakan ini berpotensi menciptakan efek multiplier: memperkuat permintaan bahan pangan lokal, membuka lapangan kerja di rantai pasok pangan, dan meningkatkan produktivitas belajar. Bila dikelola dengan baik, MBG dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan jangka panjang yang tidak sekadar menolong, tetapi membangun daya tahan sosial generasi muda.
Bersamaan dengan itu, Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor ekonomi rakyat. Hingga Juli 2025, tercatat 80.081 koperasi baru telah berdiri di 38 provinsi. Pendekatan ini menghidupkan kembali semangat koperasi sebagai pilar ekonomi gotong royong, dengan dukungan pembiayaan dan pelatihan terpusat. Ini menandai pergeseran paradigma kebijakan sosial dari konsumsi ke produksi, dari bantuan ke kemandirian.
Tantangan Efektivitas
Meski berbagai kebijakan sosial telah terbukti menekan angka kemiskinan ke level terendah (8,47 persen pada 2025), tantangan berikutnya justru muncul dari sisi efektivitas dan keberlanjutan. Di era digital, pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya diukur dari transfer uang atau makanan, tetapi juga dari digital inclusion. Banyak kelompok miskin kini tidak miskin secara fisik, tetapi digitally excluded — tidak punya akses internet, literasi digital, atau kemampuan ekonomi baru berbasis teknologi.
Karena itu, kebijakan sosial masa depan perlu juga bertransformasi menuju Digital Poverty Alleviation System — sistem terpadu berbasis big data yang mampu mendeteksi, menarget, dan memantau kondisi rumah tangga miskin secara real-time. Integrasi data BPS, Kemensos, BPJS, dan platform fintech dapat membangun arsitektur kebijakan sosial yang lebih presisi dan adaptif.
Penutup
Dua puluh tahun perjalanan pengentasan kemiskinan di Indonesia telah menunjukkan satu benang merah penting: negara semakin belajar memadukan kebijakan ekonomi dan sosial secara lebih sistematis. Era SBY menanamkan fondasi, era Jokowi memperluas dengan digitalisasi, dan era Prabowo mencoba menggabungkan gizi, pendidikan, dan pemberdayaan desa.
Namun, telah terbukti bahwa efektivitas kebijakan sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh tata kelola dan kemampuan untuk mengubah mentalitas masyarakat dari penerima menjadi pelaku. Di masa Prabowo, konsep pengentasan kemiskinan harus dipandang bukan sebagai beban fiskal, tetapi sebagai investasi sosial yang membangun produktivitas nasional.
Diharapkan kebijakan sosial Prabowo mampu menjembatani kesenjangan antara bantuan dan pemberdayaan, maka Indonesia bukan hanya akan menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga membangun middle class society yang tangguh, produktif, dan berdaya saing — inilah makna sejati dari keadilan sosial di era digital. [ ]
* Guru Besar Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI dan Direktur Riset GREAT Institute