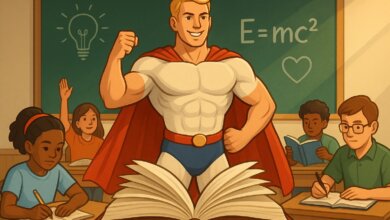Mirip dengan beasiswa, Beaguru bertujuan untuk memastikan kesejahteraan guru agar profesi ini menarik bagi lulusan terbaik. Konsep ini mengundang the bright and brightest di negeri ini untuk terjun ke dunia pendidikan. Tanpa bahan baku SDM yang berkualitas, tidak mungkin menciptakan guru-guru yang mampu membawa perubahan.
Oleh : Turino Yulianto*
JERNIH– Senja di awal Agustus lalu menyapa kami di sebuah sudut Jakarta Selatan, ditemani segelas kopi dan air mineral. Di hadapan kami, duduk Profesor Burhanuddin Abdullah, ekonom terkemuka dan mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar di tim Prabowo-Gibran, serta baru diangkat sebagai Komisaris Utama PLN. Diskusi kami saat itu, bersama rekan-rekan dari majalah Giving Today, berfokus pada program sosial Prabowo, terutama terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan di Indonesia.
Kami berbagi keprihatinan yang sama: kualitas SDM Indonesia belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (HDI), Indonesia menempati peringkat 114 dari 189 negara. Dalam Program for International Student Assessment (PISA) tahun 2022, peringkat Indonesia berada di urutan 68 dari 81 negara untuk literasi, sains, dan matematika. Lebih ironis lagi, sebuah studi mengungkapkan bahwa rata-rata IQ masyarakat Indonesia hanya 78. Meskipun pahit, kenyataan ini harus diterima sebagai obat bagi penyakit kronis yang menggerogoti pendidikan kita.

Masalah lainnya tidak kalah serius: karakter dan adab. Kekerasan di sekolah, manipulasi piagam untuk lolos seleksi zonasi, praktik suap dalam penerimaan siswa, penggunaan ijazah palsu, hingga guru besar yang gemar mencari penghormatan, telah menjamur dan dianggap lumrah. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan siswa, tetapi juga dicontohkan oleh para pemimpin kampus yang gagal menunjukkan keteladanan.
Akar permasalahan ini terletak pada pendidikan nasional yang kehilangan arah. Orientasi pendidikan kita lebih condong pada penyesuaian output dengan kebutuhan industri, seolah-olah siswa hanya dianggap sebagai komoditas untuk pasar tenaga kerja. Sementara itu, konsep Pendidikan Merdeka yang didengungkan lebih merupakan keinginan untuk melepaskan diri dari kekakuan kurikulum, tanpa kejelasan arah yang dituju. Saat ini, kebebasan yang ditawarkan baru sebatas ‘freedom from’, tetapi belum mencapai ‘freedom for’. Anak-anak dibiarkan bebas memilih sesuai keinginan mereka, sebuah opsi yang mungkin menyenangkan, tetapi tidak terarah.
Kritik terbaru datang dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla terhadap Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, yang dianggap kurang memiliki latar belakang pendidikan serta jarang hadir di kantor. Bahkan, ada kabar bahwa ijazah lulusan SMA di Indonesia mengalami penurunan standar di mata universitas di Jerman dan Belanda karena absennya ujian nasional sebagai standar penilaian.
Jadi, mau dibawa ke mana pendidikan kita? Dari berbagai riset dan pengalaman, kunci utama untuk memperbaiki pendidikan adalah kualitas guru. Jika gurunya berkualitas, maka pendidikan akan berangsur membaik. Fasilitas, kurikulum, dan sarana belajar bisa dibangun dalam waktu singkat, tetapi membentuk guru berkualitas membutuhkan visi dan komitmen besar dari negara.
Kisah tentang Kaisar Jepang yang menekankan pentingnya peran guru sering kita dengar. Ketika Jepang luluh lantak oleh bom atom, pertanyaan pertama Kaisar adalah, “Berapa jumlah guru yang masih hidup?” Pertanyaan ini mencerminkan visi yang kuat bahwa guru adalah fondasi bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa. Hasilnya terlihat dalam dua hingga tiga dekade kemudian, ketika Jepang bangkit menjadi negara maju. Di sana, guru dipandang sebagai profesi yang sangat terhormat.
Namun, di Indonesia, sulit mendapatkan guru berkualitas jika kesejahteraan mereka jauh dari memadai. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek menunjukkan bahwa pada 2023, terdapat 3,37 juta guru di Indonesia, tetapi kesejahteraan mereka, terutama yang bukan ASN, masih sangat terbatas. Banyak guru yang menerima gaji kurang dari satu juta rupiah per bulan, dan di beberapa daerah, gaji guru honorer bahkan tidak mencapai Rp500 ribu.
Akibatnya, profesi guru sering kali hanya menjadi pilihan terakhir bagi mereka yang gagal masuk ke profesi lain. Sebagai perbandingan, di negara-negara maju seperti Swiss, Kanada, Amerika, dan Jerman, rata-rata gaji guru sudah melampaui satu miliar rupiah per tahun.
Bayangkan jika pemerintah menetapkan standar pendapatan minimum untuk guru, misalnya dua kali UMR setempat. Dengan demikian, lulusan terbaik dari universitas terkemuka seperti UGM, UI, ITB, IPB, Binus, dan Telkom University akan tertarik menjadi guru. Inilah yang disebut dengan konsep Beaguru.
Mirip dengan beasiswa, Beaguru bertujuan untuk memastikan kesejahteraan guru agar profesi ini menarik bagi lulusan terbaik. Konsep ini mengundang the bright and brightest di negeri ini untuk terjun ke dunia pendidikan. Tanpa bahan baku SDM yang berkualitas, tidak mungkin menciptakan guru-guru yang mampu membawa perubahan. Prof. Burhan menilai bahwa Beaguru adalah ide yang menarik dan sejalan dengan prinsip pendidikan yang menempatkan guru sebagai prioritas utama.
Ia menekankan bahwa program ini dapat berjalan jika biaya pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar pengeluaran. Alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, yang saat ini dikritik karena kurang tepat sasaran, sebetulnya lebih dari cukup untuk membiayai Beaguru. Dengan anggaran ini, kesejahteraan 3,37 juta guru di Indonesia dapat dipenuhi. Idealnya, alokasi anggaran pendidikan sebagian besar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, sisanya untuk sarana belajar, infrastruktur, dan lainnya.
Diskusi kami berlangsung hampir dua jam, dan kesimpulannya, program Beaguru memerlukan visi yang jelas serta komitmen kuat dari pemimpin negara. Harapan kini tertuju kepada Prabowo Subianto untuk mewujudkan hal ini. []
*Ir. Turino Yulianto, MSi. Master Intelijen Strategis dari Universitas Indonesia (UI), pegiat sosial dan pendidikan.