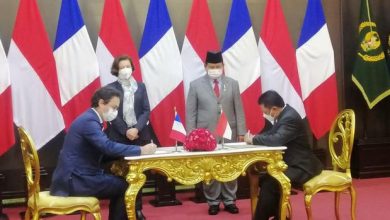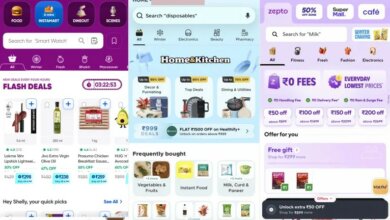Kekerasan terhadap penjual es mengungkap cacat moral institusi keamanan. Saat aparat menjadi ancaman, legitimasi negara dipertanyakan. Seragam negara kembali lupa siapa yang seharusnya dilindungi.
WWW.JERNIH.CO – Jagat maya kembali diguncang oleh sebuah video yang menyisakan rasa sesak di dada. Seorang penjual es—berjuang mengais rezeki di bawah terik matahari—menjadi korban arogansi oknum aparat. Alih-alih mendapatkan pembinaan atau pendekatan yang manusiawi, ia justru diperlakukan secara merendahkan martabat: dipaksa menghabiskan dagangannya sendiri, disertai kekerasan fisik.
Peristiwa ini jelas bukan sekadar “salah paham di lapangan” atau ekspresi ketegasan aparat. Ia adalah cermin retak dari wajah institusi keamanan yang seharusnya menjadi pelindung, terutama bagi mereka yang paling rentan: rakyat miskin yang menggantungkan hidup pada kerja harian. Kejadian ini juga melukai hak azasi manusia.
Secara konstitusional, peran TNI dan Polri telah diatur dengan terang. UU No. 34 Tahun 2004 menegaskan tugas TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Babinsa—sebagai ujung tombak pembinaan teritorial—semestinya menjadi telinga bagi keluh kesah rakyat, bukan algojo bagi pedagang kecil.
Demikian pula Polri, yang melalui UU No. 2 Tahun 2002 diamanatkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Ketika seorang penjual es yang fakir miskin diperlakukan dengan kekerasan, bukan hanya nurani yang dilukai, tetapi juga garis hukum dan moral yang dilanggar secara terang-terangan. Seragam yang seharusnya menjadi simbol perlindungan justru bertransformasi menjadi alat intimidasi.
Dari perspektif hukum, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prosedur operasional standar (SOP) dan hak asasi manusia. Hukum mengenal asas proporsionalitas: tindakan aparat harus sebanding dengan pelanggaran yang terjadi.
Jika pedagang melanggar aturan tata ruang atau ketertiban umum, sanksinya bersifat administratif atau edukatif. Memukul dan memaksa seseorang mengonsumsi dagangannya di luar batas fisik bukan hanya tidak proporsional, tetapi masuk dalam kategori penganiayaan dan penyiksaan (torture), yang dilarang baik oleh konvensi internasional maupun hukum pidana nasional.
Secara tata kelola, insiden ini menyingkap lubang besar dalam sistem pengawasan internal. Aparat di level akar rumput—yang bersentuhan langsung dengan warga—kerap merasa memiliki “kekuasaan mutlak” karena minim pengawasan.
Diskresi yang seharusnya menjadi alat kebijaksanaan berubah menjadi kesewenang-wenangan ketika akuntabilitas tidak berjalan. Profesionalisme aparat semestinya diukur dari kemampuan mereka menangani rakyat kecil tanpa kekerasan, bukan dari seberapa takut warga saat melihat kehadiran mereka.
Pertanyaan mendasarnya: mengapa pola arogansi semacam ini terus berulang meski reformasi birokrasi selalu digaungkan?
Ada masalah struktural dalam pembinaan aparat. Pertama, kurikulum pendidikan militer dan kepolisian masih kerap menitikberatkan maskulinitas dominan dan kepatuhan buta pada komando, namun minim penguatan empati sosial dan pemahaman HAM di level praktis.
Aparat dilatih untuk “menaklukkan” musuh, tetapi gagal membedakan antara ancaman negara dan rakyat kecil yang sedang kebingungan mencari sesuap nasi.
Kedua, budaya impunitas masih terasa kuat. Sanksi internal yang sering berhenti pada level administratif—bahkan sekadar mutasi—tanpa efek jera, menciptakan rasa aman palsu bagi pelaku. Ini diperparah oleh esprit de corps yang keliru: solidaritas yang membutakan, di mana anggota saling melindungi alih-alih saling mengoreksi.
Ketika arogansi dicontohkan oleh senior dan ditiru oleh junior sebagai simbol “wibawa”, maka lingkaran kekerasan akan terus berputar.
Secara teoretis, penyimpangan ini dapat dibaca melalui berbagai lensa. Jean-Jacques Rousseau, dalam teori Kontrak Sosial, menyatakan bahwa rakyat menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara demi jaminan keamanan. Ketika aparat justru menjadi sumber ancaman, kontrak sosial itu cacat secara moral. Negara kehilangan legitimasi etiknya.
Konsep Human Security mempertegas bahwa keamanan sejati bukan hanya soal kedaulatan wilayah, tetapi kebebasan dari rasa takut (freedom from fear) dan kebebasan dari kekurangan (freedom from want). Merampas hak dagang seorang fakir miskin adalah serangan langsung terhadap dua pilar keamanan manusia tersebut.
Sementara itu, Michel Foucault mengingatkan bahwa seragam dan senjata menciptakan asimetri kuasa yang tajam. Dalam konteks ini, kita melihat praktik “mikro-fasisme”: keyakinan keliru bahwa posisi hierarkis memberi hak atas tubuh dan martabat orang lain.
Dari perspektif kerakyatan, tindakan ini adalah pengkhianatan terhadap filosofi Kemanunggalan TNI dengan Rakyat. Rakyat—terutama mereka yang hidup di garis kemiskinan—adalah pemilik sah negeri ini. Memaksa seorang pedagang menghabiskan dagangannya berarti menghina keringat dan perjuangan bertahan hidup.
Bagi seorang fakir miskin, modal hari itu adalah napas bagi keluarganya. Kekerasan semacam ini adalah bentuk pemiskinan struktural yang dilegitimasi oleh arogansi jabatan.
Viralnya peristiwa ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pimpinan tertinggi TNI dan Polri. Kita tidak bisa terus berlindung di balik narasi usang “hanya oknum”. Jika oknum muncul berulang kali, maka masalahnya bukan semata individu, melainkan budaya institusi yang permisif terhadap kekerasan.
Reformasi kultural harus menyentuh hingga level Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Mereka perlu diingatkan kembali bahwa gaji, seragam, dan kehormatan yang mereka pakai berasal dari pajak rakyat—termasuk dari recehan hasil jualan pedagang es di pinggir jalan.
Aparat adalah pelayan rakyat, bukan tuan bagi rakyat. Jika rakyat merasa lebih aman ketika aparat tidak hadir, maka ada yang keliru dalam cara kita mengelola keamanan. Kita merindukan sosok aparat yang membantu mendorong gerobak yang mogok, bukan yang memukul tangan-tangan yang sedang berjuang mencari nafkah halal.
Kasus ini harus diakhiri dengan sanksi tegas dan terbuka, bukan sekadar permintaan maaf formal. Hanya dengan penegakan hukum yang adil dan konsisten, martabat seragam dapat dipulihkan—dan kepercayaan publik yang kian terkikis bisa dibangun kembali.(*)
BACA JUGA: Oknum Pajak dan Bea Cukai Dilindungi Siapa?