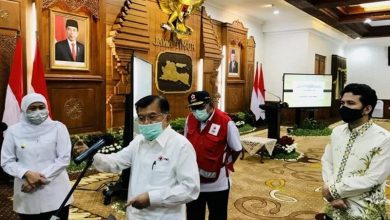Resistensi politik terhadap imigrasi di Jepang yang lama tertutup, serta masyarakat yang terkadang waspada terhadap pendatang baru, telah menyebabkan sistem hukum dan dukungan yang ambigu, yang membuat sulit orang asing untuk menetap. Pekerja asing dibayar rata-rata sekitar 30 persen lebih rendah daripada rekan-rekan mereka warga Jepang.
Oleh : Motoko Rich dan Kiuko Notoya*
JERNIH–Ngu Thazin ingin meninggalkan negaranya yang dilanda perang untuk masa depan yang lebih baik. Dia sudah punya incaran: Jepang.
Di Myanmar, dia belajar bahasa Jepang dan lulus dengan gelar sarjana kimia dari satu universitas paling bergengsi di negaranya. Namun kini dengan senang hati dia mengambil pekerjaan di Jepang sebagai pengganti popok dan memandikan para lansia di sebuah panti jompo di satu kota menengah di negara itu.
“Sejujurnya, saya ingin tinggal di Jepang karena aman,” kata Thazin, yang berharap suatu saat nanti lulus ujian yang memungkinkan dirinya bekerja sebagai pengasuh berlisensi. “Dan saya ingin terus mengirim uang kepada keluarga saya.”
Jepang sangat membutuhkan orang-orang seperti Thazin untuk mengisi pekerjaan yang kosong akibat populasi yang menurun dan menua. Jumlah pekerja asing telah meningkat empat kali lipat sejak 2007, menjadi lebih dari dua juta, di negara dengan populasi 125 juta orang itu. Banyak pekerja ini melarikan diri dari upah rendah, penindasan politik, atau konflik bersenjata di negara asal mereka.
Namun meskipun pekerja asing menjadi lebih nyata di keseharian Jepang–, bekerja sebagai kasir di toko serba ada, petugas hotel, pelayan restoran, petugas panti jompo–mereka diperlakukan dengan ambivalen. Politisi tetap enggan menciptakan jalur bagi pekerja asing, terutama mereka yang memiliki pekerjaan berkeahlian rendah, untuk tinggal dalam jangka waktu lama.
Hal ini bisa jadi pada akhirnya akan merugikan Jepang dalam persaingan dengan negara tetangga, seperti Korea Selatan dan Taiwan, atau bahkan tempat yang lebih jauh seperti Australia dan Eropa, yang juga berusaha keras mencari tenaga kerja asing.
Resistensi politik terhadap imigrasi di Jepang yang lama tertutup, serta masyarakat yang terkadang waspada terhadap pendatang baru, telah menyebabkan sistem hukum dan dukungan yang ambigu, yang membuat sulit orang asing untuk menetap. Pekerja asing dibayar rata-rata sekitar 30 persen lebih rendah daripada rekan-rekan mereka warga Jepang. Karena takut kehilangan hak untuk tinggal di Jepang, pekerja sering memiliki hubungan yang tidak pasti dengan majikan mereka, dan kemajuan karier pun sulit dicapai.
“Kebijakan Jepang dirancang agar orang-orang bekerja di Jepang untuk waktu relatif singkat,” kata Yang Liu, seorang peneliti di Research Institute of Economy, Trade and Industry di Tokyo. “Jika sistem ini terus berjalan seperti sekarang, kemungkinan pekerja asing akan berhenti datang, sangat tinggi.”
Pada 2018, pemerintah Jepang mengesahkan undang-undang yang mengizinkan peningkatan tajam jumlah “pekerja tamu” berkeahlian rendah ke negara tersebut. Awal tahun ini, pemerintah berkomitmen untuk menambah lebih dari dua kali lipat jumlah pekerja tersebut dalam lima tahun ke depan, menjadi 820.000. Mereka juga merevisi program magang teknis yang digunakan oleh pengusaha sebagai sumber tenaga kerja murah–yang dikritik oleh pekerja serta aktivis buruh sebagai penyebab pelecehan.
Namun, para politisi Jepang masih jauh dari membuka perbatasan negara secara luas. Jepang belum mengalami migrasi besar-besaran seperti yang dialami Eropa atau Amerika Serikat. Jumlah total penduduk asing di Jepang–termasuk pasangan non-pekerja dan anak-anak—hanya 3,4 juta alias kurang dari tiga persen populasi. Persentase di Jerman dan Amerika Serikat, misalnya, hampir lima kali lipat.
Jepang telah memperketat beberapa aturan meskipun melonggarkan yang lain. Musim semi ini, Partai Demokrat Liberal yang berkuasa mendorong revisi undang-undang imigrasi Jepang yang memungkinkan pencabutan izin tinggal permanen jika seseorang alpa membayar pajak. Para pengkritik kebijakan ini memperingatkan bahwa beleid itu bisa memudahkan pencabutan status tempat tinggal untuk pelanggaran yang lebih ringan, seperti gagal menunjukkan kartu identitas kepada petugas polisi.
“Ancaman semacam itu merampas rasa aman penduduk tetap (permanen resident) dan akan mendorong diskriminasi dan prasangka,” kata Michihiro Ishibashi, anggota Partai Demokrat Konstitusional Jepang yang beroposisi, di parlemen.
Dalam komite parlemen terpisah, Menteri Kehakiman Ryuji Koizumi mengatakan bahwa revisi tersebut dimaksudkan untuk “mewujudkan masyarakat di mana kita bisa hidup berdampingan dengan orang asing,” dengan memastikan mereka “mematuhi aturan minimum yang diperlukan untuk hidup di Jepang.”
Jauh sebelum orang asing bisa mendapatkan izin tinggal permanen, mereka harus menavigasi persyaratan visa yang rumit, termasuk tes bahasa dan keterampilan. Tidak seperti di Jerman, di mana pemerintah menawarkan penduduk asing baru hingga 400 jam kursus bahasa dengan tarif subsidi sekitar 2 dolar AS per pelajaran, Jepang tidak memiliki pelatihan bahasa terorganisasi untuk pekerja asing.
Meskipun politisi mengatakan negara harus melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mengajar bahasa Jepang, “Mereka belum siap untuk mengalokasikan uang untuk ini dari pajak,” kata Toshinori Kawaguchi, direktur Divisi Pekerja Asing di Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang.
Ini membuat pemerintah daerah dan pengusaha yang pada gilirannya memutuskan apakah akan dan seberapa sering mereka harus menyediakan pelatihan bahasa. Pengelola panti jompo yang mempekerjakan Thazin di Maebashi, ibu kota Prefektur Gunma di Jepang tengah, menawarkan beberapa pengasuhnya satu hari pelajaran bahasa Jepang secara kelompok, serta satu lagi pelajaran 45 menit, setiap bulan. Pekerja yang menyiapkan makanan hanya menerima satu pelajaran sepanjang 45 menit setiap bulan.
Akira Higuchi, presiden perusahaan tersebut, Hotaka Kai, mengatakan bahwa dia memberikan insentif kepada pekerja untuk belajar bahasa Jepang secara mandiri. Mereka yang lulus tingkat kedua tertinggi dari ujian kemampuan bahasa Jepang pemerintah, katanya, “Akan diperlakukan sama dengan orang Jepang, dengan gaji dan bonus yang sama.”
Terutama di luar kota-kota besar, orang asing yang tidak berbicara bahasa Jepang bisa kesulitan berkomunikasi dengan pemerintah daerah atau sekolah. Dalam keadaan darurat kesehatan, sedikit pekerja rumah sakit yang berbicara bahasa selain bahasa Jepang.
Hotaka Kai telah mengambil langkah-langkah lain untuk mendukung stafnya, termasuk menampung pendatang baru di apartemen perusahaan yang disubsidi dan menawarkan pelatihan keterampilan.
Dapur asrama yang digunakan bersama oleh 33 wanita berusia antara 18 hingga 31 tahun meperlihatkan warisan kebiasaan yang bercampur. Dari dapur itu penulis melihat sisa-sisa kemasan merica bubuk “Ladaku” dari Indoesia, serta paket bumbu “Thit Kho” buatan Vietnam yang lazim digunakan untuk membuat daging babi rebus dengan telur.
Di seluruh Prefektur Gunma, ketergantungan pada pekerja asing tidak dapat disangkal. Di Oigami Onsen, sebuah desa pegunungan yang sepi di mana banyak restoran, toko, dan hotel ditutup, setengah dari 20 pekerja penuh waktu di Ginshotei Awashima, sebuah penginapan mata air panas tradisional Jepang, berasal dari Myanmar, Nepal, atau Vietnam.
Dengan lokasi penginapan yang sangat khas pedesaan, “Tidak ada lagi orang Jepang yang ingin bekerja di sini,” kata Wataru Tsutani, pemiliknya.
Beberapa pekerja asingnya memiliki latar belakang pendidikan yang tampaknya memenuhi syarat mereka untuk dapat lebih dari pekerjaan rendahan. Seorang pria berusia 32 tahun dengan gelar fisika dari universitas di Myanmar melayani makanan di ruang makan penginapan. Seorang wanita berusia 27 tahun yang mempelajari budaya Jepang di universitas di Vietnam ditempatkan di meja resepsionis. Seorang pria berusia 27 tahun dari Nepal yang sedang belajar sejarah pertanian di universitas di Ukraina sebelum invasi Rusia, kini mencuci piring dan menata futon, tempat tidur gaya Jepang, di kamar tamu.
Sebagian besar pelanggan di Ginshotei Awashima adalah orang Jepang. Sakae Yoshizawa, 58, yang datang untuk menginap semalam bersama suaminya dan sedang menikmati secangkir teh di lobi sebelum check out, mengatakan dia terkesan dengan pelayanan di sana. “Bahasa Jepang mereka sangat bagus, dan saya merasa nyaman dengan mereka,” kata Nyonya Yoshizawa.
Ngun Nei Par, manajer umum penginapan, lulus dari universitas di Myanmar dengan gelar geografi. Dia berharap pemerintah Jepang akan memperlancar jalan menuju kewarganegaraan yang memungkinkan dia membawa keluarganya ke Jepang, suatu hari nanti.
Tsutani, pemilik penginapan, mengatakan bahwa masyarakat yang belum menyadari kenyataan mungkin keberatan jika terlalu banyak orang asing yang mendapatkan kewarganegaraan Jepang. “Saya sering mendengar bahwa Jepang adalah ‘negara yang unik,'” kata Tsutani. “Tapi tidak perlu mempersulit orang asing untuk tinggal di Jepang,” kata dia. “Kita ini butuh ingin pekerja.” [The New York Times]