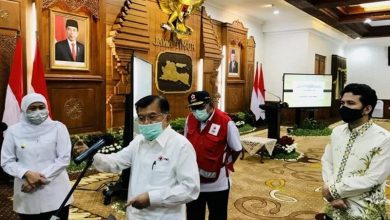Peran Jusuf Kalla mencapai puncaknya ketika ia secara aktif memfasilitasi perundingan antara pemerintah Indonesia dan GAM yang dimediasi oleh Crisis Management Initiative (CMI), sebuah lembaga non-pemerintah yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Proses ini dikenal sebagai “Perundingan Helsinki.” Kalla berada di belakang layar, mengatur strategi politik dalam negeri, mengomunikasikan kepentingan pemerintah kepada pihak mediator, dan memastikan bahwa proses berjalan tanpa gangguan politik.
Oleh : Iswadi
JERNIH– Perdamaian Aceh adalah salah satu tonggak sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Konflik berkepanjangan yang melibatkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia selama hampir tiga dekade berakhir dengan penandatanganan perjanjian damai di Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Di balik keberhasilan monumental ini, terdapat sejumlah tokoh kunci yang berperan secara signifikan, dan salah satu yang paling menonjol adalah Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla, yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden Republik Indonesia dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memainkan peran strategis dan diplomatis yang sangat vital. Ia tidak hanya bertindak sebagai negosiator dari pihak pemerintah, tetapi juga sebagai inisiator dan penggerak utama jalannya perundingan damai.
Sebagai seorang pengusaha sekaligus politisi yang dikenal pragmatis dan solutif, Kalla memahami bahwa konflik bersenjata di Aceh tidak akan pernah bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan militer. Ia percaya bahwa pendekatan dialog dan perundingan adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawa, membangun kembali kepercayaan, dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.
Keterlibatan Jusuf Kalla dalam isu Aceh sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum perundingan Helsinki. Pada awal 2000-an, Kalla turut menginisiasi perundingan-perundingan awal, termasuk upaya damai di bawah payung Henry Dunant Centre (HDC) pada 2002. Meski perundingan ini gagal, pengalaman tersebut menjadi bekal penting baginya dalam memahami dinamika konflik dan karakter para pemangku kepentingan.
Peran Jusuf Kalla mencapai puncaknya ketika ia secara aktif memfasilitasi perundingan antara pemerintah Indonesia dan GAM yang dimediasi oleh Crisis Management Initiative (CMI), sebuah lembaga non-pemerintah yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Proses ini dikenal sebagai “Perundingan Helsinki.” Kalla berada di belakang layar, mengatur strategi politik dalam negeri, mengomunikasikan kepentingan pemerintah kepada pihak mediator, dan memastikan bahwa proses berjalan tanpa gangguan politik.
Di sisi GAM, tokoh yang memainkan peran sentral adalah Malik Mahmud, yang menjabat sebagai juru runding utama. Malik Mahmud merupakan salah satu tokoh senior GAM yang memiliki legitimasi kuat di mata para kombatan dan diaspora Aceh. Ia menunjukkan keteguhan dan kesediaan untuk bernegosiasi dalam kerangka kepentingan jangka panjang rakyat Aceh. Bersama timnya, Malik Mahmud membawa aspirasi masyarakat Aceh yang selama bertahun-tahun merasa terpinggirkan oleh pusat kekuasaan di Jakarta.
Selain Jusuf Kalla dan Malik Mahmud, Martti Ahtisaari juga merupakan figur kunci dalam perundingan ini. Pengalaman Ahtisaari sebagai diplomat internasional dan mantan kepala negara memberi bobot besar pada proses mediasi. Ia berhasil menciptakan suasana yang kondusif, netral, dan profesional dalam meja perundingan. Ahtisaari mendorong kedua pihak untuk tidak hanya berbicara tentang tuntutan mereka, tetapi juga untuk mendengarkan dan memahami satu sama lain.
Satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses ini adalah situasi pasca-bencana tsunami Aceh pada Desember 2004. Tragedi ini menyebabkan ratusan ribu orang meninggal dunia dan menghancurkan infrastruktur wilayah pesisir Aceh. Ironisnya, di tengah penderitaan itu muncul secercah harapan: baik pemerintah maupun GAM menyadari bahwa permusuhan tidak bisa dilanjutkan. Aceh membutuhkan bantuan, pembangunan, dan stabilitas hal yang tidak mungkin terwujud jika konflik terus berkecamuk.
Jusuf Kalla dengan cepat membaca situasi ini sebagai momentum bersejarah. Ia mempercepat proses negosiasi dan melobi berbagai pihak di dalam negeri, termasuk TNI dan DPR, untuk mendukung proses damai. Pendekatannya yang komunikatif, terbuka, dan fokus pada hasil konkret menjadikan Kalla sebagai figur yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Ia tidak hanya bicara perdamaian di ruang diplomasi, tetapi juga bekerja membangun kepercayaan melalui kebijakan nyata seperti pemberian status otonomi khusus dan pembentukan pemerintahan Aceh yang lebih mandiri.
Kesepakatan damai akhirnya ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki. Dalam MoU tersebut, GAM sepakat untuk melucuti senjata dan mengakhiri perjuangan bersenjata mereka. Sebagai gantinya, pemerintah Indonesia memberikan ruang politik yang lebih besar bagi Aceh, termasuk hak untuk membentuk partai lokal, mengelola sumber daya alam, dan menerapkan kebijakan berbasis syariat Islam. Kesepakatan ini menjadi dasar terbentuknya Pemerintah Aceh modern yang demokratis dan damai.
Kini, dua dekade setelah perjanjian itu, Aceh memang belum sepenuhnya bebas dari tantangan. Namun, perdamaian yang telah terbangun menjadi bukti bahwa konflik separatis yang kompleks sekalipun bisa diselesaikan dengan dialog dan komitmen bersama. Dan dalam sejarah itu, nama Jusuf Kalla akan selalu dikenang sebagai arsitek utama perdamaian Aceh. [ ]
*Dr. Iswadi, M.Pd, dosen Universitas Esa Unggul Jakarta