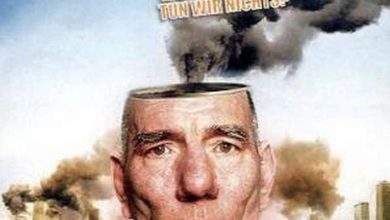Anehnya, sebagian besar dosen di PT tidak menyadari penyakit ini. Mereka malah ikut menyebarkannya. Lihatlah, dalam menulis artikel tentang Indonesia untuk jurnal internasional, mereka lebih suka mengutip pendapat orang asing daripada pendapat orang Indonesia. Untuk rujukan, mereka lebih memilih buku karya orang asing daripada buku karya orang Indonesia.
Oleh : Ana Nadhya Abrar*

JERNIH– Sebuah tulisan Yopie Hidayat muncul di Tempo 2-8 Februari 2026. Judulnya “Ultimatum Asing Menyadarkan Bursa”. Dari judul ini, kita bisa membayangkan isi tulisan itu. Yakni, perjalanan dua pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar dan Inarno Djajadi serta satu petinggi Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, mendadak sontak harus berhenti. Mereka berhenti karena memperoleh ultimatum Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Dalam tulisan sepanjang 13 paragraf tersebut, Yopie menceritakan betapa terguncangnya pasar saham Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sampai turun delapan persen. Untuk menjaga kepastian ekonomi dan mengurangi tekanan terhadap pemerintah, perdagangan saham pun segera dihentikan.
Sebagai penutup tulisan, Yopie menulis: “Petik saja hikmahnya: negeri ini masih memerlukan tekanan asing agar bisa berubah menjadi lebih baik.” Ini membuat kita tersentak macam keong kehilangan rumahnya. Ternyata manusia Indonesia masih memiliki jiwa feodal.
Seperti biasa, kita melakukan introspeksi, sekadar mencari jawaban. Lalu muncul pertanyaan, sudah 80 tahun merdeka, kok jiwa feodal manusia Indonesia masih bertahan? Masak kemerdekaan itu tidak bisa melenyapkan jiwa feodal?
Ingatan kita menerawang ke masa lalu. Dulu, pada 6 April 1977, Mochtar Lubis berceramah di Taman Ismail Marzuki. Ceramahnya itu kemudian dibukukan dalam sebuah buku berjudul “Manusia Indonesia (Sebuah Pertanggungjawaban)”. Di dalam buku itu, Mochtar mengungkapkan enam ciri pokok manusia Indonesia. Ciri ketiga tertulis: “Ciri ketiga utama manusia Indonesia adalah jiwa feodalnya”.
Tentu saja penilaian Mochtar itu menjadi kontroversial. Ada yang pro dan ada pula yang kontra. Abu Hanifah (1981) misalnya mengatakan, “Zaman Angkatan 1928, feodalisme itu tidak banyak lagi”. Ia berganti dengan neo-feodalisme. “Dalam hati kecil, hanya dirasakan, bahwa sebenarnya neo-feodalismelah yang ada sekarang,” tambah Abu.
Mengikuti pendapat Abu Hanifah ini, kita tentu mengerti tidak mudah melenyapkan jiwa feodal. Mengiringi perjalanan waktu, ia bermetamorfosis menjadi neo feodalisme. Ini terlihat jelas dalam kasus BEI. Kekuatan asing yang bernama MSCI menjadi “juragan” OJK dan BEI. Ia menguasai OJK dan BEI. Begitu berkuasanya, sehingga OJK dan BEI harus tunduk dan patuh pada MSCI.
Bukan cuma itu, neo feodalisme juga menjangkiti sebagian besar perguruan tinggi (PT) kita. Mereka berlomba-lomba memperoleh peringkat dari lembaga peringkat asing PT seperti Times Higher Education (THE) WUR, UniRank (4ICU), dan QS World University Rankings (QS WUR). Mereka merasa tidak nyaman kalau tidak mendapat peringkat dari salah satu dari ketiga lembaga peringkat asing PT tersebut.
Anehnya, sebagian besar dosen di PT tidak menyadari penyakit ini. Mereka malah ikut menyebarkannya. Lihatlah, dalam menulis artikel tentang Indonesia untuk jurnal internasional, mereka lebih suka mengutip pendapat orang asing daripada pendapat orang Indonesia. Untuk rujukan, mereka lebih memilih buku karya orang asing daripada buku karya orang Indonesia.
Dari kenyataan menyedihkan ini, kita tentu mengerti, sebagian manusia Indonesia tidak memiliki kepercayaan diri. Mereka tidak mampu melakukan perubahan sendiri. Mereka masih memerlukan validasi dari luar untuk membenarkan tindakannya. Dalam keadaan begini, kita mesti mengatakan jiwa feodal masih hidup dalam diri sebagian manusia Indonesia.
Sampai di sini tentu muncul pertanyaan, bagaiman melenyapkan jiwa feodal itu? Yang sangat penting tentu saja membangun rasa percaya diri. Para profesionalisme di berbagai bidang mesti belajar, mengusahakan dan mempraktikkan rasa percaya diri. Bagaimana caranya? Mempraktikkan berbagai jurus tentang mengembangkan rasa percaya diri, mulai dari berani menghadapi tantangan, tidak takut gagal, berimajinasi tentang keberhasilan hingga mengikuti suara-suara positif.
Kendati begiu, kita perlu waspada, membangun rasa percaya diri adalah proses, bukan tujuan. Nikmati prosesnya. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. [ ]
*Guru Besar Jurnalisme UGM