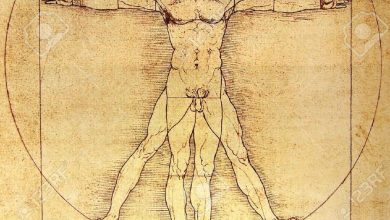Justru Sokrates, yang terus mengajak orang berpikir dan mempertanyakan, yang kemudian dijatuhi hukuman mati oleh warga Athena. Sōkratēs memilih mati mempertahankan kebenaran yang diyakininya, juga iman monoteismenya, dan itu membuatnya dijatuhi tuduhan atheos (ateis, alias tidak percaya dewa-dewi). Itu ia pilih ketimbang harus membayar denda atau mengikuti saran para muridnya untuk melanggar hukum, yaitu melarikan diri dari penjara
Oleh : Alfathri Adlin*
JERNIH–Sōkratēs adalah filsuf ‘atipik’ atau “filsuf yang susah dicari padanannya di masa mana pun.” Dia hidup sangat miskin. Bahkan dikatakan bahwa dalam setahun dia hanya mengenakan pakaian yang sama setiap hari. Suatu hari dia berjalan ke pasar, lalu berdiri di depan sebuah toko kelontong, mengamati barang-barang yang dijual di toko itu. Kemudian dia berujar kepada salah seorang muridnya, “Betapa banyak barang yang tidak kubutuhkan di toko itu.”
Selain itu, dia adalah filsuf yang tidak pernah menuliskan ajarannya. Adalah Platōn (kita lebih sering menyebutnya Plato—red) yang menuliskannya. Akan tetapi, entah sudah berapa banyak aliran filsafat yang menyatakan diri sebagai pengikut Sōkratēs, menjadikan ajaran Sōkratēs sebagai landasan pemikirannya, menjadikan filsuf miskin itu sebagai rujukannya.

Tak hanya sampai di situ. Orang yang menjadi rujukan banyak aliran pemikiran dan filsuf kontemporer ini dengan terang-terangan mengatakan bahwa dirinya disebut bijak karena justru dirinya tidak tahu apa-apa. Filsuf yang menjadi rujukan banyak pemikir sesudahnya — bahkan hingga ribuan tahun ini — adalah orang yang menyatakan dirinya tidak tahu apa-apa! “Aku tak bisa mengajari siapa pun ihwal sesuatu, aku hanya bisa membuat mereka berpikir,” tandas Sōkratēs, sebab “Hidup yang tak pernah direnungi adalah hidup yang tak layak dijalani.”
Namun, justru orang seperti inilah yang kemudian dijatuhi hukuman mati oleh warga Athena. Sōkratēs memilih mati mempertahankan kebenaran yang diyakininya, juga iman monoteismenya, dan itu membuatnya dijatuhi tuduhan atheos (ateis alias tidak percaya dewa-dewi), ketimbang harus membayar denda atau mengikuti saran para muridnya untuk melanggar hukum, yaitu melarikan diri dari penjara selama menunggu hukuman mati dengan cara para muridnya menyuap penjaga penjara. Sōkratēs juga tidak takut untuk berkata benar (parrhesia) sekalipun harus menghadapi kematian karenanya, hidup ugahari, dan meninggalkan pesan terakhir kepada muridnya agar melunasi hutang Sōkratēs setelah kematiannya.
Sōkratēs pun menghadapi detik-detik menjelang kematiannya dengan tenang, bahkan tidur nyenyak di malam terakhir kehidupannya, hingga membuat muridnya heran melihat ketenangan gurunya tersebut. Dia pun tak menyimpan kebencian dan tak membolehkan balas dendam. Tak pernah menyalahkan Aristophanes yang telah mementaskan teater di hadapan warga Athena dan isinya berupa fitnah ihwal Sōkratēs sebagai gay yang menyukai dan memangsa pemuda Athena. Sokrates yang dituding atheos (tidak percaya dewa dewi) sebab selalu bersumpah atas nama Tuhan Yang Esa (Ho Theoi), dan juga fitnah bahwa dia telah mengajarkan moralitas baru yang merusak.
Inti pemikiran Sōkratēs (dan Platōn, tentu saja) adalah pengenalan diri (gnothi seauton), serta tak ada pemilahan antara moralitas privat dan moralitas publik. Pada Sōkratēs kita bisa melihat bagaimana wilayah privat dan publik itu tak terpisahkan. Pemisahan kedua hal tersebut adalah ‘temuan’ dan ‘konsep diri’ para filsuf modern. Maksud ‘diri’ di sini bukanlah jiwa, akan tetapi “konstruksi etis yang mengarahkan ucapan dan pikiran” seseorang. Integritas moral ini seringkali tak tersentuh dan terabaikan disebabkan oleh bias Great Divide atau pemilahan atas berbagai hal yang menjadi ciri khas dunia modern.
Gejala Great Divide lazim ditemukan di kalangan filsuf (post)modern, bagaimana terpisahnya antara aksiologi dengan epistemologi, bagaimana terpisahnya kerumitan teoretik di pikiran dengan ketidakberdayaan mengendalikan hasrat, meski terlatih berpikir logis dan kritis. Seringkali hanya terjatuh pada kenyinyiran demi kenyinyiran di media sosial atau WAG misalnya, bahkan tak jarang memberi apologi atas berbagai bentuk kegombalan tindak tanduknya. Karenanya, tak heran, jika sebagian filsuf (post)modern mewacanakan sebentuk pemikiran filosofis ke ranah publik, namun itu terpisah sama sekali dari integritas pribadinya di ranah privat.
Pada diri Sōkratēs, kita masih melihat filsafat sebagai ‘cinta kebijaksanaan’ yang merupakan tekhné tou biou (art of living atau seni menjalani hidup); bukan sekadar olah pikir njelimet dan abstrak. Ada aspek praksis di dalamnya, yaitu pengenalan diri, pengendalian diri, dan latihan mati sebelum mati agar jiwa (psukhe) bisa terlepas dari paku — berupa epithumia (syahwat) dan thumos (hawa nafsu) — yang telah menancapkan jiwa ke tubuh (soma). Dengan filsafat sebagai tekhné tou biou, maka jiwa bisa belajar lebih tenang dan jernih, tanpa ada distorsi dari hasrat yang menempel di tubuh.
Filsafat bukan sebatas permainan rigor (ketat) dan rumit logika serta asah nalar dalam wilayah wacana yang disebar ke publik, untuk kemudian merasa arogan dan takjub pada diri sendiri, lalu tunjuk sana sini melabeli “kamu tidak bernalar, kamu bego, kamu tidak baca buku filsafat,” dan berbagai kesombongan sejenisnya. Philosophia adalah cinta kebijaksanaan dalam arti “bestari dan arif di ranah privat maupun publiknya.” Dalam bahasa Inggris kita biasa menggunakan kata “wisdom”.
Para pembelajar filsafat yang menyimak biografi para filsuf (post)modern tentu akan maklum dengan berbagai ‘kenyelenehan’ gaya hidup para filsuf tersebut. Saya tak perlu paparkan di sini karena akan memancing protes dari banyak pihak yang meyakini bahwa wilayah privat dan publik memang sudah semestinya dipisahkan dan, tentu saja, “jurus jitu argumentum ad hominem.” Belum lagi kriteria moral dan etis yang akan dipermasalahkan berkepanjangan. Well, “bukankah sejarah filsafat (post)modern juga adalah sejarah pertengkaran?” demikian tandas guru filsafat pertama saya (merangkap promotor kedua), yaitu Prof. Bambang Sugiharto.
Akan tetapi, pada diri Sōkratēs, kita masih bisa melihat asketisme, integritas antara yang dia katakan dengan keberaniannya mempertahankan perkataan tersebut, bahkan dengan nyawanya, dan bagaimana dia juga menghormati hukum polis Athena sekalipun hukum itu telah memperlakukannya dengan tidak adil. Menurut Sokrates, tidak mengapa jika kita diperlakukan tak adil, asalkan bukan kita yang malah berbuat tak adil. Bahkan dia pun menolak mentah-mentah usulan dari para muridnya untuk menyogok penjaga penjara agar bisa melarikan diri. Jika itu terjadi, maka hancur sudah seluruh ajaran Sōkratēs ihwal philosophia yang mengajarkan keutuhan dan ketakterpisahan etika di ranah privat dan ranah publik seorang philosophos.
Sedangkan dalam filsafat (post)modern, seringkali nalarlah yang diasah sedemikian rigor dan tajam, mempermasalahkan berbagai asumsi dasar, proposisi, argumen, dan definisi. Namun, seperti apa kehidupan kita di wilayah privat, itu urusan masing-masing. Yang penting di wilayah publik Anda tidak korupsi, tidak menyakiti orang lain, tidak mencuri, tidak memperkosa, tidak merampok dan berbagai tindakan yang melanggar hukum lainnya, maka Anda adalah seorang warga yang baik. Kalau ditambah dengan bisa menulis artikel atau buku filsafat yang rumit? Wah, itu sih lebih baik lagi, karena bisa menghasilkan gelar akademik, kapital simbolik, royalti, memutar modal penerbitan, serta mengharumkan nama almamater dan negara.
Demikian. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, filsafat adalah seni menjalani hidup yang integratif serta latihan mati sebelum mati. Bukan sekadar olah pikir dan silat lidah demi kemenangan berargumentasi. Selain itu, kini, tak jarang filsafat hanya menjadi seni mencipta konsep, menjadi sebentuk intellectual exercise untuk berpikir rigour, seni memberi argumen pada pemikiran filosofis yang saling bertolak belakang satu sama lain, namun toh sama-sama “logis.”
Selain itu, biografi sebagian filsuf (post)modern memperlihatkan bagaimana kenjelimetan teoretik di kepala tak membuat sang filsuf mampu mengendalikan diri di ranah privat. Tetap menaruh dendam kesumat untuk dibawa mati, saling membenci, nyinyir tapi merasa seolah itu adalah praktik berpikir kritis, serta petantang petenteng seolah alam semesta terangkum semua di kepalanya.
Lalu, bagaimana dengan aspek bestari atau arif dalam filsafat serta kehidupan privat seorang filsuf? Oh maaf, Anda berbicara di zaman yang salah. [Inilah.com]