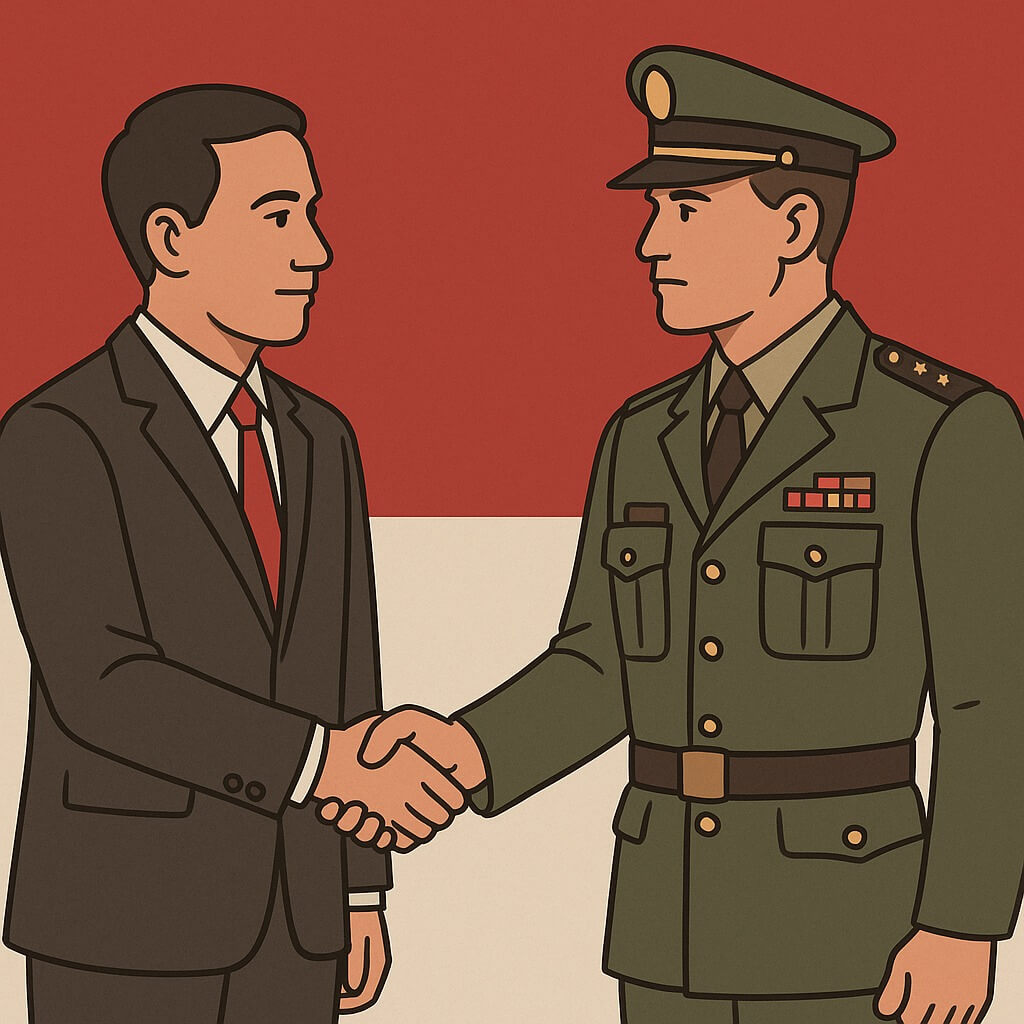
Namun sejarah militer Indonesia tidak sesederhana itu. Dalam era Orde Lama, justru militer-lah yang seringkali menjadi pelindung terakhir republik dari ancaman ideologis dan politis yang sangat nyata. Ketika Presiden Soekarno mulai menjauh dari demokrasi parlementer, dan kekuatan politik seperti PKI semakin dominan, militer tampil sebagai kekuatan penyeimbang.
Oleh : Radhar Tribaskoro*
JERNIH– Dalam sejarah panjang Republik Indonesia, hubungan antara masyarakat sipil dan militer tidak pernah benar-benar sederhana. Selalu ada ketegangan, kecurigaan, bahkan trauma. Namun ada pula solidaritas, pengorbanan, dan kerja sama.
Pada era demokrasi seperti sekarang ini, penting bagi publik untuk meluruskan pemahaman tentang hubungan sipil-militer, agar demokrasi dapat berkembang dalam kepercayaan dan kontrol yang sehat — bukan dalam kecurigaan atau glorifikasi berlebihan.

Salah satu polemik mutakhir mencuat ketika Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggagas program pendidikan karakter melalui pelatihan semi-militer bagi anak-anak yang dianggap “nakal” atau bermasalah secara sosial. Reaksi keras datang dari berbagai lembaga, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), beberapa anggota DPR, dan sejumlah LSM. Mereka menyebut pelatihan militer bukan solusi untuk persoalan sosial sipil, karena institusi militer dianggap tidak paham psikologi anak, keras secara struktural, dan memiliki rekam jejak represi.
Kontroversi lain muncul ketika TNI dilibatkan dalam pengamanan di lingkungan Kejaksaan Agung, sebuah lembaga sipil penegak hukum. Keterlibatan ini pun langsung dicurigai sebagai upaya “campur tangan militer” dalam ranah sipil yang seharusnya dijalankan oleh kepolisian atau pengamanan internal. Apakah kecurigaan itu valid? Apakah militer memang anti-demokrasi secara kodrati? Atau adakah cara yang lebih tepat untuk memahami peran mereka dalam konteks demokrasi yang sehat?
Antara trauma dan kenyataan
Kecurigaan terhadap militer memang bukan tanpa dasar. Selama lebih dari tiga dekade, Indonesia berada di bawah pemerintahan Orde Baru yang dikendalikan oleh kekuatan militer. Sistem dwifungsi ABRI memberi perwira militer posisi dalam birokrasi sipil, politik, dan ekonomi. Represi terhadap kebebasan sipil terjadi secara luas, dari pembungkaman pers hingga pelanggaran HAM berat di Timor Timur, Papua, dan Aceh.
Dalam konteks ini, wajar bila pascareformasi, masyarakat sipil menuntut “sterilisasi” ranah sipil dari pengaruh militer. Pemisahan TNI dan Polri, penghapusan fraksi militer di DPR, dan revisi doktrin militer adalah langkah-langkah penting yang dilakukan untuk membangun demokrasi sipil yang sehat.
Namun sejarah militer Indonesia tidak sesederhana itu. Dalam era Orde Lama, justru militer-lah yang seringkali menjadi pelindung terakhir republik dari ancaman ideologis dan politis yang sangat nyata. Ketika Presiden Soekarno mulai menjauh dari demokrasi parlementer, dan kekuatan politik seperti PKI semakin dominan, militer tampil sebagai kekuatan penyeimbang.
TNI secara aktif membela keberadaan partai-partai Islam dan nasionalis yang nyaris dibungkam. Puncaknya adalah pada tahun 1965, ketika terjadi konflik internal hebat yang kemudian disusul dengan transisi besar kekuasaan ke Orde Baru.
Artinya, militer Indonesia tidak bisa semata-mata dilihat sebagai entitas represif. Dalam berbagai fase sejarah, mereka juga berperan sebagai penyelamat dari kekacauan politik. Dan kini, dalam era pascareformasi, peran militer masih terus mengalami evolusi.
Antara disiplin dan demokrasi
Salah satu kritik klasik terhadap militer adalah bahwa ia adalah organisasi hirarkis, kaku, dan cenderung menolak pluralisme yang menjadi dasar demokrasi. Dalam banyak hal, kritik ini benar. Sistem komando militer dibangun untuk menghadapi ancaman, bukan untuk mengelola perbedaan. Namun menyamakan watak struktural militer dengan kecenderungan politik anti-demokrasi adalah penyederhanaan yang tidak adil.
Militer, dalam konteks modern, bukan lagi lembaga politik. Ia adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Undang-undang telah menempatkan TNI sebagai lembaga yang tunduk pada otoritas sipil. Militer tidak lagi masuk parlemen, tidak memiliki partai, dan tidak mengelola bisnis negara seperti dulu. Bahkan dalam banyak kasus, perwira tinggi TNI memilih untuk pensiun dini bila ingin masuk dunia politik—dan ini sesuai prinsip demokrasi.
Jika hari ini TNI masih menunjukkan ketertarikan untuk membantu sektor-sektor sipil seperti penanggulangan bencana, pengamanan wilayah vital, hingga pembinaan sosial, hal itu tidak serta-merta berarti mereka ingin kembali berkuasa. Bisa jadi itu mencerminkan semangat pelayanan dan nasionalisme yang masih tertanam kuat dalam doktrin mereka.
Pendidikan militer untuk anak “nakal”?
Salah satu isu yang memperlihatkan kekacauan persepsi sipil-militer adalah kebijakan pelatihan karakter berbasis semi-militer untuk anak-anak bermasalah. Mereka disebut “nakal”, “berisiko tinggi”, atau “potensial kriminal”.
Sebagian pihak menilai bahwa membawa mereka ke pelatihan militer akan menambah trauma, memperparah kekerasan struktural, dan tidak menyentuh akar masalah sosialnya. KPAI dan beberapa aktivis HAM menolak keras kebijakan ini, menganggap bahwa solusi sosial tidak bisa didekati dengan cara-cara militeristik.
Namun kita juga harus jujur mengakui bahwa banyak lembaga pembinaan sipil pun gagal mendidik anak-anak ini secara efektif. Di sisi lain, cukup banyak program pelatihan semi-militer di pesantren, sekolah asrama, dan komunitas-komunitas pemuda yang justru berhasil memberikan kedisiplinan, kebugaran, dan rasa tanggung jawab.
Apakah program seperti ini salah? Tidak selalu. Yang perlu dikritisi adalah metode dan pengawasan. Jika pelatihan dilakukan dengan prinsip pedagogis yang tepat, diawasi oleh psikolog anak, dan tidak menggunakan kekerasan, maka disiplin militer bisa menjadi elemen pendidikan karakter yang efektif.
Dengan kata lain, militer bisa hadir dalam ruang sipil — jika peran mereka dibingkai secara sipil dan transparan.
Komitmen moral militer terhadap demokrasi
Contoh paling segar dari keterlibatan militer dalam demokrasi justru datang dari para jenderal yang telah pensiun. Forum Purnawirawan Prajurit TNI muncul pada 2024 sebagai reaksi atas kekacauan etika dan hukum dalam pemilu presiden. Mereka mengajukan delapan butir pernyataan moral, salah satunya menyerukan koreksi terhadap proses Pilpres yang dianggap melanggar prinsip keadilan elektoral.
Mereka tidak meminta kekuasaan, tidak mengusulkan militer mengambil alih pemerintahan, tidak mendesak pembentukan Dewan Revolusi atau semacamnya. Mereka hanya menyuarakan bahwa legitimasi kekuasaan harus dibangun di atas konstitusi, bukan relasi darah atau rekayasa putusan Mahkamah Konstitusi.
Pernyataan ini membungkam tudingan bahwa militer hanya akan bicara bila soal kekuasaan. Forum Purnawirawan menunjukkan bahwa militer Indonesia hari ini punya nurani, dan bersedia menyuarakan kebenaran bahkan jika itu berseberangan dengan kekuasaan yang sedang kuat.
Memahami militer secara proporsional
Menilai militer hari ini harus dilakukan secara proporsional, historis, dan kontekstual. Tidak boleh berlebihan dalam mengultuskan peran mereka, tetapi juga tidak adil jika setiap keterlibatan mereka langsung dicurigai sebagai manuver politik atau ancaman terhadap demokrasi.
Militer adalah bagian dari bangsa ini, dan mereka punya kapasitas teknis, logistik, dan disiplin yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat — asalkan diletakkan dalam kerangka sipil, tunduk pada hukum, dan diawasi secara demokratis.
Kecurigaan yang berlebihan bisa mengasingkan militer dari transformasi. Di sisi lain, keakraban yang membutakan bisa menyeret kembali negara ke pola-pola otoriter. Yang dibutuhkan adalah relasi sipil-militer yang rasional, kritis, dan terbuka terhadap evaluasi bersama.
Sipil dan militer membangun bersama
Demokrasi bukan hanya soal pemilu, partai politik, atau aktivisme sipil. Demokrasi adalah sistem sosial-politik yang melibatkan semua kekuatan bangsa dalam kerangka konstitusi dan hukum. Militer adalah bagian dari itu.
Dalam negara demokratis, sipil memimpin, tetapi militer harus didengar. Sipil membuat hukum, tapi militer yang sering kali menjaga stabilitas agar hukum itu bisa ditegakkan. Sipil mengkritik, militer melindungi. Keduanya saling membutuhkan.
Menolak keterlibatan militer secara mutlak dalam urusan sipil adalah reaksi trauma masa lalu. Tapi masa kini adalah kesempatan untuk menata ulang hubungan itu dalam bentuk baru — relasi setara, transparan, dan berbasis tanggung jawab bersama.
Jika militer bisa bersuara untuk keadilan seperti Forum Purnawirawan, jika tentara bisa membantu anak-anak muda menemukan kedisiplinan baru tanpa kekerasan, jika institusi militer bisa hadir di ranah sipil sebagai mitra dan bukan tuan — maka barangkali kita tengah menyaksikan lahirnya militer baru yang demokratis, konstitusional, dan humanis.
Dan bila masyarakat sipil bersedia membuka diri untuk dialog, maka demokrasi kita akan menjadi lebih kuat. Bukan karena tidak ada perbedaan, tapi karena semua perbedaan itu dikelola dalam rasa saling percaya — bukan curiga terus-menerus. []
* Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia; mantan Sekretaris DPD Gerindra Jawa Barat







