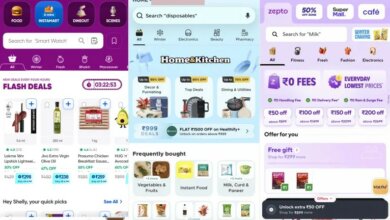PSSI dan Reformasi Setengah Hati, Ketika Kenyamanan Dipertahankan

Kekalahan di lapangan bukan kecelakaan, melainkan konsekuensi dari tata kelola yang dibiarkan rusak. Di balik jargon reformasi, PSSI masih dikuasai politik, kompromi, dan pengurus yang alergi pada perubahan struktural.
WWW.JERNIH.CO – Indra Sjafri diputus kontrak akibat gagal membawa timnas Sea Games 2025 lolos grup. Menyusul kemudian pengunduran diri manajer timnas (yang juga manajer tim sepakbola putra Sea Games) Sumardji, Kombes Polisi yang cukup lama berada di tubuh PSSI.
Peristiwa serentak merupakan buntut dari riak di tubuh PSSI yang tidak satupun meraih prestasi bagus sepanjang 2025. Harapan pecinta sepakbola tanah air sirna ditelan kegaduhan di internal induk olahraga sepakbola nasional itu.
PSSI sudah terlalu lama menjadi rumah nyaman bagi pola-pola lama yang enggan mati: politik klub yang berkelindan dengan kepentingan pribadi, pengurus yang lebih lihai bernegosiasi di ruang rapat daripada membangun sistem sepakbola, serta keputusan-keputusan penting yang berdampak jangka panjang namun dibuat serba reaktif.
Jangan malu mengakuinya—PSSI tidak sedang kekurangan semangat, tetapi kekurangan keberanian untuk berubah secara struktural. Yang kita saksikan hari ini adalah ironi yang berulang: kegagalan di lapangan berjalan seiring dengan kegagalan tata kelola di balik layar.
Masalah mendasar PSSI bukanlah kekurangan talenta pemain, melainkan kepengurusan yang sejak lama bercampur aduk dengan kepentingan politik klub dan bisnis sepakbola. Belakangan mantan pelatih –yang tidak bertanggung jawab karena ngacir pulang ke negerinya- Patrick Kluivert dalam unggahannya di media sosial bilang, PSSI terlalu sarat kepentingan politik. Sayang, Kluivert tak mengelaborasi istilah “kepentingan politik” yang ia maksud.
Banyak posisi strategis diisi oleh figur yang memiliki afiliasi langsung dengan klub atau jejaring kekuasaan lama. Konflik kepentingan pun menjadi keniscayaan, bukan pengecualian. Wajah-wajah lama yang kembali hadir dalam struktur baru seakan menegaskan satu pesan: perubahan boleh dikampanyekan, tetapi kenyamanan lama tetap dipelihara.
Kelemahan lain yang tak kalah serius adalah rapuhnya akuntabilitas dan transparansi komisi-komisi internal, terutama komisi disiplin. Sanksi kerap terasa inkonsisten, lebih sering berujung denda administratif ketimbang pembenahan akar persoalan. Penegakan aturan tampak lentur, mudah ditafsirkan, dan pada akhirnya rawan dipolitisasi. Dalam iklim seperti ini, keadilan kompetisi hanya menjadi jargon, bukan prinsip yang ditegakkan.
Bebeapa eksekutif sungguh tidak tahu dunia sepakbola dengan akar-akarnya. Tetapi paling sering mengobral kata-kata. Dan, ketika suatu saat ditanya kegagalan di Sea Games, di sosial media ia bilang “Tanyakan Saja pada Yang Mengetahui”. Kok bisa? Seakan di pundaknya sudah tidak ada lagi sebuah sikap moral yang disebut sebagai “tanggung jawab”.
Pola pengambilan keputusan pun cenderung reaktif. Pemecatan pelatih di tengah krisis, keputusan tergesa-gesa yang mengorbankan kesinambungan program, hingga kegagalan memaksimalkan momentum FIFA Matchday, menunjukkan absennya perencanaan jangka panjang yang matang. Ketika kesempatan internasional pada November 2025 dilewatkan begitu saja, dampaknya tidak hanya terasa pada kalender pertandingan, tetapi juga pada peringkat FIFA dan kepercayaan publik terhadap arah besar PSSI.
Semua persoalan struktural itu menemukan cerminnya di lapangan. Kekalahan telak Indonesia 0–6 dari Jepang pada Juni 2025 bukan sekadar skor memalukan; ia adalah potret telanjang dari ketimpangan persiapan, kedalaman skuad, dan kualitas manajemen sepakbola. Demikian pula kegagalan melanjutkan mimpi menuju Piala Dunia 2026 setelah kekalahan krusial di fase akhir kualifikasi. Setiap kekalahan besar selalu diikuti kegaduhan internal, perubahan pelatih, dan kegamangan arah.
Pemecatan Shin Tae-yong di awal 2025, lalu eksperimen singkat bersama Patrick Kluivert yang juga berakhir tanpa fondasi kuat, menegaskan satu hal: keputusan non-teknis terlalu sering mengalahkan pertimbangan sepakbola. Ketidakstabilan manajerial ini merusak kontinuitas pembinaan pemain muda, mengacaukan identitas permainan, dan membuat tim nasional seperti proyek jangka pendek yang mudah dibongkar-pasang.
Ketika ditanya kepada para pejabat tingkat atas PSSI itu, semuanya buang badan atau jika tidak, mereka berusaha melerai kegundahan dan kemarahan publik dengan bilang , “Let’s Move On” tanpa menjelaskan seterang-terangnya “apa yang sedang terjadi?”. Seolah masalah dibuang begitu saja zonder proses analisa.
Dalam konteks inilah pertanyaan tentang kompetensi pengurus menjadi relevan. Erick Thohir datang dengan janji modernisasi dan membawa sejumlah nama baru ke dalam struktur PSSI periode 2023–2027, meski tetap berdampingan dengan figur-figur lama. Kehadirannya memberi harapan akan perubahan, tetapi harapan itu tidak otomatis menjelma menjadi sistem. Nama besar tidak serta-merta menghadirkan tata kelola yang besar pula.
Kritik terhadap kinerja komisi internal, inkonsistensi kebijakan, serta keputusan-keputusan yang dipertanyakan menunjukkan bahwa kapasitas teknis dan budaya organisasi PSSI belum berubah secara mendasar. Terlalu banyak posisi strategis masih diisi oleh aktor yang mahir berpolitik organisasi, namun minim rekam jejak dalam pengelolaan sepakbola profesional. Reformasi pun berhenti di permukaan—sebatas rebranding dan narasi—tanpa menyentuh jantung persoalan.
Lalu, apakah Erick Thohir masih diperlukan untuk PSSI ke depan? Jawabannya bukan soal pribadi, melainkan soal struktur. Erick akan tetap relevan bila ia berani menggeser pusat kekuasaan dari figur ke institusi: memperkuat komite teknis dengan profesional independen, membuka transparansi anggaran, menerima audit eksternal, dan membiarkan pengawasan publik bekerja. Namun bila kepemimpinan hanya berfungsi menjaga keseimbangan politik internal dan membagi posisi demi stabilitas suara, maka ketergantungan pada satu figur justru menjadi masalah baru.
Bagi publik, hal itu sama saja tidak mendidik mereka untuk melihat PSSI dengan kacamata sebuah organisasi modern. Bukan kacamata individu dan popularitas.
Reformasi PSSI tidak bisa lagi bersifat kosmetik. Audit independen terhadap kinerja dan keuangan harus dilakukan dan dipublikasikan. Konflik kepentingan wajib dibatasi dengan aturan keras dan masa jeda bagi pengurus yang terafiliasi klub. Rekrutmen posisi teknis harus terbuka dan berbasis kompetensi internasional.
PSSI juga membutuhkan peta jalan sepuluh tahun dengan indikator kinerja yang terukur, bukan target abstrak, bukan juga rencana plin-plan. Kontinuitas kepelatihan harus dilindungi dari intervensi politik sesaat, dan partisipasi publik perlu dilembagakan melalui mekanisme pemantauan independen.
Pada akhirnya, PSSI tidak kekurangan jargon atau tokoh besar. Yang kurang adalah keberanian memutus mata rantai kenyamanan lama. Sepakbola Indonesia tidak akan maju hanya dengan mengganti wajah di baliho konferensi pers. Ia hanya akan bergerak ke depan jika struktur dirombak, kepentingan dipisahkan, dan profesionalisme ditegakkan—tanpa kompromi.(*)
BACA JUGA: Ketua Umum PSSI Menyesal Tak Bisa Kirim Timnas ke Piala AFF