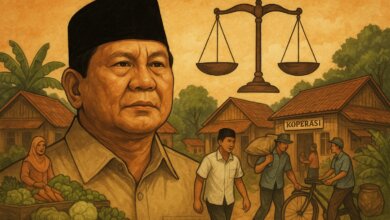Populisme dan Tantangan Pemikiran Kritis GREAT Institute

Populisme tumbuh subur lewat narasi semu yang menyederhanakan masalah kompleks. Narasi semu adalah bahan bakar utama mesin populisme.
JERNIH – Populisme adalah pendekatan politik yang menekankan dikotomi antara “rakyat” yang dianggap murni dan “elite” yang dianggap korup atau jauh dari kepentingan masyarakat. Jan-Werner Müller (2016), seorang teoretikus politik, mendefinisikan populisme sebagai klaim moral bahwa hanya populis yang mewakili “rakyat sejati,” sementara pihak lain dianggap tidak sah. Populisme bukanlah ideologi tunggal, melainkan sebuah gaya atau strategi politik yang bisa digunakan oleh aktor kiri maupun kanan.
Dalam praktiknya, populisme sering menggunakan retorika sederhana, emosional, dan penuh janji besar yang mudah diterima masyarakat, meskipun seringkali tidak didukung oleh kebijakan yang realistis.
Dalam konteks Indonesia, populisme kerap muncul dalam momen pemilu, baik nasional maupun daerah. Contoh nyata terlihat dalam kampanye-kampanye politik pasca-reformasi, di mana citra pemimpin yang sederhana, “anti-elite,” dan dekat dengan rakyat menjadi nilai jual utama.
Beberapa ciri yang dapat dicermati dari praktik populisme politik Indonesia di antaranya personalisasi politik dimana figur pemimpin lebih ditonjolkan ketimbang platform ideologis partai. Kemudian, munculnya retorika anti-elite dalam rupa janji untuk melawan “korupsi elite” atau “pemerintah lama” yang kerap menjadi jualan politik.
Ciri lainnya adalah konotasi dekat dengan rakyat kecil. Mereka mengangkat isu kesejahteraan rakyat bawah, distribusi bantuan, dan citra merakyat (blusukan, bahasa sederhana, simbol budaya lokal). Dan, yang paling terasa adalah praktik polarisasi sosial, mereka memainkan politik identitas dan polarisasi yang dipakai untuk memperkuat dukungan.
DIGITAL POPULISM
Hikayat populisme sendiri sebenarnya tidak muncul dari berbagai fakta empiris. Tidak ada satu orang pencetus populisme, karena ia lebih merupakan fenomena global yang muncul sejak lama. Namun, istilah “populism” pertama kali dipopulerkan pada abad ke-19 melalui People’s Party (Populist Party) di Amerika Serikat yang memperjuangkan kepentingan petani melawan kapital besar.
Secara teori modern, tokoh-tokoh seperti Ernesto Laclau (2005) menekankan bahwa populisme adalah cara membangun identitas politik melalui “rantai kesetaraan” (chain of equivalence) di mana berbagai tuntutan rakyat dikumpulkan menjadi satu narasi besar melawan elite.
Internet dan media sosial mempercepat penyebaran populisme. Ia mampu memancing viralitas emosi. Pesan emosional lebih cepat menyebar dibanding argumen rasional. Ditambah faktor echo chamber dimana algoritma media sosial memperkuat polarisasi dengan menyajikan konten sesuai preferensi pengguna. Ruang digital yang lebih condong menawarkan sesuatu yang bersifat visualisasi memupuk politik meme dan hoaks. Hingga hadirlah narasi semu yang diperkuat dengan konten sederhana namun provokatif. Inilah mengapa populisme di abad ke-21 sering disebut “digital populism.”
Di sinilah kemudian dapat menjadi persoalan, ditambah dengan dangkalnya literasi masyarakat tentang sebuah narasi. Populisme bisa membawa dua wajah, positif dan negatif. Sejatinya ia dapat membuka kanal bagi rakyat kecil untuk menyuarakan aspirasi. Bahkan memberi peluang melakukan koreksi jarak antara rakyat dan elite politik.

Sebaliknya, populisme di tengah rendahnya akal dan lemahnya literasi hanya akan melemahkan rasionalitas publik. Retorika emosional sering menggantikan analisis kebijakan berbasis data. Munculnya narasi semu, dimana populisme kerap menciptakan “musuh bersama” yang sederhana, padahal masalah politik sangat kompleks. Pada akhirnya berujung pada polarisasi. Masyarakat lebih mudah terbelah karena isu identitas dan janji populis.
Seperti yang dikatakan Margaret Canovan, populisme adalah “the shadow of democracy,” bayangan yang selalu mengikuti demokrasi, bisa memperkuat atau justru merusaknya.
POPULISME DAN NARASI SEMU
Narasi semu adalah konstruksi wacana yang tampak meyakinkan, tetapi miskin substansi dan sering kali menyesatkan. Dalam politik populis, narasi semu berbentuk klaim bahwa hanya mereka yang mewakili rakyat sejati. Juga bisa berupa janji penyelesaian instan terhadap masalah kompleks. Dan-banyak terjadi di Indonesia- adalah retorika emosional yang menutupi kekurangan program konkret.
Menurut Jan-Werner Müller, “Kaum populis mengklaim bahwa mereka, dan hanya mereka, yang mewakili rakyat. Semua pesaing lainnya tidak sah.”
Laporan LIPI (2019) mencatat bahwa Pemilu 2014–2019 memperlihatkan peningkatan polarisasi berbasis agama, terutama di media sosial. Narasi semu berbunyi: “Jika bukan dari kelompok kami, maka ia melawan umat/rakyat.”. Sebuah narasi semu yang mengusung politik identitas.
Di banyak daerah ditemukan janji ekonomi instan. Banyak kandidat kepala daerah menjanjikan lapangan kerja besar-besaran, atau penghapusan kemiskinan dalam waktu singkat, padahal data BPS menunjukkan masalah struktural seperti ketimpangan ekonomi dan kualitas SDM tidak bisa diatasi hanya dengan program jangka pendek.
Dan banyak lagi bertabur narasi semu. Sadar atau tidak narasi semu berdampak pada pelemahan kemampuan berpikir kritis. Masyarakat lebih mudah menerima retorika emosional ketimbang analisis data. Narasi semu memperlebar jurang antara kelompok sosial-politik.
Celakanya, data berbicara, berdasarkan survei Katadata Insight Center (2020), 79% masyarakat Indonesia menerima hoaks politik melalui media sosial, yang seringkali berbasis narasi semu. Artinya telah terjadi misinformasi dan hoaks.
Sehingga sungguh tepat jika Ernesto Laclau (2005) bilang, “Populisme memerlukan ‘rantai kesetaraan’ di mana berbagai tuntutan rakyat disatukan dalam satu narasi besar melawan ‘musuh bersama.’ Namun, narasi itu sering bersifat semu karena hanya konstruksi simbolis.”
Bahkan jauh sebelum politik menggunakan narasi semu sebagai bentuk dari populisme, Jean-François Bayart pada 1993 telah meneropong betapa narasi politik di negara berkembang seringkali bersifat “imaginative,” membentuk realitas sosial berdasarkan imajinasi, bukan fakta.
Jadi, narasi semu adalah “senjata utama” populisme yang dapat memperkuat partisipasi politik, tapi juga berbahaya bila tidak dikritisi. Karena itu, peran publik yang kritis, media independen, dan lembaga think tank sangat penting untuk mencegah demokrasi terjebak dalam ilusi retorika.
PERAN GREAT INSTITUTE
Dalam politik modern, peran akademisi, gerakan rakyat (termasuk mahasiswa) maupun lembaga think tank alias pemikir adalah penyeimbang. Terutama dalam hal melawan narasi semu, ketiganya adalah pilar yang saling bersinggungan. Aademisi menciptakan pengetahuan, think tank seperti GREAT Institute mengemasnya, rakyat menyebarkannya.
Namun think tank harus memimpin perlawanan terhadap narasi semu karena mereka punya kombinasi unik: otoritas ilmiah, kemampuan komunikasi publik, dan akses politik.
GREAT Institute memiliki kemampuan strategis dalam melawan narasi semu. Mengapa demikian?
Narasi semu butuh lawan yang berbasis data. GREAT Institute bisa cepat merespons dengan data dan analisis, tanpa kehilangan daya tarik komunikasi.
Lembaga pemikir berada di ruang publik dan ruang kebijakan. Ini adalah alasan tepat yang membedakan posisi akademisi yang kuat di ruang akademis, gerakan rakyat kuat di jalanan, sementara think tank berada di ruang kebijakan yang menentukan arah negara.
GREAT Institute menguasai policy communication: menyajikan riset dalam bentuk singkat (policy brief, infografis, artikel populer) yang bisa menandingi retorika populis. Kemasan komunikasi ini penting untuk meredam narasi tanpa data.
Jangan lupa jika akademisi dianggap terlalu teoretis, dan aktivis dianggap partisan, think tank punya posisi “penengah” yang lebih mudah dipercaya oleh publik maupun elite. Kepercayaan publik lebih condong kepada think tank.(*)
BACA JUGA: GREAT Institute: Panggung Terbuka dan “Ruang Rahasia”, Dua Wajah Dialektika Nasional