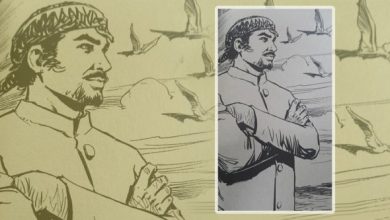Ukur

Itulah yang membuat Si Weregu kian lama makin menghitam. Darah hitam ayam cemani yang dihisapnyalah yang membuatnya demikian. Konon, saat kayu yang mulai dibentuk oleh janggawareng alias buyut dari buyut itu diwariskan kakeknya kepada Ukur, kakeknya bilang untuk tidak memakainya sembarangan
Oleh : Darmawan Sepriyossa
Pengantar:
Setelah jatuhnya Kerajaan Majapahit, ratusan tahun kemudian kerajaan-kerajaan taklukan di seluruh Nusantara bangkit memupuk kekuatan. Yang paling mencorong adalah Kerajaan Mataram, pengklaim pewaris kekuasaan Majapahit. Sementara kekuatan asing yakni Portugis, Belanda dan Inggris, mulai pula datang menancapkan kuku kekuasaan mereka. Masing-masing dengan kerakusan dan kekejamannya sendiri. Pada saat itu, di Tanah Sunda muncul kekuatan yang mencoba menolak penjajahan, dipimpin seorang bernama Dipati Ukur.—
Episode-4
Tangan Ukur meraih tumpukan nasi, mengambilnya secomot sebelum nasi itu dibulat-bulatkannya dalam genggamannya. Nasi yang bagus, pikirnya. Sangat pulen dan tak tercerai berai dalam genggaman. Dicarinya apakah ada sambal terasi atau sejenisnya di bungkusan itu, ternyata tak ada.
Sempat terbersit sedikit rasa kecewa di hati Ukur. Baginya, dan nyaris semua perjaka Sunda saat itu, tak sempurna makan tanpa sambal. Sambal terasi tentu lebih disukai. Apalagi bila terasi itu datang dari Cirebon, dengan bahan baku udang yang dilumat halus sebelum dijadikan terasi.
Nikmat sekali bila nasi yang telah dibuntal-buntal genggamannya itu ia cocolkan ke sambal terasi Cirebon. Tetapi kalaulah tak ada sambal terasi, sambal muncang alias sambal kemiri atau sambal bawang pun jadilah. Ini makan tanpa sambal, deuuuh…
Tapi meski tak ada sambal, cepat juga nasi di bungkusan daun jati itu habis. Ukur tampak menyukai masakan Mataram yang disebut garang asem itu. Rasanya tak membuat lidahnya harus menyesuaikan diri dengan cita rasa Mataram yang cenderung manis. Ia tak bisa menelan sate kambing ala Mataram yang dibumbui dengan aneka bumbu, terutama gula aren dengan proporsi yang dominan.
Buat lidah Ukur, sate kambing cukuplah dengan bumbu cair orang-orang Cina yang disebut kecap, yang rasanya asin itu. Ditambah beberapa potongan bawang merah. Bumbu cair ala Cina itu kini dilihatnya telah ada di berbagai wilayah Mataram. Tetapi tetap saja sebagaimana terasi, kecap buatan orang-orang Cina Cirebonlah yang menurutnya terbaik dan paling enak.
Baru saja Ukur selesai mencuci tangannya di mangkok gerabah, saat telinganya yang terlatih menangkap bunyi kecil namun tak lazim. Semacam bunyi kaki yang berjingkat hati-hati, mengendap-endap agar tak didengar orang. Dan bukan dari satu titik! Ukur memperkirakan paling tidak bunyi itu terdengar dari tiga titik, seolah mengepung posisinya saat ini.
Ukur tahu, benteng Keraton Mataram terlalu tinggi untuk dimasuki para pencoleng kelas teri. Jadi, kalau ada yang mengendap-ngendap ke sini dan berhasil melompati benteng lebih dulu, tentu pencoleng itu bukan sembarang orang. Orang itu pasti punya ilmu kanuragan yang bisa diandalkan. Atau sebaliknya, justru orang-orang penghuni bentenglah yang kini berada mengitarinya dalam persembunyian mereka itu. Hal itu bukan mustahil mengingat bukan sekali dua Ukur berhadapan laga dengan mereka. Entah mengapa, Ukur merasa cukup banyak para penghuni Keraton Mataram ini yang tak menyukainya. Entah sebab apa.
Seolah tak ada apa-apa Ukur melipat tangan kampretnya sampai ke siku, yang akan memudahkannya bergerak bila perlu. Pelan pula ia berdiri tapi dengan sikap seolah tak peduli. Bagaimana pun Ukur tahu, biarlah orang-orang yang mungkin tengah mengincarnya itu hanya tahu bahwa dirinya hanya seorang yang kekenyangan setelah menghabiskan nasi sebungkah besar dalam bungkusan daun jati. Sama sekali tak ada perlunya ia menunjukkan sikap bersiaga yang justru akan membuat para pengintipnya waspada.
Tiba-tiba, dengan iringan teriakan yang terdengar penuh dendam, Ukur merasakan desir angin kuat dari sebelah kiri belakang posisinya. Ukur menduga itu sabetan parang, menilik desir yang biasa ia hadapi.
“Modaaar kowe!”
Kira-kira dua jengkal lagi parang itu akan melahap daging bahu kirinya, Ukur segera menjatuhkan diri sambil berbalik ke belakang. Parang itu lewat sekitar sejengkal dari arah bahunya, memperlihatkan pemegangnya, seorang berpakaian hitam-hitam dengan kedok menutupi mukanya, tampak hilang keseimbangan.
Refleks sudut mata Ukur melihat kaki yang menapak tak sempurna akibat serangan yang luput tak terduga. Kini giliran kakinya membabat kaki-kaki kehilangan keseimbangan itu dengan jurus ‘tejeh kuda beger mindo’.
“Heup ah!” teriak Ukur. Kakinya yang terlatih membabat tulang kering lawan. Seketika, dengan teriakan kaget lawannya tumbang, tersungkur sebelum cepat membalikkan badan untuk berdiri.
“Bruuk!”
Ukur bermaksud segera menghabisi penyerangnya. Ia melihat dagu lawan yang tengah jatuh itu terbuka, seolah meminta untuk ditendang sekerasnya. Namun belum juga kakinya bergerak, dari samping kanannya seorang berpakaian serupa dengan lawannya yang terjatuh mengayunkan goloknya, menebas kepala Ukur dari atas ke bawah.
“Rasakan kau, Sunda!”
Ukur terpaksa melakukan gerakan suliwa, menjatuhkan badannya hampir menempel tanah guna menghindari tebasan golok tersebut. Senyampang itu, kedua tangannya mengambil salah satu pergelangan kaki lawan, memelintirnya sekerasnya sebelum melancarkan sebuah sepakan keras ke pergelangan kaki yang tidak sedang ia pelintir. Bersamaan dengan hantaman kaki itu, tangannya melepas kaki yang tadi ia pelintir kuat-kuat.
“Kau yang justru harus rasakan, Jawa!” Mendengar perkataannya sendiri itu, Ukur nyaris tertawa sendiri. Lucu sebenarnya. Kelakuan dirinya dan lawan-lawannya ini tak ubahnya kelakuan bocah. Mengejek dengan sesuatu yang tak layak dijadikan bahan ejekan. Apa salahnya jadi orang Sunda? Apa pula sialnya lahir sebagai orang Jawa? Yang jelas, dengan mengejeknya dengan sebutan ‘Sunda’ itu, Ukur jadi bisa mereka-reka siapa lawan-lawan yang tengah ia hadapi.
Belum juga Ukur menyiapkan kepalan untuk menghantam siapa saja dari dua orang lawannya itu yang menyerangnya duluan, dari samping kanannya sebuah tendangan deras menuju lambungnya.
“Syaat!”
Ukur sempat menggerakkan tangan kanannya, menangkis tendangan itu. Hanya karena posisinya kurang menguntungkan untuk menahan serangan dari arah tersebut, tak urung ujung kaki penyerangnya sampai juga mengenai lambungnya.
“Duk!”
“Kurang ajar!” Ukur mendesis. Benar tendangan itu tidak membuatnya terluka dalam, tetapi tetap saja menerima tendangan bukanlah hal yang mengenakkan.
“Itu baru bayaran buat apa yang kau lakukan pada temanku. Sebentar lagi kau akan menerima banyak rentenya, Ukur!” Orang tadi berkata setelah sebelumnya mengekeh beberapa jenak. Bola matanya yang tak tertutup topeng berkilat jahat.
Sudah ada orang ketiga yang mengeroyoknya malam ini. Ukur sadar, dengan diserang bertiga dan sejak awal sudah bermain senjata, alhasil ketiga cecunguk ini benar-benar serius ingin menghabisinya. Dia tak bisa hanya mengelak serangan.
Sudah saatnya ia menyerang, bahkan dengan serangan serius yang mematikan. Tak ada salahnya kalau pun salah seorang dari mereka yang menyerangnya perlaya. Toh mereka pun tak tampak setengah hati untuk menghabisinya.
Pelan-pelan Ukur menarik tongkat kayu Weregu dari pinggangnya. Belum saatnya menghunus keris Panunggul Naga yang selalu membantunya membereskan masalah sejenis. Belum, cukup si Weregu Hideung itu saja yang akan ia gunakan untuk melawan golok dan parang para durjana ini.
Apalagi Ukur sadar, tongkat pendek sepanjang dua jengkal itu dengan gampang akan dipandang enteng siapa pun lawannya, akan membuat mereka jauh dari waspada. Wajar bila semua orang akan mempertanyakan apa keistimewaan tongkat Weregu yang telah menghitam dimakan usia itu?
Padahal, kalau saja mereka tahu betapa sulitnya syarat untuk menjaga si Weregu Hideung itu tetap di sampingnya, siapa pun tak akan bisa menganggap Weregu itu sekadar kayu biasa. Tak hanya mewiridkan Surat Al-Falaq sebanyak 99 kali di setiap malam Jumat sambil terus mengelus si Weregu, setiap Maulud Ukur juga harus memandikan Si Weregu dengan darah ayam cemani.
Tahukah apa itu ayam cemani? Ayam berbulu hitam, berdaging hitam dan berdarah juga kehitaman. Itulah yang membuat Si Weregu kian lama makin menghitam. Darah hitam ayam cemani yang dihisapnyalah yang membuatnya demikian. Konon, saat kayu yang mulai dibentuk oleh janggawareng alias buyut dari buyut itu diwariskan kakeknya kepada Ukur, kakeknya bilang untuk tidak memakainya sembarangan.
“Maneh nyaho saha ari Aria Brajadenta dina wayang golek?” tanya kakeknya. “Tahukah Kau, Cu, siapa Aria Brajadenta dalam jagat pewayangan?”
Ukur mengangguk. Setahu dia, Raden Gatutkaca memiliki beberapa paman yang menyurup dalam anggota tubuhnya. Mereka adalah para denawa alias jin raksasa yang gagah perkasa, sakti mandraguna bernama Brajamusti, Brajadenta, Brajawikalpa dan Brajalamatan.
“Nah, dalam kayu Weregu ini hidup jin sejenis Aria Brajadenta tadi. Maka hati-hatilah.”
Prosesi pewarisan Weregu Hideung itu sesederhana itu. Hanya setelah pemberian itu kakek memintanya melakukan shalat dua rakaat. Shalat hajat, memohon agar mampu menerima warisan itu dengan amanah.
“Ayo konco, jangan kepalang. Ini soal hidup dan mati kita. Pilihannya hanya Si Sunda ini yang mati, atau kita yang akan dihabisi junjungan kita karena gagal. Ingat pula hadiah yang akan kita terima kalau bisa menamatkan riwayat Si Sunda keparat ini,” salah seorang di antara orang-orang bertopeng itu berteriak, menyadarkan Ukur dari lamunan sekejapnya.
Seolah mendapatkan tenaga tambahan, serentak dua orang di antara tiga penyerang bertopeng itu merangsek Ukur. Hanya orang yang tadi berteriak, yang tampak jelas merupakan pemimpin dari ketiganya, yang diam di tempat. Tapi terhadap dia pun Ukur tak bisa lengah, karena jelas pimpinan pengeroyok itu hanya diam dalam upayanya mencari celah untuk menyerang.
Seorang menyerang Ukur dengan tendangannya, terlontar keras ke arah dagu. Ukur merasa tak harus melakukan gerakan nyingcet hanya untuk serangan seperti itu. Ia hanya menarik kaki kanannya ke belakang dengan tangan melakukan gerakan kelid, yang membuat dagunya yang menjadi sasaran berjarak cukup jauh dari kaki lawannya.
“Wuuuusss!”
Dari kekuatan anginnya, Ukur tahu dagunya mungkin saja bisa ambrol keluar dari persendian rahangnya jika tendangan itu mendarat telak. Namun kini, dengan lolosnya dagu itu otomatis kaki lawannya mengangkang terbuka, membiarkan selangkangan dan ‘burung kondor’nya luput tanpa penjagaan.
Alhasil, dengan gerakan yang sukar diikuti mata awam, tangan kanan Ukur yang tadi menggenggam Weregu segera melontarkan batang kayu itu ke tangan kiri. Dengan cepat, tangan kanan yang kini terbuka itu bergerak menuju selangkangan lawan yang terbuka, melakukan gerak kepret dengan kekuatan penuh.
“Plak!”
“Auuuuuuuuuuung!” Lawannya menjerit dengan lengkingan keras. Bagaimana tidak, ia merasa telor burung kondornya pecah berantakan. Selain rasa mulas yang tak terkatakan, kepalanya pun seketika gelap. Ia sempat menghunjam tanah dengan kepala jatuh lebih dulu sambil memegangi bagian burung kondornya yang entah bagaimana nasibnya itu. Lalu diam tak bergerak, setidaknya pingsan saat itu juga. [bersambung]