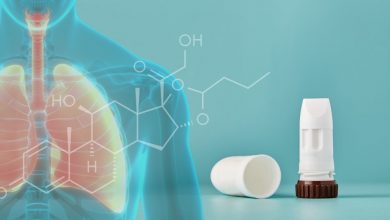Tentang Wabah, Zoonosis, dan Dunia yang (akan) Selalu Dikalahkan Pandemi

Kini, satu-satunya sains yang pasti adalah ketika vaksin Covid19 ditemukan. Dan belum ada sampai hari ini.
Oleh : IGG Maha Adi*
“Gentlemen, it is the microbes who will have the last world.” –Louis Pasteur
“Either we learn to live together or we die together.” – I.F. Stone
“Satu-satunya konspirasi adalah kita dengan keserakahan kita yang absurd untuk melepaskan wabah ini.”—
Nama dokumen itu WHO R&D Blueprint. Isinya banyak, antara lain daftar pandemi global yang mereka waspadai dan diberi prioritas tinggi untuk dimusnahkan. “Disease X,” ada di urutan terakhir dalam daftar. Agar paralel, patogennya mesti juga disebut “Pathogen X.”
Bill & Melinda Gates Foundation dan PwC membantu menyusunnya. Ini sejenis penyakit dunia yang misterius, imajiner, tapi jelas bukan daftar konspiratif untuk memusnahkan manusia. Peluang munculnya pandemi baru selalu ada dan daftar itu sebagai pengingat sekaligus peringatan dini untuk kita, bahwa tidak ada yang dengan pasti mampu menunjuk locus dan tempus delicti berikutnya. Setiap pandemi mirip dengan gempa bumi yang selalu mengejutkan saat terjadi, lalu kita berusaha mempelajari apa saja yang ditinggalkannya untuk mengurangi risiko dari yang berikutnya. Setidaknya begitu coping mechanism Covid-19 sampai hari ini. Tugas WHO adalah menggerakkan sumber daya kesehatan global untuk mengantisipasi dan menghentikan X.
Disease X itu benang merah dari ketiga buku tentang pandemi global ini: ‘Spillover’ dari David Quammen, ‘The Next Pandemic’ yang ditulis Ali S. Khan dan ‘The Coming Plague’ karya Laurie Garret. Ada beberapa buku lain yang sama tebal dan melelahkan untuk dibaca. Dan ciri umum buku bersubjek pandemi ada pada ketiganya, yaitu karakter alarmist yang muram, karena jawaban yang suram atas dua pertanyaan yang mereka ajukan: apa yang telah terjadi & yang akan dilakukan dunia? Walaupun demikian, ketiganya adalah penulis sains yang luar biasa, satu orang diantaranya mantan direktur di CDC Amerika Serikat.
Zoonosis
Quammen, Khan, dan Laurie secara meyakinkan memperingatkan kita akan tibanya Disease X, Pathogen X, seperti orasi Bill Gates pada 2015. Basis peringatan itu sederhana, yaitu perulangan pandemi dan ketakberdayaan dunia menghadapinya–terutama pandemi zoonosis.
Selain virus, sumber pandemi zoonosis adalah bakteri, cacing, jamur, protista dan prion yang lebih kecil dari virus. Mari kita deretkan sebagian epidemi dan pandemi penyakit karena zoonosis ini: Flu Spanyol, AIDS, SARS, Ebola, cacar monyet, hantavirus, anthrax, demam berdarah dan demam berdarah Bolivia, demam Lassa, virus Nipah, Marburg, TBC sapi, flu burung, virus West Nile, scrub typhus (tsutsugamushi), dan influenza. Memang benar dunia berhasil mengatasi patogen virus pada cacar air dan polio, bahkan mendeklarasikan zero polio. Namun keduanya bukan zoonosis karena hanya menyerang manusia, sehingga vaksin massal bisa menghentikannya.
Sejarah wabah
Epidemi atau pandemi selalu kembali. Uraian yang cukup rinci tentang epidemi pertama, datang dari sejarawan Yunani Thucydides ketika wabah menyerang Athena 430 SM. Dari deskripsi yang ditulisnya sebagai korban, epidemi itu bisa jadi cacar air atau campak yang juga membunuh 4 ribu tentara Yunani.
Kecamuk wabah ini telah menurunkan moral orang Athena menghadapi Perang Peloponnesia yang sedang berkecamuk. Dan Sparta mengalahkan mereka. Ada lagi catatan wabah malaria yang menyerang Roma sekitar 300 SM, dan tahun 165 Masehi giliran cacar air menghabisi sebagian tentara mereka di Parthia (Iran Kuno).
Setelah itu, masih banyak epidemi lain di di Eropa dan Jepang. Lalu terjadilah ledakan besar Black Death Kedua yang menghantui seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Asia selama 5 abad (1346-1844). Pandemi ini diperkirakan menewaskan 100-125 juta penduduk dunia. Baru saja dunia mendeklarasikan dirinya bersih, tak sampai 80 tahun kemudian flu spanyol menyerang pada 1918-1919; 50 juta orang tewas di seluruh dunia, dengan 675 ribu orang diantaranya di Amerika Serikat.

Sepanjang catatan sejarah itu, tidak ada yang menyebutkan nama obat atau vaksin yang terbukti efektif. Para dokter atau tabib mencoba apa saja yang mungkin. Juga para pendeta. Saat pandemi Black Death Kedua, pemeluk Kristen dan Islam digambarkan memenuhi gereja dan mesjid memasrahkan hidupnya pada kekuatan doa.
Menengok Darwin
Teori Evolusi Charles Darwin mengatakan semua mahluk hidup, tak terkecuali virus, ber-evolusi melalui seleksi alam. Tujuan evolusi adalah mempertahankan diri dan berkembang biak. Sifat intrinsik sekaligus inheren mahluk hidup ini bertahan melalui adaptasi terhadap lingkungan, agar mereka lolos seleksi. Virus selalu beradaptasi dengan inangnya; bila sang inang tak mampu menghidupinya lagi ia akan meloncat ke inang baru, memulai evolusi dalam variasi kecil yang dapat diwariskan, yang meningkatkan kemampuannya untuk bersaing, bertahan hidup dan bereproduksi.
Orang mengenal mutasi gen dan kromosom sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Virus Covid-19 diketahui telah bermutasi dalam tiga tipe berbeda A,B, dan C. Ilmu pengetahuan memberi tahu bahwa pertarungan virus vs inang ini abadi. Ekpresi kemenangan Covid-19 adalah penyakit bahkan kematian yang diderita sang inang, sedangkan kemenangan sang inang tak selalu ditandai kematian bagi Sang Virus karena ia bisa bersembunyi. Survival of the fittest.
Faktor pendorong epidemi dan pandemi itu bisa macam-macam: kemiskinan, instabilitas politik, pemanasan global, kerusakan hutan, ketidaksiapan infrastruktur kesehatan, lalu lintas manusia dan barang, faktor politik-ekonomi dan kepemimpinan.
Untuk zoonosis, faktor utamanya adalah hubungan manusia dengan satwa selama ribuan tahun. Hubungan ini didominasi oleh hubungan instrumental yang berkarakter satu arah. Pihak pertama yaitu manusia, menganggap keberadaan yang lain hanya bermakna—yaitu satwa liar atau domestikasi—sepanjang berguna baginya. Sebagai instrumen, manusia memperlakukan satwa secara praktis dan simbolis. Dalam hubungan praktis, kita memburu, memakan, mendomestikasi atau menjualbelikan satwa. Pada hubungan simbolis, manusia memberikan makna supra-practical. Kita menjadikan satwa lambang 12 zodiak dan 12 shio, bahkan dewa-dewa pada berbagai kebudayaan kuno.
Dan betapa kita juga terdorong oleh imajinasi kekuatan mistis binatang dengan memujanya atau membunuhnya sembari berharap kekuatannya mengalir melalui darah dan tulangnya. Atau alasan yang lebih superfisial dan absurd: memakan binatang langka semata-mata karena kelangkaannya. Semakin langka seekor satwa, para tabib (cum pedagang) ikut membumbui bahwa semakin banyak bagian tubuhnya yang sangat berkhasiat.
Dan 7,7 miliar manusia itu terlalu banyak untuk Bumi ini. Kita berkembang, merangsek kemana saja, mengubah apa saja untuk kepentingan kita. Hutan, belukar, sungai, laut kita taklukkan dan kuras. Manusia lalu berusaha menjadikan satwa liar sebagai hewan piaraan di rumah, hiburan di taman satwa, teman klangenan yang bikin hati adem tentram, memeluk, merangkul bahkan tidur bersama mereka sembari merekayasa lingkungan dan makanannya; harimau, ular, orangutan, burung, monyet, kamelon, iguana, penyu, atau apa saja berkeliaran di halaman belakang. Cepat atau lambat, virus-virus itu meloncat dari reservoir hosts mereka ke manusia. Itulah awal zoonosis.
Politik pandemi
Apakah pandemi memampukan manusia menghadapinya? Seratus tahun setelah virus Spanyol, para pakar dalam buku-buku ini khawatir tak ada data yang menunjukkan bahwa kita layak optimistis. Dan akar penyebabnya berada ada wilayah lain: di ruang-ruang kantor para politikus, birokrat, lembaga kesehatan, dan militer.
Khan membahas tentang urgensi kebijakan yang pro pengurangan risiko pandemi pada pemerintah nasional, WHO dan PBB. Laurie menulis dengan cemas tentang rendahnya prioritas menghadapi pandemi, kurangnya dana, sumber daya manusia, fasilitas kesehatan di Amerika Serikat dan peranan cepat tanggap pihak militer.
Data sains telah dipaparkan, tapi banyak sekali pemerintah yang abai. Apakah mereka antisains? Soalnya bukan anti atau pro, tapi prioritas. Dimana mereka harus mengalokasikan sumber daya, berapa besar dan luas, apabila pandemi tak kunjung menyerang, misalnya dalam 30 atau 40 tahun? Alokasi ini bisa bernilai ratusan juta dolar per tahun. Tambahan pula, ada keyakinan kuat atas kualitas pelayanan kesehatan yang semakin baik, sehingga kewaspadaan pun menurun.
Tapi menyesal tak ada gunanya. Kini, satu-satunya sains yang pasti adalah ketika vaksin Covid19 ditemukan. Dan belum ada sampai hari ini. Para politikus lantas dihadapkan pada situasi sulit yang sama meresahkannya: kebangkrutan ekonomi dan kerusuhan sosial. Pemerintah harus memilih opsi-opsi yang ada, tentu saja dengan hati-hati, untuk menyelamatkan ekonomi di depan mata dan sementara waktu perlu “mengesampingkan” beberapa pertimbangan sains yang “paling tidak pasti.” Itulah sebabnya tak semua negara mengambil langkah sama: Swedia dengan herd immunity kontras dengan Cina yang menerapkan lockdown, ada pula Thailand di sisi lain dengan relaksasi social distancing. Mana diantara ketiganya yang kita sebut antisains? Apa alasannya?
Bahkan pendirian Presiden Trump dapat dimaklumi jika kita mempelajari “skandal” vaksin. WHO pernah menolak vaksin Ebola rVSV-ZEBOV yang ditawarkan penemunya dengan alasan terlalu prematur. Vaksin ujicoba itu akhirnya tetap diproduksi Merck lalu dipakai di Afrika. Dan ampuh. Memang tak sepenuhnya salah lembaga kesehatan dunia itu, karena protokol ujicobanya semakin ketat setelah sebelumnya kena skandal vaksin meningitis buatan Pfizer pada 1996 yang menewaskan 11 anak-anak Afrika.
Presiden Trump mungkin saja tukang omong yang rajin nge-tweets dengan lobus parietal sedikit korslet, sehingga semua informasi lewat begitu saja tanpa ditapis di kepalanya, tapi tak lantas ia bisa kita bilang antisains. Selama sains belum sampai pada kepastiannya (alias belum ada vaksin Covid19), Presiden seperti Trump akan bertanya apakah disinfektan atau penyinaran UV adalah obat alternatif. Untuk sebagian besar orang, pertanyaan itu terdengar bodoh tetapi yang bodoh tak serta merta antisains.
Ia tak mengabaikan sains tapi ingin sains secepat mungkin membantunya. Trump mungkin akan bersikap “agak ceroboh” dengan menerima tawaran vaksin dalam tahap apapun, selama ia bisa diyakinkan bahwa itu akan memusnahkan Covid19. Ia mungkin akan memaksa FDA untuk mempercepat izinnya. Hari ini, ekonomi Amerika adalah prioritas pertama baginya: 35 juta orang Amerika Serikat terdaftar menganggur karena Covid-19! Dan sebagai politikus, samar-samar dia mendengar lonceng kekalahannya pada Pemilu November nanti.
Dan lihat saja seluruh grafik pendugaan penyebaran Covid19 di Amerika. Tak ada yang sungguh-sungguh sama tergantung asumsinya. Ilmuwan mungkin berhati-hati sampai yakin aman, tapi bila waktunya yang aman itu? Grafik mana yang lebih dipercaya oleh Presiden seperti Trump atau Joko Widodo? Dan seorang Presiden atau Perdana Menteri setiap hari harus menghadapi risiko berdimensi banyak dan memilih di antara opsi yang tersedia, yang mungkin berbahaya. Ingat juga akar kultural, historis dan filosofis sebagai grundnorm—dalam hal Amerika, ini berarti mempertimbangkan nilai liberalisme dan kapitalisme yang tumbuh dan mempengaruhi cara pandang dan pengambilan keputusan publik.
Covidiot
Tetapi, jika kebijakan relaksasi diartikan membiarkan masyarakat keluar rumah atau bepergian tanpa mematuhi protokol—tidak memakai masker, tak mengatur jarak aman, tidak melakukan tes atau membawa surat bebas Covid19, tetap membuka toko non-pangan, atau berkerumun hanya untuk melihat penutupan restoran seperti di Sarinah—maka itu bukan tanda antisains, tetapi tanda terang benderang dari kelemahan kepemimpinan nasional atau daerah dalam mengelola krisis. Tentu saja situasi ini sulit. Siapa bilang semua ini gampang? Karena itu kita menggelar Pemilu/Pemilukada berbiaya puluhan triliun agar merasa pasti bahwa yang terpilih akan menuntaskan masalah kita. Oh ya, soal kumpul-kumpul di Sarinah itu cuma menunjukkan Covidiot nyata adanya. [ ]
*Mantan jurnalis majalah TEMPO, National Geographic, dan lain-lain