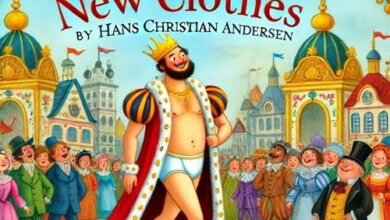Jika Prabowo kini ingin memperbaiki Whoosh, maka langkah pertama bukan menalangi, tetapi mengembalikan rasionalitas publik atas proyek tersebut. Itu berarti membuka angka, membuka kontrak, membuka struktur biaya, mengaudit jalur rente dan penggelembungan, mengevaluasi proyeksi permintaan secara objektif, dan mengakui bahwa pilihan skema pembiayaan awal adalah sebuah kegagalan desain yang harus dicatat sebagai pembelajaran negara, bukan disapu di bawah karpet. Jika rasionalitas dipulihkan, Whoosh tidak harus menjadi simbol kesalahan. Ia dapat menjadi simbol koreksi. Dan itu jauh lebih berharga bagi bangsa ini daripada kebanggaan yang dibangun dari penyangkalan.
Oleh : Radhar Tribaskoro*
JERNIH– Ketika Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh, yang sedang dibicarakan bukan hanya soal teknis pembiayaan. Yang sedang bergeser adalah batas antara apa yang dipahami sebagai tanggung jawab negara dan apa yang merupakan risiko bisnis dari keputusan politik masa lalu. Pertanyaan yang muncul kemudian bukan semata “siapa yang membayar siapa”, tetapi apakah negara masih memiliki kemampuan untuk memperbaiki keputusan yang keliru tanpa sekaligus membenarkan keliru itu sendiri.
Proyek Whoosh sejak awal bukan dirancang sebagai proyek negara dalam pengertian fiskal. Ia diperkenalkan sebagai proyek B2B, sebuah kerja sama antarperusahaan, agar tidak membebani APBN dan agar publik mempercayai bahwa proyek ini memiliki kelayakan bisnis. Narasi bahwa proyek ini tidak akan mengambil uang rakyat bukan klaim tambahan; ia adalah fondasi legitimasi dari keseluruhan proyek. Karena di bawah struktur itulah negara meyakinkan publik bahwa kereta cepat tidak akan menjadi monumen biaya tinggi yang kemudian harus ditanggung generasi berikutnya.
Namun, fakta di lapangan memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Proyeksi pendapatan dari penjualan tiket tidak sebanding dengan biaya operasional dan kewajiban pembiayaan. Biaya konstruksi meningkat, bunga pinjaman berjalan, dan struktur pemasukan tidak mampu menutupinya. Kereta tersebut dapat terus berjalan, tetapi beban finansialnya tidak pernah berdiri pada kakinya sendiri. Pada titik ini, pertanyaan tentang siapa yang menanggung kekurangan itu menjadi pertanyaan yang tak dapat dihindari.
Prabowo berada dalam posisi yang tidak sederhana. Ia mewarisi sebuah proyek yang sudah berjalan dan dipromosikan sebagai kebanggaan nasional. Dalam politik, membatalkan atau menolak proyek semacam ini sering dibaca sebagai tindakan anti-modernitas, anti-pembangunan, atau anti-nasional. Ia harus berhati-hati dalam memastikan bahwa tindakannya tidak dibaca sebagai pemutusan kontinuitas politik yang terlalu tajam. Namun justru di sinilah terletak tantangan kenegarawanan: membedakan kontinuitas yang diperlukan dari kesalahan yang harus diperbaiki.
Menggunakan APBN untuk menanggung utang Whoosh berarti mengesahkan kesalahan desain awal proyek itu sendiri. Jika pemerintah memasukkan utang BUMN yang timbul dari keputusan bisnis ke dalam beban fiskal negara, maka negara sedang menormalisasi gagasan bahwa risiko privat dapat selalu diatasi dengan uang publik. Impunitas kebijakan tidak pernah disebut dalam peraturan, tetapi ia muncul melalui pola tindakan: ketika keputusan yang salah dilindungi, ketika perhitungan yang tidak matang ditutupi, ketika perencanaan yang buruk ditebus dengan dana rakyat.
Di titik inilah rasionalitas politik mulai mendominasi rasionalitas ekonomi. Yang dipertimbangkan bukan lagi apakah langkah itu tepat dalam kerangka keberlanjutan fiskal, melainkan apakah ia memudahkan stabilitas politik jangka pendek, apakah ia menjaga harmoni koalisi, apakah ia menghindarkan gesekan dengan figur yang berpengaruh dalam pemerintahan sebelumnya. Namun sebuah negara tidak dikelola hanya dengan logika stabilitas politik. Negara bertahan melalui kemampuan untuk mengakui dan mengoreksi kesalahan. Bukan menundanya. Bukan menutupinya.
Jika proyek Whoosh ingin diperlakukan sebagai investasi sosial, maka konsistensi logika harus dipulihkan. Investasi sosial adalah proyek negara. Proyek negara menggunakan pembiayaan negara. Dalam hal ini, penawaran Jepang—yang memberikan skema bunga rendah dan tenor panjang—adalah proposal yang paling rasional bagi negara. Namun penawaran itu ditolak bukan karena pertimbangan ekonomi, tetapi karena pertimbangan politik: keinginan menunjukkan bahwa Indonesia mampu membangun infrastruktur besar. Namun, keinginan untuk menunjukkan “kedaulatan ekonomi” justru menghasilkan biaya fiskal yang jauh lebih berat.
Jika Prabowo kini ingin memperbaiki Whoosh, maka langkah pertama bukan menalangi, tetapi mengembalikan rasionalitas publik atas proyek tersebut. Itu berarti membuka angka, membuka kontrak, membuka struktur biaya, mengaudit jalur rente dan penggelembungan, mengevaluasi proyeksi permintaan secara objektif, dan mengakui bahwa pilihan skema pembiayaan awal adalah sebuah kegagalan desain yang harus dicatat sebagai pembelajaran negara, bukan disapu di bawah karpet.
Mengoreksi kesalahan tidak sama dengan menghukum masa lalu. Tetapi menutupi kesalahan adalah jalan menuju pembusukan negara. Negara yang tidak dapat berkata “di sini kita salah” akan selalu terjatuh pada pola yang sama: kegagalan yang diulangi dalam bentuk yang berbeda, tetapi dengan konsekuensi yang semakin besar. Dalam bahasa sistem, negara kehilangan kemampuan belajar. Dan negara yang tidak belajar akhirnya kehilangan legitimasi, karena legitimasi tidak lahir dari kemenangan atau pembangunan semata, melainkan dari kemampuan memperbaiki diri.
Mengembalikan rasionalitas Whoosh berarti mengakui bahwa sebagian besar kebanggaan yang dibangun di atasnya adalah kebanggaan simbolik, bukan kebanggaan struktural. Kereta itu dapat tetap berjalan. Ia dapat membawa penumpang setiap hari. Tetapi narasi yang menyertainya tidak boleh dibangun dari penyangkalan atas fakta. Ia harus dibangun dari transparansi, koreksi, dan penataan kembali struktur biaya. Jika negara memutuskan untuk mendukung Whoosh, maka Whoosh harus menjadi proyek negara yang rasional, bukan proyek politik yang ditutup dengan uang rakyat.
Kita pernah mengalami masa ketika kesalahan negara ditutup dengan kekuasaan, bukan dibetulkan dengan pengetahuan. Kita tahu ke mana arah jalan itu. Ia bukan jalan pembaruan. Ia adalah jalan stagnasi yang disamarkan sebagai kemajuan. Rasionalitas bukan sekadar perhitungan angka. Rasionalitas adalah kemampuan mengatakan: “Ini bukan tentang salah atau benar, tetapi tentang cara kita memperbaiki yang salah agar masa depan negara tidak menjadi beban dari kesalahan hari ini.”
Prabowo tidak perlu malu mengakui bahwa skema pendahulunya keliru. Tidak ada negara maju yang lahir dari kontinuitas membabi buta. Jerman pasca-perang bangkit karena ia berani mengakui kesalahan masa lalunya. Jepang mereformasi ekonomi karena ia bersedia meninggalkan struktur yang tidak efisien. Korea Selatan bangkit dari krisis karena ia mengakui bahwa oligarki keuangan tidak bisa terus dibiarkan. Negara tumbuh bukan dengan menyangkal kesalahan, tetapi dengan mengakui, menindak, dan menata ulang.
Membayar Whoosh dengan APBN tanpa koreksi adalah bentuk impunitas kebijakan. Mengembalikan rasionalitas Whoosh berarti menolak impunitas itu. Dan di sinilah pilihan moral pemerintahan baru ini diuji: apakah ia akan menjadi rezim yang menutup kesalahan masa lalu, atau rezim yang memulihkan kemampuan negara untuk belajar dari kesalahan itu.
Jika rasionalitas dipulihkan, Whoosh tidak harus menjadi simbol kesalahan. Ia dapat menjadi simbol koreksi. Dan itu jauh lebih berharga bagi bangsa ini daripada kebanggaan yang dibangun dari penyangkalan. [ ]
Penulis berijasah asli dari Jurusan Studi Pembangunan FE-Unpad; Anggota Komite Eksekutif KAMI; Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air