PPDB DKI: Refleksi Keadilan di Dunia Pendidikan
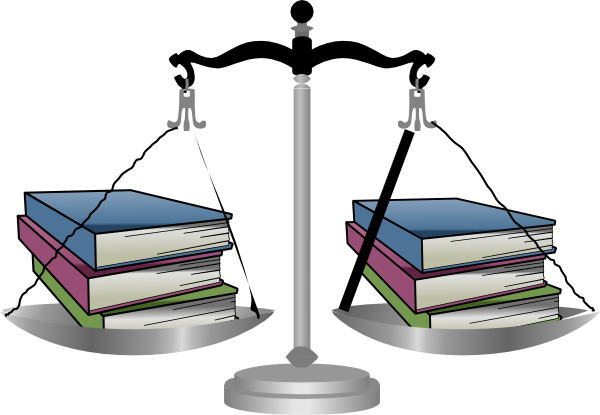
Keadilan pendidikan jelas bukan mengenai siapa yang masuk dan tidak masuk ke sekolah negeri, tetapi seberapa mampu pemerintah memberikan pendidikan yang merata bagi semua calon didik yang mau belajar.
Oleh : Tito Satya Rinaldi
Sebelum berkembang opini bermacam-macam, saya harus memberikan informasi bahwa saya adalah orang tua dua siswa yang tahun ini bergantung dengan keputusan Provinsi DKI terkait aturan PPDB.

Sabri, anak pertama saya, memasuki jenjang SMA, sedangkan Sabra masuk ke jenjang SMP. Hal ini patut saya sampaikan untuk memberikan pemahaman bagi para pembaca terkait subjektivitas ataupun objektivitas tulisan saya.
Banyak rekan maupun teman, baik di dunia maya maupun nyata, yang dalam beberapa bulan ini mendapat kegalauan terkait masa depan pendidikan anak-anak mereka. Wabah pandemi COVID-19 dan tidak diselenggarakannya Ujian Nasional, mendorong terbentuknya sebuah aturan penyesuaian yang berimplikasi besar pada setiap calon peserta didik, khususnya di jenjang SMP dan SMA. Di DKI, aturan tersebut mengubah komposisi jumlah penerimaan siswa didik dan cara kualifikasi yang digunakan pada setiap jalur.
Keramaian terjadi ketika jalur zonasi PPDB DKI (sebagai jalur dengan komposisi terbesar) menggunakan umur sebagai kriteria utama dalam penerimaan terbesar. Bukan nilai dan bukan jarak (dalam satuan meter/kilometer). Berita di media massa dan media sosial memperlihatkan beberapa anak yang cukup “dewasa” masuk ke jenjang SMP atau SMA. Sehingga muncul anekdot, “bukan yang pintar, tetapi yang tua”. Bahkan muncul gerakan orang tua ‘garis keras’ yang mengecam kebijakan para aparat dan birokrat yang terlibat dalam kebijakan tersebut.
Masuk ke jalur berikutnya, jalur prestasi akademik, yang juga memicu kegerahan beberapa orang tua, terutamanya adalah penggunaan angka akreditasi sekolah sebagai pengali nilai akademis setiap siswa. Beberapa sekolah swasta mendapatkan priviledge yang luar biasa, karena memiliki akreditasi tinggi. Siswa berprestasi di salah satu sekolah, bisa tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk ke sekolah negeri pilihan karena itu.
Tibalah jalur akhir, yang juga menggunakan cara penilaian yang sama dengan jalur prestasi akademik. Di mana nilai siswa diperhitungkan dengan nilai akreditasi sekolah asal.
Alhamdulillah, sejak melihat hasil jalur zonasi diumumkan via website PPDB yang menyatakan kedua anak saya GAGAL masuk ke sekolah yang diinginkan, saya dan istri memutuskan mencari sekolah swasta untuk mereka. Keduanya sudah berhasil mendapatkan sekolah dengan implikasi biaya sekolah yang cukup signifikan, baik uang masuk maupun bulanan. Semua patut disyukuri.
Setelah semua ini terjadi, apa opini saya? Semua polemik yang terjadi menjadi salah satu parameter ketidaksiapan kita semua dalam memeratakan keadilan pendidikan bagi banyak seluruh rakyat Indonesia, khususnya DKI. Apa sebabnya? Saya akan coba bahas satu persatu.
Sekolah negeri (public school) adalah sekolah yang secara prinsip tidak berbayar alias (nyaris) gratis. Sabri selama sekolah di SMP Negeri 41 hampir tidak pernah mengeluarkan biaya, kecuali ketika pendalaman materi menjelang UN. Sekolah negeri yang diselenggarakan pemerintah masih memiliki kualifikasi informal, sekolah favorit dan non-favorit.
Untuk SMA, dasar “kefavoritan” itu dibentuk dari berapa jumlah lulusannya yang masuk ke Perguruan Tinggi Negeri, terutama lewat jalur undangan (SNMPTN). Sedangkan untuk SMP, kefavoritan didasarkan atas berapa banyak siswanya bisa masuk ke SMA favorit, efek berantai.
Apa akibatnya? Untuk mendapatkan kesempatan jalur undangan, maka seluruh siswa didik (dan orang tua didik tentunya), melakukan banyak cara (legal atau non legal). Hal ini menurut saya jelas merupakan indikator ketidakadilan yang pertama.
Bagaimana pemerintah bisa memberikan keadilan bagi siswa SMP dan SMA ketika output yang diterima oleh PTN sudah menerapkan sistem ketidakadilan? Benar, masih ada jalur lain untuk bisa masuk ke PTN, tetapi mau tidak mau indikator ketidakadilan diterapkan pada output, sehingga secara proses pasti akan muncul ketidakadilan juga.
Sehingga, ketika wabah pandemi ini muncul dan menghilangkan Ujian Nasional, maka yang terjadi juga geger keadilan pendidikan. Pemerintah harus menjawab, apakah keadilan pendidikan akan diberikan kepada siswa yang rata-rata pintar saja, atau kepada semua siswa yang mau mengenyam pendidikan? Ketika pemerintah bisa menjawab itu, maka prioritas pemerintah mungkin tidak fokus pada membangun sekolah-sekolah unggulan, tetapi memastikan tersedianya daya tampung yang cukup di setiap jenjang pendidikan.
Fenomena perubahan kriteria dalam PPDB memberikan indikasi bahwa kebutuhan tercukupinya sekolah negeri semakin penting. Ketika dulu muncul stigma hanya yang cukup pintar yang bisa bersekolah negeri, maka saat ini hal tersebut perlahan hilang. Setiap sekolah negeri akan cenderung merata, dan para pendidik pun mau tidak mau harus berusaha memberikan kesempatan yang luas bagi setiap siswa didiknya untuk mendapatkan materi pendidikan yang sama. Apalagi krisis ekonomi akibat pandemi membuat sebagian orang tua siswa kehilangan kemampuan untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta. Hal ini memicu makin tampaknya keterbatasan daya tampung sekolah, terutama di jenjang SMA. Perubahan perilaku ini yang menurut saya luput dari hitungan pemerintah DKI.
Itulah mengapa ketika banyak orang tua menanyakan opini saya mengenai PPDB DKI, jawaban jujur saya adalah “saya paham, tapi mestinya ada jalan yang lebih baik”. Keadilan pendidikan jelas bukan mengenai siapa yang masuk dan tidak masuk ke sekolah negeri, tetapi seberapa mampu pemerintah memberikan pendidikan yang merata bagi semua calon didik yang mau belajar.
Apa jalan yang lebih baik? Pertama, hilangkan status sekolah favorit. Kedua, ketimpangan fasilitas pendidikan dari setiap sekolah negeri harus segera dihilangkan. Ketiga, pemilihan jalur undangan tidak diberikan kepada sekolah favorit, kalau tidak mampu mengidentifikasi siswa berprestasi, maka hilangkan jalur undangan.
Keempat, dengan bantuan teknologi, materi pendidikan antarsekolah negeri dapat semakin terstandardisasi, setidaknya rotasi pendidik bisa menjadi ujian pemerataan pendidikan ini.
Masih banyak langkah-langkah yang dapat dilakukan, tapi kita harus samakan dulu persepsi bahwa keadilan pendidikan adalah pondasi utama untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. [ ]
*penulis, orang tua murid yang bersekolah di DKI Jakarta







