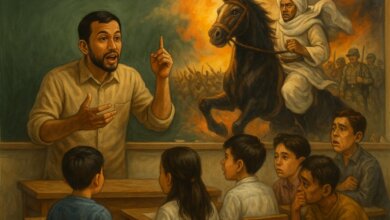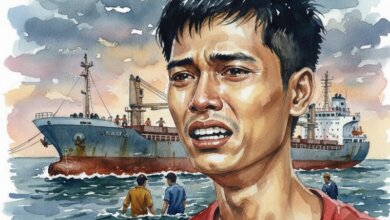Di era kebohongan saat ini, ketika integritas sering diuji dan pengabdian tanpa pamrih terasa langka, K.H. Abdul Halim adalah oase. Ia menunjukkan: sejarah bukan hanya tentang nama besar. Tapi terkait mereka yang menanam benih perubahan dalam keheningan. Ketekunan, kesederhanaan, keberanian, dan konsistensi—semua itu tercermin dalam teladan Abdul Halim.
JERNIH– Saudaraku,
Di kampung Ciborelang, Majalengka, pada 26 Juni 1887, lahirlah Abdul Halim, putra dari K.H. Muhammad Iskandar, seorang ulama kharismatik yang dihormati. Ciborelang bukan sekadar nama kampung bau lisung. Ia adalah laboratorium kehidupan: tempat ketekunan, kesabaran, dan keadilan tertanam sejak dini.
Ketahuilah. Masa kecil Abdul Halim beraura perdesaan. Tempat tinggalnya terasa hangat-nyaman, bak sarang burung yang melindungi dan merawat anak unggas. Sawah-sawah terhampar indah. Apalagi di pagi hari diselimuti kabut tipis. Aroma tanah basah terasa begitu meruap. Suara ayam berkokok bersahutan. Anak-anak berlarian menuju mushola. Menguatkan suasana batin perkampungan yang mengasyikkan, sekaligus menyatukan.
Di sela aktivitas bertani dan belajar, Abdul Halim menatap langit. Menyerap pelajaran dari alam dan masyarakat. Gelombang itu membentuk karakter kepemimpinan. Tanpa sadar kelak menuntunnya menjadi seorang tokoh nasional, meski berasal dari kampung kecil. Ayahnya menanamkan prinsip sederhana tapi kokoh: “Ilmu tanpa amal adalah pohon tak berbuah.”
Catatlah. Pendidikan awalnya ditempuh di pesantren-pesantren lokal. Ia diajar guru-guru, penuh dedikasi dan ikhlas. Menekankan keseimbangan antara ilmu agama dan kesadaran sosial. Perjalanan belajarnya merambah hingga ke Mekah, berguru pada Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabaui, seorang ulama modernis-moderat. Dari beliau, Abdul Halim belajar menyeimbangkan pemikiran tradisionalis dengan modernis. Memahami nilai-nilai klasik sekaligus prinsip-prinsip reformasi sosial. Sikap moderat ini menjadi landasan pemikiran Abdul Halim sepanjang hidupnya, membuatnya diterima di berbagai kalangan. Menjadi pemersatu di tengah perbedaan pandangan.
Ingatlah. Dari petualangan, pulang ke tanah air. Mendirikan pesantren. Memadukan tradisi klasik dengan kurikulum modern—mengajarkan kitab kuning sekaligus kesadaran kebangsaan dan sosial. Tak hanya itu. Ia aktif dalam Persyarikatan Ulama, Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), dan organisasi pergerakan lain. Demi menyiapkan generasi muda yang mampu berpikir kritis. Memahami kemerdekaan. Menolak penjajahan dengan strategi cerdas. Kiprahnya membawanya ke sidang BPUPKI, di mana ia menjadi jembatan antara tradisi pesantren dan aspirasi nasional.
Tengoklah. Percikan suasana sidang BPUPKI. Ia dikenal tenang namun tegas. Rekonstruksi dialog berikut menguatkan hal itu:
Rekan BPUPKI: “Halim, bagaimana pendapatmu soal falsafah dan dasar negara?”
Abdul Halim: “Falsafah dan dasar negara benar-benar harus lahir dari nurani rakyat, bukan sekadar kesepakatan politik elite. Negara tanpa landasan moral-etis akan runtuh sebelum berdiri.”
Rekan lain: “Apakah agama akan memisahkan kita?”
Abdul Halim: “Agama bukan sekadar simbol. Ia fondasi etika dan moral, yang menuntun setiap warga negara tanpa memaksakan keyakinan tertentu.”
Sederet kalimat jawaban itu terasa bernas dan menggema. Warisan intelektual atau pemikiran Abdul Halim mencerminkan integrasi antara keislaman dan kebangsaan. Menolak kompromi. Tanpa mereduksi prinsip. Namun ia tetap bijak dalam menghadapi perbedaan. Abdul Halim terus menulis. Mengajar. Menyebarkan gagasan tentang pentingnya pendidikan pesantren dan peran ulama dalam menjaga bangsa.
Camkanlah. Warisan intelektualnya tak kalah penting, bagaikan bunga terus mewangi: Santi Asromo. Ya, sebuah lembaga pendidikan. Memadukan pengajaran agama dengan ilmu umum. Menekankan pembentukan karakter dan kepemimpinan. Ia pun berperan penting dalam pendirian Persatuan Umat Islam (PUI), wadah konsolidasi umat di Nusantara untuk memperkuat pendidikan pesantren dan persatuan umat.
Sadarlah. Di era kebohongan kiwari. Ketika integritas sering diuji dan pengabdian tanpa pamrih terasa langka, K.H. Abdul Halim adalah oase. Ia menunjukkan: sejarah bukan hanya tentang nama besar. Tapi terkait mereka yang menanam benih perubahan dalam keheningan. Ketekunan, kesederhanaan, keberanian, dan konsistensi—semua itu tercermin dalam teladan Abdul Halim.
Sepakat. Ia bukan sekadar tokoh masa lalu. Ia adalah cermin bagi kita yang ingin menapaki jalan benar: berani setia pada nurani, menyalakan cahaya di kegelapan, dan berjalan tegak-lurus meski sendiri.
K.H. Abdul Halim telah lama meninggalkan kita. Menghadap Sang Mahacinta pada 7 Mei 1962. Namun teladannya tetap menyala. Dari anak kampung hingga sidang BPUPKI. Menunjukkan bahwa keberanian, integritas, dan pengabdian bukan soal sorak-sorai atau popularitas, tapi setia pada nilai-nilai kebenaran-fundamental.
Kini, ketika kita menoleh ke belakang, jejak Abdul Halim adalah suluh bagi perjalanan bangsa.
Saudaraku, renungkanlah. Dalam keheningan, kita menemukan kekuatan yang paling terang. Dalam kesetiaan, kita menemukan teladan yang paling abadi. Dalam pengabdian, kita menemukan arti kemerdekaan yang sejati. [ ]