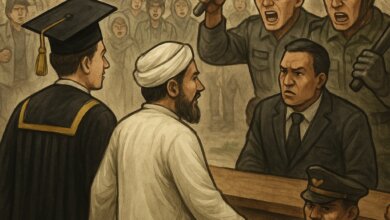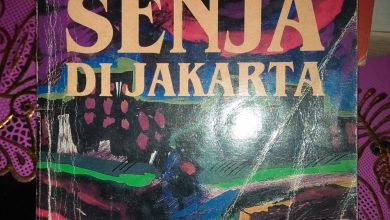Idealnya universitas adalah menjadi mercusuar akal sehat dan etika publik. Saleem Badat menyampaikan tentang pentingnya memahami “The Role of Higher Education in Society: Valuing Higher Education”. Dia menyatakan bahwa kita tidak akan memahami “what it means to be a university” jika kita gagal memahami “a sense of our own worth” dan “our understanding of our identity”.
Oleh : Fahmy Lukman*
JERNIH–Saya seorang dosen perguruan tinggi yang telah berkiprah dengan profesi itu lebih dari 30 tahun. Sebuah perjalanan waktu panjang dengan seluruh dinamika “asam-garam” yang terjadi dalam bilangan waktu tersebut.
Saat ini, ada ruang kegelisahan yang mendalam ketika memperhatikan dan mengamati keberadaan perguruan tinggi di Indonesia yang mendapat sorotan tajam publik nasional, bahkan internasional. Saya seperti tersengat tatkala sahabat saya, seorang guru besar filsafat dari Benha University Mesir beberapa waktu lalu bertanya tentang apa yang terjadi dengan universitas di Indonesia. Saya hanya terdiam dan berupaya mengalihkan pembicaraan. Saya tidak sanggup untuk menjawabnya.
Saya teringat kembali pada sebuah dialog cukup panjang tahun 2015 dengan menteri pendidikan tinggi Mesir saat itu, tentang seorang tokoh Afrika Selatan yang sangat disegani karena kiprahnya dalam memajukan pendidikan, terutama di Afrika Selatan. Tokoh itu adalah Saleem Badat dari Rhodes University, South Africa. Dalam satu pidatonya, Badat mengungkapkan tentang esensi “what it means to be a university” dan hal itu tidak akan pernah lengkap tanpa adanya “a sense of our own worth” yang muncul dari pemahaman mendalam tentang identitas kita.

A Sense of Our Own Worth dan tantangan keberagaman
Dalam dunia yang semakin multikultural, identitas universitas tidak bisa lepas dari bagaimana sivitas akademika, dosen, peneliti, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan berinteraksi satu sama lain. “A sense of our own worth” tidak semata ditentukan oleh reputasi akademik dan ranking universitas, tetapi juga bagaimana setiap individu di dalamnya mampu memahami, menghargai, dan bekerja sama dengan berbagai latar belakang budaya, perspektif, serta kebebasan berpendapat.
Dengan mengakui dan menginklusikan keragaman, universitas dapat memupuk iklim akademik yang benar-benar terbuka dan inklusif. Ini tentu saja mencakup desain kurikulum yang merefleksikan keberagaman ilmu dan budaya, serta kebijakan dan praktik yang menjunjung tinggi kesetaraan kesempatan.
Berangkat dari pertanyaan di atas, dalam beberapa tahun terakhir ini, kita menyaksikan dinamika kompleks tentang lanskap sosial, politik, ekonomi Indonesia, terutama jelang dan pascapemilu 2024. Peran perguruan tinggi dan para intelektual menjadi sorotan tajam dan serius, khususnya ketika sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa dari berbagai universitas beberapa waktu lalu menyampaikan pendapat dan pernyataan keprihatinan atas memburuknya etika publik dan tata kelola kekuasaan. Fenomena ini bukan semata-mata ekspresi politis, tetapi merupakan refleksi dari krisis yang lebih mendalam, yaitu lunturnya akhlak, etika, norma universitas dan pudarnya tanggung jawab intelektual.
Dalam kaitan ini, idealnya universitas adalah menjadi mercusuar akal sehat dan etika publik. Saleem Badat menyampaikan tentang pentingnya memahami “The Role of Higher Education in Society: Valuing Higher Education“. Dia menyatakan bahwa kita tidak akan memahami “what it means to be a university” jika kita gagal memahami “a sense of our own worth” dan “our understanding of our identity“.
Prinsip tersebut mengingatkan bahwa institusi pendidikan tinggi harus mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan intelektual dan lepas dari intervensi politik dan agenda kepentingan tertentu. Universitas harus menjaga jarak dengan kekuasaan dan politik. Universitas, menurutnya, bukan sekadar “mesin produksi” ijazah atau pusat peringkat akademik, tetapi sebuah organisasi kompleks yang menghadapi tantangan moral dan sosial dalam dunia yang terus berubah. Mengabaikan identitas dan nilai dasar universitas berarti “bunuh diri”, membiarkan institusi ini kehilangan jiwanya.
Kondisi ini menjadi sangat relevan dengan realitas di Indonesia. Berbagai kasus yang muncul dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari politisi mengejar gelar akademik sebagai alat legitimasi kekuasaan, moralitas para akademisi dan mahasiswa, sampai maraknya kasus plagiarisme dan ijasah abal-abal merupakan bentuk konkret dari peluruhan akhlak akademik. Fenomena ini menunjukkan bahwa universitas tak luput dari bahaya politisasi dan komersialisasi, dua hal yang kerap menggerogoti nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab intelektual. Jika universitas tunduk pada kekuasaan politik atau pasar, maka universitas itu telah kehilangan otonomi dan kredibilitasnya sebagai benteng kebenaran dan moralitas.
Dalam konteks inilah maka tanggung jawab intelektual menjadi kata kunci. Intelektual bukan sekadar orang yang memiliki pengetahuan tinggi, tetapi juga pribadi yang berani menyuarakan kebenaran, membela keadilan, dan menggugah kesadaran publik.
Gian Tu Trung dari Vietnam menegaskan bahwa intelektual adalah orang yang menggabungkan pengetahuan, kemampuan, kemauan untuk membangkitkan masyarakat, dan memiliki tujuan mulia. Kekurangan salah satunya, maka gelar intelektual tidak layak disandang. Artinya, para akademisi tidak cukup hanya menjadi ahli dalam bidangnya, tetapi juga harus memiliki keberanian moral untuk menjadi pengawal nurani publik.
Begitu pula pernyataan Sigal R. Ben-Porath dalam “Cancel Wars, How Universities Can Foster Free Speech, Promote Inclusion, and Renew Democracy”. Dalam buku itu, dia menyoroti pentingnya peran universitas dalam menumbuhkan kebebasan berpendapat dan memperbarui demokrasi. Ia menekankan bahwa kampus seharusnya menjadi ruang aman bagi dialog kritis dan pertukaran gagasan, bukan menjadi instrumen kekuasaan yang mengekang kebebasan berfikir dan pemikiran. Di tengah polarisasi politik dan memburuknya etika publik, universitas memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi diskursus yang beradab, konstruktif, dan berpijak pada nilai-nilai demokratis.
Sayangnya, tidak sedikit institusi pendidikan tinggi yang gagal memainkan peran tersebut. Ketika perguruan tinggi tidak lagi membangun iklim berpikir kritis, atau bahkan justru membungkam suara kritis dari dalam kampus, maka universitas telah gagal menjalankan fungsinya sebagai penjaga nalar publik. Hal ini semakin diperparah oleh praktik birokratisasi dan komodifikasi, komersialisasi pendidikan, yang menjadikan gelar akademik sebagai komoditas, bukan hasil proses intelektual yang jujur dan bermakna.
Pada sisi lainnya, kita juga tengah menghadapi cultural lag, yaitu ketimpangan antara kemajuan ilmu dan teknologi dengan kemunduran moral dan spiritual. Indonesia telah melahirkan ribuan doktor dan guru besar, tetapi jika banyak dari mereka diam terhadap ketidakadilan, membiarkan praktika korupsi, manipulasi intelektual, atau bahkan menjadi bagian dari sistem yang tidak etis, maka keberadaan mereka hanya akan memperkuat status quo yang korup dan tidak berpihak pada rakyat.
Seorang tokoh dunia pernah menyatakan, “Dunia menjadi tempat yang berbahaya bukan karena mereka yang berbuat jahat, tetapi karena mereka yang melihat kejahatan dan tidak melakukan apa-apa”. Ini adalah pengingat keras bagi setiap akademisi dan intelektual bahwa diam dalam situasi krisis moral adalah bentuk pengkhianatan terhadap pengetahuan itu sendiri, di samping Tuhan tentu saja. Sebagai entitas yang memiliki privilese pengetahuan dan akses terhadap wacana publik, para intelektual wajib menjadi penjaga etika dan kebenaran, bukan sekadar penonton atau penikmat kenyamanan akademik.
Simpulan
Menjadi universitas sejati berarti bersedia menjalankan misi transformasi sosial. Universitas harus menjadi ruang dialog antar-kebenaran, bukan menara gading yang terasing dari realitas. Ia harus menjadi jembatan antara ilmu dan nurani, antara teori dan praksis, antara kampus dan masyarakat. Untuk itu, kita perlu membangun kembali kesadaran kolektif tentang “makna menjadi universitas” sebagaimana diajukan oleh Saleem Badat. Sebuah kesadaran yang tidak hanya terfokus pada prestasi akademik atau peringkat internasional, tetapi juga pada kontribusi moral dan sosial dari pendidikan tinggi itu sendiri.
Dengan demikian, universitas dan para intelektualnya diharapkan tidak sekadar menjadi saksi atas kegagalan etika publik, tetapi menjadi pelopor perubahan. Merekalah yang memikul tanggung jawab sejarah untuk menata ulang nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan dan kehidupan sosial-politik. Jika Indonesia ingin bergerak menuju peradaban yang lebih adil, bermartabat, dan manusiawi, maka universitas harus kembali pada akarnya, yaitu ruang pembebasan, penyadaran, dan pemuliaan spritualitas, akhlak, dan nilai-nilai hidup bersama. Is it possible? We must answer that question with wait and see and hopefully the storm will pass quickly. []
*Dosen pada Departemen Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran dan ketua Asosisasi Linguistik Hukum Indonesia (ALHI)