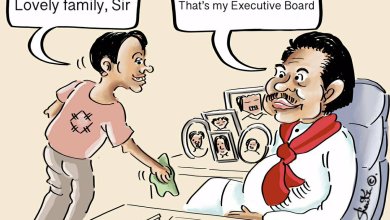Waktu Orang Cibasale Masih Hidup dari Gacong

JAKARTA— Pertama kali saya mendengar kata ‘pare IR’ (padi IR) itu kalau tak salah tahun 1978, saat kelas 2 SD. Diucapkan seorang bapak tetangga sebelah rumah dengan nada sedikit merendahkan. Kalau tak salah, ia menolak saat diajak makan pagi oleh istrinya, karena,”…sanguna beas pare IR. Nasinya ditanak dari beras IR.”
JAKARTA— Pertama kali saya mendengar kata ‘pare IR’ (padi IR) itu kalau tak salah tahun 1978, saat kelas 2 SD. Diucapkan seorang bapak tetangga sebelah rumah dengan nada sedikit merendahkan. Kalau tak salah, ia menolak saat diajak makan pagi oleh istrinya, karena,”…sanguna beas pare IR. Nasinya ditanak dari beras IR.”
Bukan hendak membela si bapak, jika setelah beranjak besar saya memaklumi penolakan bapak tetangga saya itu saat diajak makan istrinya yang menanak nasi berbahan padi IR. Sebagaimana kita tahu, urang Sunda umumnya menyukai nasi pulen. Sementara beras IR menghasilkan nasi yang pera, soliter sendiri-sendiri tak mau membangun persatuan di antara mereka. Lihat saja warung-warung yang buka di wilayah urang Sunda. Biasanya hanya laris manakala beras yang disajikan cukup pulen. Urang Sunda, bagaimana pun miskinnya mereka, bila makan di luar rumah selalu ingin makan nasi pulen, yang bisa mereka kepal-kepal dan cocolkan ke sambel dadak yang digerus langsung di cowetnya.
Padi IR ini memang bukan jenis padi yang biasa ditanam secara tradisional di sawah atau ladang (huma) orang Indonesia. Padi itu hasil Revolusi Hijau, yang dikembangkan lembaga International Rice Research Institute (IRRI) di Filipina, pertengahan 1970-an. Pak Harto–Sang ‘Bapak Pembangunan’, membawa dua varietas IR, yakni IR5 dan IR8 untuk ditanam di Indonesia guna menyukseskan swasembada pangan. Jenis padi yang di sini diadaptasi sebagai PB5 dan PB8 itu memang lebih produktif menghasilkan bulir padi, selain tahan hama wereng. Namun ya itu tadi, banyak petani menolak menanamnya karena rasanya tidak enak alias pera.
Para petani kita di tahun 1970-an itu– bahkan di daerah saya hingga pertengahan 1980-an, lebih memilih varietas-varietas lokal yang menghasilkan nasi yang pulen disantap. Rojolele, Pandanwangi, misalnya, lebih disukai untuk ditanam. Tetapi mulai 1980-an, dengan ‘tekanan’ pemerintah yang massif melalui Kelompencapir, para petani pun akhirnya menyerah. Mereka meninggalkan pola lama dan mulai menanam varietas-varietas unggul. Kalau tak salah, telinga bocah saya saat itu sering mendengar di radio atau TVRI orang berulang-ulang mengatakan ‘VUTW’, alias Varietas Unggul Tahan Wereng, sebagai jenis padi yang ‘mantul Pak De’ bila ditanam. Dan memang benar, dengan varietas-varietas baru itu Indonesia bahkan sempat mencapai swasembada pangan serta mendapatkan penghargaan Badan Pangan PBB (FAO).
Tetapi secara budaya, penanaman varietas-varietas padi baru itu menggusur banyak sekali budaya pertanian tradisional kita. Tak hanya dalam pola menanam dan menuai, tapi juga menghilangkan keriaan dan keguyuban—setidaknya, saat panen.
Bagi anak-anak sebaya saya zaman itu, panen merupakan hajatan besar tersendiri. Hajatan yang cukup lama, hingga dua bulan ke muka, dengan berbagai variasi aktivitas di dalamnya. Pada saat panen, padi yang dituai umumnya padi-padi tradisional yang berbatang panjang. Di Majalengka umumnya yang ditanam itu pare bulu, yang disebut demikian karena di ujung setiap bulir seperti ada selembar bulu. Tak jarang hingga satu meter lebih tingginya. Batang-batang padi itu dituai tidak dengan sabit seperti saat ini, melainkan dengan etem atau ani-ani dalam bahasa Indonesia.
Sisa batang padi yang tak dipotong akan kami ambil, dipotong dengan pisau tajam. Biasanya pisau silet bekas yang sudah tak lagi dipakai bercukur. Bapak-bapak kami atau anak-anak yang lebih besar akan membuatkan kami terompet batang padi. Yang lebih jago bahkan bisa membuat semacam seruling dari batang padi. Setelah jadi, ramai-ramai kami akan meniupnya. Tak hanya di sawah manakala menunggu panen selesai, terompet batang padi itu akan kami bawa ke rumah, dimainkan dan disimpan hingga menciut kekeringan.
Selama bermain terompet pun kami anak-anak akan ‘menjarah’ petak-petak sawah dan huma yang sudah dipanen. Tanpa ragu kami akan merunduk, tengkurap atau bahkan bergulingan di pematang, melindas batang-batang padi yang sudah dipotong. Yang kami cari biasanya belalang-belalang, terutama yang masih lunak terbungkus selaput. Itulah belalang yang paling enak bila digoreng kering dengan aneka rempah dan bumbu asam Jawa. Oh ya, di tempat kami, belalang-belalang itu bahkan bisa dijual di pasar dalam ukuran literan. Belalang-belalang itu kami kumpulkan dalam korang atau wadah ikan dari anyaman bambu. Kantong plastik masih jarang sekali saat itu.
Bila padi di semua petak sudah dipotong, tinggallah para buruh tani yang ikut membantu panen menunggu pembagian. Biasanya padi-padi itu diikat membentuk ikatan yang disebut pocong atau geugeus. Lima ikatan pocong akan diikat lagi dalam ikatan lebih besar yang disebut sangga. Nah, para buruh tani yang membantu panen itu akan mendapatkan upah satu pocong setiap satu sangga. Cara pembagian ini di Majalengka disebut Gacong. Tina sasangga meunang sapocong, atau dari satu sangga, buruh dapat satu pocong.
Orang-orang kampung saya, Cibasale, biasanya bukan pemilik lahan. Hanya buruh tani. Umumnya mereka hidup dari sistem Gacong tersebut.
Usai panen belum berarti pesta anak-anak berakhir. Kami masih bisa mencari telor-telor bebek yang digembalakan di sawah-sawah bekas panen itu. Kadang bukan mencari, lebih tepat menyembunyikan telor yang dikeluarkan bebek kepacirit yang kebelet bertelur. Segala cara bisa kami lakukan untuk menyembunyikan telur-telur muntahan itu. Kalau sekadar dimarahi tukang angon bebek manakala ketahuan sih biasa banget.
Kira-kira sebulan lebih setelah panen, manakala tumpukan jerami sudah diguyur hujan, ada lagi yang bisa kami lakukan: mengais-ngais tumpukan jerami. Bukan mencari jarum yang tentunya sia-sia. Kami mencari dan mengumpulkan jamur jerami atau jamur padi yang bila dipepes dengan tambahan irisan bawang merah, rasanya selangiiit. Tentu saja, buat lidah kami, anak-anak kere zaman itu. [ dsy]
Bukan hendak membela si bapak, jika setelah beranjak besar saya memaklumi penolakan bapak tetangga saya itu saat diajak makan istrinya yang menanak nasi berbahan padi IR. Sebagaimana kita tahu, urang Sunda umumnya menyukai nasi pulen. Sementara beras IR menghasilkan nasi yang pera, soliter sendiri-sendiri tak mau membangun persatuan di antara mereka. Lihat saja warung-warung yang buka di wilayah urang Sunda. Biasanya hanya laris manakala beras yang disajikan cukup pulen. Urang Sunda, bagaimana pun miskinnya mereka, bila makan di luar rumah selalu ingin makan nasi pulen, yang bisa mereka kepal-kepal dan cocolkan ke sambel dadak yang digerus langsung di cowetnya.
Padi IR ini memang bukan jenis padi yang biasa ditanam secara tradisional di sawah atau ladang (huma) orang Indonesia. Padi itu hasil Revolusi Hijau, yang dikembangkan lembaga International Rice Research Institute (IRRI) di Filipina, pertengahan 1970-an. Pak Harto–Sang ‘Bapak Pembangunan’, membawa dua varietas IR, yakni IR5 dan IR8 untuk ditanam di Indonesia guna menyukseskan swasembada pangan. Jenis padi yang di sini diadaptasi sebagai PB5 dan PB8 itu memang lebih produktif menghasilkan bulir padi, selain tahan hama wereng. Namun ya itu tadi, banyak petani menolak menanamnya karena rasanya tidak enak alias pera.
Para petani kita di tahun 1970-an itu– bahkan di daerah saya hingga pertengahan 1980-an, lebih memilih varietas-varietas lokal yang menghasilkan nasi yang pulen disantap. Rojolele, Pandanwangi, misalnya, lebih disukai untuk ditanam. Tetapi mulai 1980-an, dengan ‘tekanan’ pemerintah yang massif melalui Kelompencapir, para petani pun akhirnya menyerah. Mereka meninggalkan pola lama dan mulai menanam varietas-varietas unggul. Kalau tak salah, telinga bocah saya saat itu sering mendengar di radio atau TVRI orang berulang-ulang mengatakan ‘VUTW’, alias Varietas Unggul Tahan Wereng, sebagai jenis padi yang ‘mantul Pak De’ bila ditanam. Dan memang benar, dengan varietas-varietas baru itu Indonesia bahkan sempat mencapai swasembada pangan serta mendapatkan penghargaan Badan Pangan PBB (FAO).
Tetapi secara budaya, penanaman varietas-varietas padi baru itu menggusur banyak sekali budaya pertanian tradisional kita. Tak hanya dalam pola menanam dan menuai, tapi juga menghilangkan keriaan dan keguyuban—setidaknya, saat panen.
Bagi anak-anak sebaya saya zaman itu, panen merupakan hajatan besar tersendiri. Hajatan yang cukup lama, hingga dua bulan ke muka, dengan berbagai variasi aktivitas di dalamnya. Pada saat panen, padi yang dituai umumnya padi-padi tradisional yang berbatang panjang. Tak jarang hingga satu meter lebih tingginya. Batang-batang padi itu dituai tidak dengan sabit seperti saat ini, melainkan dengan etem atau ani-ani dalam bahasa Indonesia.
Sisa batang padi yang tak dipotong akan kami ambil, dipotong dengan pisau tajam. Biasanya pisau silet bekas yang sudah tak lagi dipakai bercukur. Bapak-bapak kami atau anak-anak yang lebih besar akan membuatkan kami terompet batang padi. Yang lebih jago bahkan bisa membuat semacam seruling dari batang padi. Setelah jadi, ramai-ramai kami akan meniupnya. Tak hanya di sawah manakala menunggu panen selesai, terompet batang padi itu akan kami bawa ke rumah, dimainkan dan disimpan hingga menciut kekeringan.
Selama bermain terompet pun kami anak-anak akan ‘menjarah’ petak-petak sawah dan huma yang sudah dipanen. Tanpa ragu kami akan merunduk, tengkurap atau bahkan bergulingan di pematang, melindas batang-batang padi yang sudah dipotong. Yang kami cari biasanya belalang-belalang, terutama yang masih lunak terbungkus selaput. Itulah belalang yang paling enak bila digoreng kering dengan aneka rempah dan bumbu asam Jawa. Oh ya, di tempat kami, belalang-belalang itu bahkan bisa dijual di pasar dalam ukuran literan. Belalang-belalang itu kami kumpulkan dalam korang atau wadah ikan dari anyaman bambu. Kantong plastik masih jarang sekali saat itu.
Bila padi di semua petak sudah dipotong, tinggallah para buruh tani yang ikut membantu panen menunggu pembagian. Biasanya padi-padi itu diikat membentuk ikatan yang disebut pocong atau geugeus. Lima ikatan pocong akan diikat lagi dalam ikatan lebih besar yang disebut sangga. Nah, para buruh tani yang membantu panen itu akan mendapatkan upah satu pocong setiap satu sangga. Cara pembagian ini di Majalengka disebut Gacong. Tina sasangga meunang sapocong, atau dari satu sangga, buruh dapat satu pocong.
Orang-orang kampung saya, Cibasale, biasanya bukan pemilik lahan. Hanya buruh tani. Umumnya mereka hidup dari sistem Gacong tersebut.
Usai panen belum berarti pesta anak-anak berakhir. Kami masih bisa mencari telor-telor bebek yang digembalakan di sawah-sawah bekas panen itu. Kadang bukan mencari, melainkan lebih tepat menyembunyikan telor yang dikeluarkan bebek kepacirit yang tak bisa menahan untuk bertulur hanya di kandang. Segal acara bisa kami lakukan untuk menyembunyikan telur-telur muntahan itu. Kalau sekadar dimarahi tukang angon bebek manakala ketahuan sih biasa banget.
Kira-kira sebulan lebih setelah panen, manakala tumpukan jerami sudah diguyur hujan, ada lagi yang bisa kami lakukan: mengais-ngais tumpukan jerami. Bukan mencari jarum yang tentunya sia-sia. Kami mencari dan mengumpulkan jamur jerami atau jamur padi yang bila dipepes dengan tambahan irisan bawang merah, rasanya selangiiit. Tentu saja, buat lidah kami, anak-anak kere zaman itu. [ dsy]