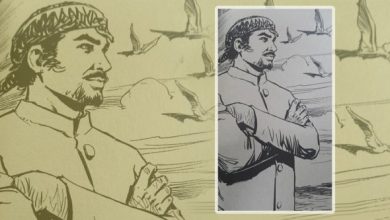Ukur
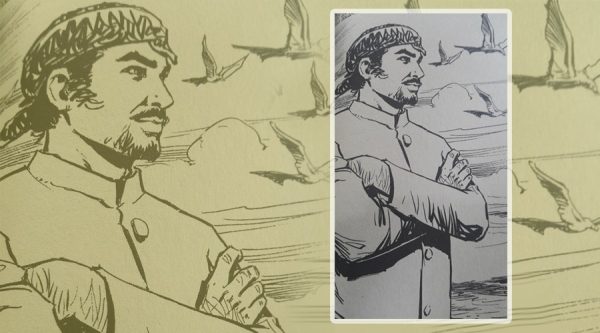
“Perang yang bermula ketika Ramanda Prabu Geusan Ulun tak bisa mengusir Ibunda Ratu Harisbaya yang menyelinap ke dalam tendanya di wilayah Keraton Cirebon ketika Ramanda sebentar mengaso sepulang dari Pajang. Itu terjadi sekitar tahun 1585.”
Oleh : Darmawan Sepriyossa
Pengantar:
Setelah jatuhnya Kerajaan Majapahit, ratusan tahun kemudian kerajaan-kerajaan taklukan di seluruh Nusantara bangkit memupuk kekuatan. Yang paling mencorong adalah Kerajaan Mataram, pengklaim pewaris kekuasaan Majapahit. Sementara kekuatan asing yakni Portugis, Belanda dan Inggris, mulai pula datang menancapkan kuku kekuasaan mereka. Masing-masing dengan kerakusan dan kekejamannya sendiri. Pada saat itu, di Tanah Sunda muncul kekuatan yang mencoba menolak penjajahan, dipimpin seorang bernama Dipati Ukur.—
Episode-9
Menyaksikan kejadian itu tak sedikit wadya bala penyerang kocar-kacir ketakutan. Beberapa tak sempat kabur jauh karena segera jatuh disabet golok atau tertembus tombak teman-temannya sendiri atas perintah seseorang yang kini mulai kelihatan memimpin. Ukur sekilas melihat perawakannya, mengingatkannya pada seseorang di Keraton Mataram.
Ukur mencondongkan badannya ke depan, berbisik pada Lodaya. Si Belang itu mengakhiri kesenangannya merobek-robek perut korban di depannya. Diangkatnya kaki depannya, lalu mundur beberapa langkah. Segera setelah itu, dengan lompatan panjang Lodaya menerjang ke muka, ke arah orang yang memberikan perintah kepada para penyerang.
“Hait!” orang dengan kepala tertutup topeng, hanya menyisakan lubang hidung dan dua lubang mata itu terperanjat. Ia melompat menghindari terkaman Lodaya. Benar saja, dari lompatannya terlihat ilmu meringankan badan orang itu tidak hanya bertaraf rata-rata. Ia seorang jago yang menguasai ilmu kanuragan tinggi.
Begitu kedua kakinya menapak tanah, orang itu melihat Ukur yang tetap menunggang macan itu mendekatinya, setapak demi setapak.
“Ki Sanak, ada dendam apa antara kau dan aku, sehingga di mana pun kau selalu mengincar nyawaku?” tanya Ukur. Baik suara maupun wajahnya menunjukkan ketenangan.
Orang itu hanya mengeluarkan dengusan keji, matanya liar melihat kiri-kanan, memastikan masih ada puluhan pengikutnya yang bertahan bersamanya. Memang ada, dan cukup banyak. Sekitar 30-an orang. Lainnya, kalau tak mati, ya kabur tercerai berai. Bagi mereka yang kabur, bertemu ular besar, harimau ganas atau tertahan jurang selama pelarian itu masih kemungkinan. Sementara berkelahi melawan Lodaya haus darah di sini sudah keniscayaan. Mereka memilih kemungkinan yang masih bisa diakali ketimpang menjadi mangsa cakar dan rahang runcing, lalu mati di sini.
“Bukan urusanmu, juga bukan urusanku, anjing!” kata orang itu lebih keji lagi. “Yang aku tahu, semakin cepat membunuhmu artinya semakin bagus buatku.” Lalu dengan sedikit gerakan golok, ia mengisyaratkan anak buahnya untuk menyerang Ukur.
Meski tampak ragu-ragu, tiga orang menerjang maju hendak membabatkan golok mereka ke Ukur dan Lodaya. Belum juga golok itu mereka sabetkan, terjangan Lodaya telah memakan korban seorang dari mereka. Leher orang itu bolong dikerobok cakar yang runcing dan kuat. Darah menyembur, ikut mengotori pakaian Ukur.
Berbeda sebelumnya, Lodaya kini tak mengacuhkan darah segar itu. Ia kembali melompat tinggi, melampaui kepala dua penyerangnya tadi. Sementara itu duhung Ukur bekerja membabat keduanya. Seorang terkena pinggangnya, membuat usus segala isi perutnya terburai. Sementara yang lain kena di bagian paha, memperlihatkan tulang paha yang putih tersobek benda tajam. Keduanya tumbang. Yang satu dipastikan segera perlaya.
Kini Ukur melihat semua penyerangnya telah dicekam jeri. Semua tertegun mematung, beberapa yang nyalinya kecil bahkan sampai terkencing-kencing.
Ukur menepuk Lodaya sekerasnya. Seolah mengerti, Lodaya itu menggeram hebat. Kepalanya mendongak dengan mulut terbuka, memperlihatkan taring-taringnya yang setajam pisau baja.
“Wuaaaa!” Teriak kawanan yang telah hilang keberanian itu. Susah payah mereka berusaha lari, jatuh bangun ketakutan, diikuti pandangan kesal pemimpinnya. Satu dua terjungkal dihantam pisau terbang yang dilontarkan para hulubalang Aria Rangga Gempol yang beberapa saat tadi justru lebih banyak menonton.
Tapi sang pemimpin pun akhirnya tampak harus tahu diri. Gilirannya kini melirik kiri kanan, berusaha lari. Ukur segera tanggap. Mungkin tak terlalu perlu untuk tahu siapa yang selama ini mengusiknya sampai taraf mencari jalan untuk melenyapkan hidupnya. Tetapi ia pun merasa tak ingin punya persoalan gara-gara membiarkan dirinya diliputi teka-teki.
Dengan satu teriakan panjang Ukur melompat dari punggung Lodaya. Arahnya jelas, menerjang si pemimpin yang berusaha lari.
“Deg!”
Tendangan Ukur tepat menjejak punggung orang yang diincarnya.
“Gubraak!”
Orang itu terdorong ke depan dengan wajah nyaris mencium tanah dengan keras. Tetapi ternyata ia bukan orang sembarangan. Sejengkal lagi mukanya menghajar tanah, ia langsung berjumpalitan menghindari tabrakan fatal itu. Bahkan dengan lesakan keras kakinya menjejak tanah, ia bisa bersalto di udara, berputar dua tiga kali.
Tetapi Ukur sudah tak ingin berbuat setengah hati. Baru saja orang itu hendak menjejak tanah setelah bersalto kesekian kali, cakar Ukur dalam jurus Pamacan telah merobek tak hanya topeng yang menutup wajahnya. Tiga garis memanjang menyobek pipi orang itu, mengambil sebagian dagingnya yang kini tertinggal dicakar Ukur.
“Wuaaaa!”
Si pemimpin penyerangan itu berteriak kesakitan. Ia menutup pipinya, bukan untuk melindungi wajahnya dari penglihatan Ukur. Ia memang merasakan kesakitan yang amat sangat.
Saat tangan yang menutup mukanya itu ia tarik, terlihatlah wajah yang merah penuh darah. Ukur segera mengenalnya.
“Kanjeng Senapati Ronggonoto!” teriaknya. Tetap saja, meski ia sudah punya syak terhadap atasannya, Ukur masih saja terpekik kaget menyaksikan kebenaran dugaannya.
“Kanjeng Senapati…mengapa?” Ukur bertanya. Posisinya kini tak lagi dalam kuda-kuda tegap. Ia merasa tidak pada tempatnya membuat atasannya kini menjadi cacat abadi, yang akan dibawa hingga mati.
Senapati Ronggonoto tak menjawab. Ia hanya menggeram murka. Matanya melotot, seolah bola mata itu hendak meloncat, membawa keluar segala amarahnya. Lalu, dengan teriakan kemarahan senapati Mataram itu melompat ke semak-semak, berlari menghindari Ukur dan rombongannya. Ia tak hanya menjerit marah, karena sayup-sayup seiring kian menjauhnya dia, terdengar tangisan penuh sedih dan marah.
Jika sebelumnya ia punya dendam, maka sejak saat itu dendam Senapati Ronggonoto kepada Ukur mungkin berlipat sepuluh kali. Memang, sejak awal pun wajah Ronggonoto bukanlah wajah tampan dan halus, setampan wajah gemblak- gemblak piaraan para Warok. Tetapi kini wajah tirus tak menarik itu sudah berubah menjadi raut wajah yang mengerikan dengan tetelan daging melekat akibat sobekan cakar.
Ukur tak hendak mengejar Senapati Mataram yang lari itu. Ia tahu, tak punya dirinya rasa tega untuk membinasakan senapati itu di sini, hari ini, apapun yang telah dan hendak lagi ia lakukan barusan. Biarlah urusan itu sepenuhnya urusan Allah yang Maha Penyayang, yang terbukti selalu menyayanginya dengan tetap terhindar dari segala upaya para durjana.
Ukur tahu, apapun urusannya dengan Senapati Ronggonoto dulu, yang tak juga terpikir apa itu, kini urusan itu telah menduplikasi diri puluhan atau bahkan ratusan kali. Senapati itu pasti menjadikan urusan antara dirinya dan Ukur sebagai dendam, yang bisa jadi akan diturunkan terus hingga tujuh atau lebih keturunan.
“Ah, biarlah. Mungkin urusan ini telah menjadi titis tulis kersaning Allah. Aku tinggal menjalani dengan cara terbaik menurut ajaran yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam.” Ukur membatin.
Dilihatnya Rangga Gempol tengah memulasara anak buahnya yang perlaya. Syukurlah, melihat serangan sekitar seratus orang tadi, kematian hanya seorang prajurit bisa dikatakan prestasi besar. Apalagi kini setelah laga jurit itu usai, jelas terlihat puluhan jasad musuh yang tak lagi bernyawa. Beberapa diantaranya masih tersengal-sengal menanti sakaratul maut.
Ukur, Rangga Gempol dibantu semua pengawalnya segera memulasara mayat-mayat itu. Tak mungkin mereka dimandikan, dikafani, dishalatkan satu persatu sebelum dikubur. Akhirnya mayat-mayat musuh itu diletakkan teratur dalam sebuah lubang panjang yang digali bersama.
Beberapa barang yang lumayan berharga dilepas dari badan mereka. Begitu pula golok, pedang dan tombak yang mereka bawa, bila dirasa berguna diambil oleh para pengawal Sumedang. Hanya pakaian yang melekat di jasad para penyerang itu yang tak diganggu sama sekali.
“Mungkin kita akan bertemu para petani dan orang-orang miskin di perjalanan. Barang-barang ini jauh lebih berharga diberikan kepada mereka dibanding dibawa mayat-mayat ini mati,” kata Ukur. Rangga Gempol mengiyakan.
Setelah dishalatkan secara massal, ditimbunlah jasad-jasad itu secara bersamaan. Ukur sebenarnya ingin memulasara dengan lebih baik,tapi banyaknya mayat tak memungkinkan hal itu.
Perlakuan berbeda hanya mereka lakukan pada mayat hulubalang Sumedang Larang itu. Ia dibuatkan lubang tersendiri, dimandikan, dikafani dengan kain putih yang disambung-sambung dengan milik teman-temannya. Jadilah kafan yang cukup untuk menutupi jasadnya. Setelah dishalatkan, jasad itu pun segera ditanam. Kuburan itu sengaja agak ditinggikan, sekadar memberitahu orang-orang yang mungkin lewat bahwa di sana adalah kuburan seseorang.
Lodaya sudah sejak lama tak kelihatan, kembali ke alamnya begitu persoalan Ukur terselesaikan.
Ukur turun ke sungai yang untungnya hanya beberapa tombak jauhnya dari medan pertempuran tadi. Dilepasnya baju kampretnya yang penuh berlumuran darah. Digosok-gosoknya di aliran air, yang segera membuat air di hilir menjadi kemerahan.
Baju itu tak lagi bisa kembali ke warna sebelumnya, kuning gading. Ada warna kemerahan yang tak bisa lagi hilang. Tak apa, secara syariat baju itu sudah bersih dan bisa dipakai lagi tatkala kering nanti. Ukur pun mengambil pakaian bersih dari buntalan yang dibawanya di belakang pelana.
Dengan pakaian baru itu ia pun melaksanakan shalat ashar. Namun meski dirinya dan para pengawal sudah lapar, mereka tak sampai hati membuka bekal dan makan di situ. Bagaimanapun bau anyir darah masih kuat tercium, dan merah masih menjadi warna di mana-mana.
“Kita jalan, Rayi,” kata Ukur mengajak Rangga Gempol pergi. Entah kapan dan dari mana datangnya, Sambrani kini sudah ditungganginya lagi. Yang diajak segera menepuk punggung kuda, membiarkan binatang tunggangan itu berjalan lambat-lambat, diikuti kuda-kuda para prajurit lainnya.
“Boleh Kakang bertanya seandainya Rayi berkenan menjawab?” tanya Ukur. Rangga Gempol yang berkuda disampingnya sigap menjawab. “Silakan.”
“Mohon tidak tersinggung karena pertanyaan ini benar-benar datang dari kebodohan Kakang,” kata Ukur memulai. “Kakang merasa kalau tidak ditanyakan langsung kepada Rayi, ini akan terus bertumbuh, beranak pinak dalam benak dan sangat mungkin menjadi racun yang mengotori pikiran Kakang ke depan.”
“Silakan, Kakang. Tak ada geuneuk maleukmeuk dalam pikiran Rayi soal kakang. Tak ada cemburu, tak ada hasad,” kata Rangga Gempol.
“Sebenarnya, apa yang membuat Rayi memutuskan serah bongkokan kepada Mataram?” tanya Ukur, bertanya langsung tanpa basa-basi lagi.
”Apakah itu sudah dimusyawarahkan dengan para kokolot, terutama mungkin kepada para Kandaga Lante yang kini menjadi para kokolot Sumedang Larang, yakni Eyang Jaya Perkosa atau Eyang Sayang Hawu, Eyang Terong Peot, Eyang Kondang Hapa dan Eyang Nangganan? Karena kita tahu, sejak serah bongkokan itu orang-orang Wetan akan menyebut wilayah kita sebagai Praiangan[1] alias pemberian. Pemberian dari mereka. Itu terus terang membuat Kakang tersinggung, Rayi.”
Wajah Rangga Gempol sempat sedikit memerah. Tetapi bagaimana pun ia adalah seorang bangsawan penuh didikan, seorang terahing kusuma rembesing madu, hal itu dengan cepat berubah ketika ia tersadar.
“Kakang Ukur. Kalau Akang mau jujur, apakah hanya pada saat saya memerintah Sumedang Larang, maka kerajaan Sumedang Larang itu mulai serah bongkokan terhadap Mataram?” Rangga Gempol malah balik bertanya.
Dipati Ukur terkejut dan tahu kemana arah jawaban Rangga Gempol. Namun memang tak ada jawaban jujur lain kecuali mengakui bahwa perkataan Rangga Gempol benar adanya.
“Tidak. Sumedang Larang, meski secara resmi sebuah negeri berdaulat, faktanya telah lama menjadi bawahan Mataram.”
“Itulah, Kakang. Ingatkah Kakang bagaimana perang Sumedang Larang dengan Cirebon bisa berakhir?”, kembali Rangga Gempol bicara.
“Perang yang bermula ketika Ramanda Prabu Geusan Ulun tak bisa mengusir Ibunda Ratu Harisbaya yang menyelinap ke dalam tendanya di wilayah Keraton Cirebon ketika Ramanda sebentar mengaso sepulang dari Pajang. Itu terjadi sekitar tahun 1585. Alih-alih mengembalikan ibunda ke rama kandung saya, Raja Cirebon Kanjeng Panembahan Ratu, malah membawa Ibu Ratu Harisbaya ke Sumedang. Kita semua tahu, setelah itu dua negara yang sebelumnya bersahabat dan saling bantu itu terlibat perang campuh.”
“Peran itu memungkinkan masuknya campur tangan Mataram. Apalagi ayahanda Panembahan Ratu adalah juga menantu raja Pajang dari istri yang pertama,” Rangga Gempol sebentar terdiam.
“Baik Ayahanda Panembahan Ratu maupun Ramanda Prabu Geusan Ulun tak mampu melawan kehendak Sultan Agung, yang memang bagus menjadi penengah. Ibunda Ratu Harisbaya disepakati terus menjadi istri Ramanda Prabu Geusan Ulun, dan Rayi sendiri kemudian pindah ke Sumedang ikut Ibunda. Sebagai gantinya beberapa wilayah Sumedang jatuh ke tangan Ayahanda Panembahan Ratu, sehingga batas kekuasaan Sumedang ke timur berakhir di aliran Sungai Cilutung. Rajagaluh dan Sindangkasih pun kemudian masuk wilayah Cirebon. Perang pun berakhir, meski hubungan Sumedang dengan Cirebon tak pernah lagi seerat sebelumnya. Bahkan di Kabuyutan Sumedang, tak pernah lagi diizinkan para peziarah memakai batik, baju yang mencerminkan pakaian urang Wetan.” Rangga Gempol berhenti sejenak.
“Lalu, tidakkah berarti sejak itu baik Sumedang maupun Cirebon sebenarnya hanya bawahan, yang takluk kepada apa pun yang dikehendaki Sinuhun Mataram?” Kali ini giliran Rangga Gempol bertanya.
Ukur diam tak menjawab. Ia menyadari, benar juga apa yang dikatakan sang raja yang kini jadi sekadar wedana itu.
“Lalu tentang Praiangan, biarlah urang Wetan itu berpikir semau mereka. Dari dulu, sejak zaman karuhun kita telah menyebut tanah ini juga Priangan, bukan Praiangan. Asalnya dari kata Parahyangan yang artinya tempat tinggal segala Hyang[2], dewa-dewa yang harus kita hormati,” kata Rangga Gempol.
Ukur kembali terdiam. Hatinya yang semula galau laiknya anak abege alay, kini mulai tenang.
Ukur bersyukur dirinya telah berani bertanya langsung. Bayangkan, bila ia tetap memelihara pertanyaannya, memelihara kekecewaannya kepada Rangga Gempol, sampai kapan pun nonoman muda di sampingnya itu akan tetap ia pandang enteng. Malah mungkin saja ia lecehkan, sementara sebenarnya pikirannya sendirilah yang dangkal.
“Hatur nuhun Rayi, telah berkenan menghilangkan syak wasangka kakang dengan menjelaskan secara gamblang sikap yang Rayi pilih,” kata Ukur. Tanpa menyatakan langsung permintaan maaf, tangan Ukur terulur, mengajak Rangga Gempol bersalaman.
Saat
Wedana itu menyambutnya, tangan Ukur begitu lama menggenggam tangan pengagung
yang menyambutnya itu. Mulut Ukur komat-kamit, merapalkan doa dan permohonan
kepada Allah yang Maha Kuasa. Ia berharap persahabatan di antara keduanya bisa
lebih erat menjadi laiknya saudara. [bersambung]
[1] Praiangan juga Juliaen de Silva, orang bule pertama yang datang ke Bandung, dalam bahasa Belanda kuno pada 1641. Data tersebut ditulis di Landsarchivaris (Arsip Negara) yang ditemukan E.C Godee Molsbergen. Sementara istilah Priangan ini menurut Hageman berasal dari kata Prayangan yang artinya memberikan atau menyerahkan dengan hati yang suci. Istilah Priangan menurut Otto van Rees, disebut-sebut oleh Komandan Jacob Couper tahun 1684 ketika ia diperintah Gubernur Jendral VOC memberikan acte van aanstelingen kepada para Bupati Priangan.
[2] Menurut Ajat Rohaedi (alm), Priangan merupakan kontraksi dari kata Parahyangan yang artinya tempat tinggal Hyang yang harus dihormat.