UKUR
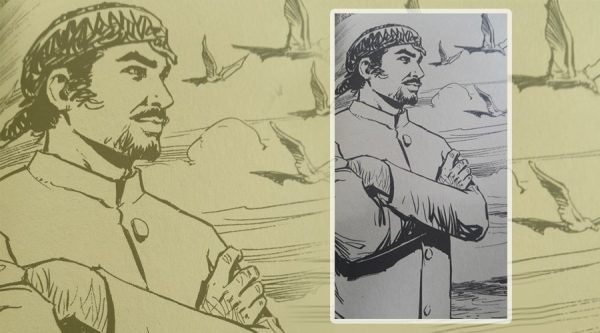
Kini jarak antara pasukan terdepan dengan benteng itu tak lebih dari empat puluh langkah. Hening, tak terdengar suara apa pun dari dalam benteng, menandakan sebagian besar penghuninya masih berada di alam mimpi.
Oleh : Darmawan Sepriyossa
Pengantar:
Setelah jatuhnya Kerajaan Majapahit, ratusan tahun kemudian kerajaan-kerajaan taklukan di seluruh Nusantara bangkit memupuk kekuatan. Yang paling mencorong adalah Kerajaan Mataram, pengklaim pewaris kekuasaan Majapahit. Sementara kekuatan asing yakni Portugis, Belanda dan Inggris, mulai pula datang menancapkan kuku kekuasaan mereka. Masing-masing dengan kerakusan dan kekejamannya sendiri. Pada saat itu, di Tanah Sunda muncul kekuatan yang mencoba menolak penjajahan, dipimpin seorang bernama Dipati Ukur.—
Episode-19
Para senapati segera memerintahkan para anak buah mereka untuk mendirikan tenda. Tak berapa lama seluruh lahan kosong di sepanjang Dermaga Cimanuk itu sudah penuh dengan tenda. Para prajurit pun sudah diperintahkan beristirahat. Sebagian langsung berbaring dalam tenda. Ada pula yang terjun ke batang sungai, mandi membersihkan diri, melunturkan daki dan debu yang menempel sepanjang perjalanan. Namun tak kurang-kurang pula yang langsung berjalan-jalan, berkeliaran entah mencari apa.
Esoknya pasukan Sumedang-Ukur belum bergerak karena pasukan Tumenggung Bahureksa pun belum juga kelihatan batang hidung mereka. Kesepakatannya jelas, tanggal 15 Agustus kedua pasukan akan bertemu di sini di Dermaga Cimanuk. Pasukan Tumenggung sebagian datang dari laut, masuk ke muara Cimanuk dan bertemu dengan pasukan Sumedang-Ukur. Sebagian lainnya yang jumlahnya berkali lebih banyak diperkirakan sudah akan datang dari arah jalanan pantai utara Jawa. Pasukan itu berangkat dari Mataram dengan menyusuri tepian pantai, hingga bergabung juga di tempat ini.
Hingga hari ketiga pasukan yang mereka tunggu tak juga datang. Bila pada hari pertama dan kedua keterlambatan kedatangan pasukan itu disyukuri karena membuat mereka bisa beristirahat dan membuka peluang para prajurit nakal untuk sedikit mencari kesenangan, tidak demikian saat ini.
Terlambat tiga hari dari perencanaan yang longgar, membuat pasukan Sumedang-Ukur bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan pasukan Mataram? Benarkah mereka jadi berangkat dan pada saatnya bersama-sama menyerbu Batavia? Atau tidakkah hanya pasukan Sumedang-Ukur yang sebenarnya diminta menyerang Kompeni, sementara Keraton Jawa sendiri tak mempersiapkan wadya bala?
Pada hari kelima dan enam, rumor sudah mulai meruap kuat di antara prajurit. Diam menunggu hanya membuat para prajurit Sumedang-Ukur bisa bertukar desas-desus yang akhirnya hanya membuat mental mereka kian terganggu. Ada kabar, Kompeni telah mencium gerakan itu dan menyerang Mataram lebih dulu. Timbul desas-desus saat itu pasukan Mataram telah dihancurkan di Cirebon, sebelum mereka tiba!
Persoalan makin rumit manakala senapati bagian perbekalan datang melapor bahwa logistik menipis. “Makanan hanya cukup buat tiga hari ke depan, Kanjeng Dipati,” kata dia saat datang melapor kepada Ukur. “Setelah itu prajurit kita akan bertempur dengan perut kelaparan.”
Ukur beberapa saat tepekur. Tak mungkin dirinya menggerakkan pasukan yang tengah diamuk lapar pada saatnya nanti. Ia kini dihadapkan kepada dilema, apakah harus sendirian menyerang Batavia tak bersama-sama pasukan Mataram, atau menunggu sampai kapan pun pasukan yang dijanjikan itu datang dan sama-sama maju menggempur?
“Kita tunggu sampai besok siang, bagaimana?” tanya Ukur kepada para senapatinya. Wajahnya meminta pertimbangan sahabatnya, Ngabei Tarogong.
“Iya, sebaiknya memang begitu. Bila besok siang wadya Mataram tak juga datang, mungkin kita bisa segera berangkat ke Batavia, tetap pada tujuan semula,” kata Ngabei Tarogong menjawabkan yang lain.
“Kaula berpendapat lain,” tiba-tiba sebuah suara memecah keheningan rapat. Ki Somahita ternyata. Ukur mempersilakan Umbul Sindangkasih itu meneruskan bicara.
“Kita tetap di sini, menunggu pasukan Mataram benar-benar datang. Bila mereka datang, kita bergerak bersama mereka menyerbu Batavia…”
“Kalau tidak?” Ngabei Tarogong memotong.
“Kalau tidak, ya kita tetap menunggu di sini.”
“Sampai kapan? Sudah enam hari kita menunggu, belum ada tanda-tanda hidung mereka jebul.[1]” Suara Ngabei Tarogong meninggi.
“Lagi pula, lihat ke dapur umum. Bekal kita sudah tipis. Kalau empat hari lagi pun mereka jadi datang, prajurit kita bertempur dalam lapar.”
Ki Somahita diam. Hanya mulutnya yang terkatup menunjukkan sikap sebal, dengan roman wajah yang menunjukkan ketidaksukaaannya kepada Ngabei Tarogong. Tentu saja, gampang dipastikan bahwa ia pun tak menyukai Ukur.
“Masih ada yang mau bicara dan mengajukan pendapat?” tanya Ukur. Rapat yang dihadiri para senapati dan umbul itu tetap hening.
“Baiklah kalau begitu. Kita akan menunggu sampai besok siang. Bila mereka tak muncul, kita jorag Batavia dengan kekuatan kita sendiri. Jangan pernah merasa dipermainkan Keraton Mataram. Sudah jadi garis tangan kita untuk menjaga harkat dan martabat prajurit Sunda. Kita tetap menggempur, ada atau tidak prajurit Mataram.”
Ukur berkata sambil menelisik satu demi satu wajah para senapatinya. Ia tak ingin satu wajah pun lolos dari tatapannya. Ia ingin tahu seberapa dalam semangat bertempur para senapatinya.
Malam itu para prajurit Sumedang-Ukur telah mendapatkan kepastian. Kini mereka rata-rata tidur lebih tenang, meski kepastian tentang apa yang akan dilakukan esok hari pun tetap saja membuat sebagian prajurit justru tegang. Terutama para prajurit baru dan tenaga relawan yang belum pernah mengalami jurit. Belum pernah membunuh, tegasnya. Mereka tak bisa membayangkan bahwa esok hari atau lusa harus membenamkan mata tombak ke lambung atau dada lawan, menebas leher lawan dan membuat para musuh perlaya. Harus, karena kalau tidak artinya merelakan nyawa mereka sendiri yang lepas meninggalkan raga.
Esoknya, waktu penentuan itu pun datanglah. Sejak pagi para senapati Sumedang-Ukur dan segenap prajurit yang ada berdebar-debar menantikan apa yang terjadi. Bila pasukan Mataram datang, setidaknya wadya bala mereka jauh lebih besar sehingga serbuan mereka akan menjadi laiknya air bah menerjang para Kompeni. Bila tidak, ya tak apalah. Banjir setidaknya. Atau mungkin hanya akan disebut genangan oleh para warga pinggiran Batavia yang gemar memakai pakaian bermotif kotak-kotak.
Waktu lohor datang dan pasukan yang dijanjikan itu pun tak juga kelihatan. Pasukan Sumedang-Ukur pun menggelar shalat jamaah. Saat matahari mulai bergeser dari ubun-ubun, Ukur mulai terlihat tak sabar. Seolah gatal, ia tak bisa diam duduk di satu tempat.
“Siapkan pasukan, kita berangkat!” akhirnya ia berkata kepada Ngabei Tarogong yang segera mengumpulkan senapati untuk menghimpun pasukan. Masih perlu sehari perjalanan kaki dengan istirahat yang cukup untuk tiba di Batavia. Lusa adalah hari yang menentukan apakah saat itu dirinya masih hidup dan menemani sahabat dan tuannya, Ukur, atau tidak.
Meski secara jarak Karawang-Batavia sudah dekat, pergerakan pasukan Sumedang-Ukur tak lagi seperti sebelumnya yang relatif cepat. Semakin ke Batavia justru gerakan pasukan lebih lambat dan penuh kehati-hatian. Ukur menghendaki mereka sebisa mungkin menghindari jalan terbuka yang membuat pasukan besar itu dengan mudah terlihat mata-mata musuh. Ia ingin kedatangan pasukan yang hendak menggempur Batavia itu bisa bergerak secara diam-diam dan rahasia, sehingga manakala serangan dilancarkan faktor kejutnya masih bertenaga.
Karena itulah, selain pasukan pun tak bisa lagi melaju bersamaan, Ukur juga menetapkan bahwa pasukan hanya bergerak setelah malam tiba. Laporan telik sandi Sumedang menyarankan agar pasukan bersembunyi di daerah Jatina Nagara[2], area hutan berawa-rawa yang merupakan wilayah Kesultanan Banten. Tempat itu hanya berjarak beberapa kilometer sebelah tenggara kota Batavia, sehingga ideal untuk bersembunyi dan memulai serangan.
Berdasarkan rapat pimpinan perang yang digelar malam itu, disepakati serangan akan dimulai pada pagi hari 23 Agustus. Pasukan akan dibagi menjadi empat batalion, masing-masing beranggotakan dua ribu prajurit. Masing-masing batalion itu berada di bawah pimpinan Ngabehi Tarogong, Ki Demang Saunggatang, Umbul Sagaraherang dan Tumenggung Taraju.
“Bagaimana, ada keberatan?” tanya Dipati Ukur setelah putusan itu ia ambil. Semua senapati terdiam.
“Sapuk! Setuju!” kata Ngabehi Astamanggala, Kepala Keumbulan Cihaurbeuti. Di antara para pimpinan pasukan, selain Ngabehi Tarogong, Ki Astamanggala memang tergolong senapati yang menonjol dalam pemikiran dan diplomasi. Tak hanya itu, Ki Astamanggala pun dikenal sebagai senapati yang suka akan kesusasteraan. Hampir setiap waktu luangnya dipenuhi kegiatan membaca lontar-lontar tua berisikan babad, hikayat dan pantun. Dalam soal adu jurit ia tak begitu menonjol.
Sedetik kemudian semua pimpinan pasukan menyatakan persetujuan mereka. “Sapuk!” teriak mereka berbarengan hingga suaranya menimbulkan getar, membuat para prajurit terkejut dan bertanya-tanya.
“Baiklah,” kata Ukur. “Temui pasukan masing-masing, perintahkan istirahat dan berjaga-jaga. Besok setelah subuh, kita akan menggempur benteng pertahanan Kompeni.”
***
Tepat setelah bergantian melaksanakan shalat Subuh, pasukan Sumedang-Ukur segera bergerak. Selain dibantu lebatnya hutan di sekitar Jatina Nagara yang memanjang hingga ke dekat wilayah Batavia, kegelapan yang belum sepenuhnya sirna pun membantu gerakan pasukan Sumedang-Ukur mendekati benteng tempat pasukan Kompeni bersarang. Kini jarak antara pasukan terdepan dengan benteng itu tak lebih dari empat puluh langkah. Hening, tak terdengar suara apa pun dari dalam benteng, menandakan sebagian besar penghuninya masih berada di alam mimpi.
Ukur memberikan tanda agar pasukan berhenti dan bersembunyi di keremangan. Semua pasukan tiarap. Kuda-kuda memang sudah diikat di hutan Jatina Nagara, sengaja disembunyikan. Hanya pimpinan prajurit dan para kepala batalion yang masih diizinkan menunggang kuda. Itu pun di belakang, menghindari kemungkinan kuda-kuda itu meringkik dan bisa membangunkan musuh dengan prematur.
Melihat pemandangan benteng kokoh tinggi yang ada di depannya, Ukur tersadar ada yang selama ini luput ia pikirkan. Menimbang jumlah prajurit, kecil kemungkinan para serdadu Kompeni itu akan melayani mereka dengan cara begalan pati di lapangan, beradu pasukan. Ukur mencoba berpikir sebagai orang-orang Kompeni yang kini berada dalam benteng, cara paling aman bagi pasukan Kompeni adalah tetap berada di dalam benteng tersebut. Apalagi mereka punya meriam dan bedil yang lebih digjaya untuk peperangan jarak jauh. Bodoh bila mereka keluar benteng hanya untuk melayani tantangan jurit di medan terbuka. Artinya kini bukan saatnya Ukur dan pasukannya mengedepankan taktik dan formasi perang ratu ing bala sariwu[3], meski strategi itu telah berabad-abad terbukti ampuh dalam peperangan terbuka.
“Siapkan pasukan bandring[4] dan panah!” perintah Ukur. Perintah itu segera tersampaikan dengan cara bisik-bisik estafet.
“Siapkan minyak jelantah. Kita akan menggempur benteng dengan panah dan peluru api!” Tak berapa lama bergentong-gentong minyak jelantah sisa penggorengan di bawa ke muka. Pasukan panah mulai melapisi ujung anak panah mereka dengan kain goni yang gampang terbakar. Dengan tak mengeluarkan suara tapi bergerak cepat, anggota pasukan panah sudah pula mencelupkan ujung anak panah masing-masing ke dalam minyak jelantah.
“Tunggu sampai aba-aba tiba, baru lontarkan. Sasarannya bangunan dan rumah para pengisi benteng,” kata Ukur. Pesan itu pun segera bergerak berantai.
Waktu seolah lamban bergerak. Keheningan mencekam menjadi atmosfer udara. Entah mengapa, tak seekor pun ayam jago saat itu berkokok. Hening, diam, mewujudkan sunyi yang lampus. Para prajurit Sumedang-Ukur pun kaku tak bergerak, beberapa tak sadar menahan nafas seiring suasana yang kian mencekam.
“Serang!” kata Ukur, tapi dengan suara ditahan. Ia tak ingin justru suara teriakannya yang membuat musuh-musuh di dalam benteng terkejut. Bukan, lebih baik nyala api yang membakari rumah merekalah yang melakukan kejutan itu.
“Ser! Slep! Set!” Suara ratusan, kalau bukan ribuan anak panah melesat menuju sasaran. Kalau hanya dilihat, ratusan anak panah dan peluru ketapel yang melesat membelah udara pagi yang masih remang-remang itu terlihat begitu indah. Garis-garis cahaya akibat lesatan dan lontarannya menimbulkan nuansa warna kuning yang kontras dengan keremangan pagi. Tetapi begitu terdengar jeritan penghuni benteng yang melihat api membakar rumah-rumah mereka, keindahan itu langsung sirna. Yang ada hanya api, lambang angkara murka yang bagaimana pun saat itu tengah berjaya.
“Seraaang!” Kali ini Dipati Ukur berteriak lantang, memberikan komando pertama penyerangan. Sontak keheningan pun pecah. Teriakan para prajurit disertai lompatan mereka untuk bersicepat menuju musuh, terdengar di berbagai penjuru. Kegaduhan pun kedengaran terjadi di dalam benteng. Musuh telah tersadar akan serangan, tak hanya karena api yang di beberapa tempat mulai berkobar, melainkan pula dengan sekian banyak teriakan peperangan yang riuh rendah.
“Panjat! Segera panjat benteng!” teriak Ngabehi Tarogong. Sayang, tak seorang pun yang sejak awal dipersiapkan untuk memanjat benteng. Akibatnya tak ada persiapan untuk membawa tangga atau pun gulungan tambang berujung pengait besi untuk memanjat. Namun demikian beberapa prajurit mematuhi perintah dan mencoba memanjat benteng hanya dengan menggunakan tangan dan keahlian memanjat semata.
Tiba-tiba beberapa moncong bedil menjulur dari atas benteng, mengarah kepada mereka.
Dor! Dor! Beberapa letusan terdengar, diiringi raung kesakitan para prajurit yang tertembus timah panas. Setelah itu beriringan beberapa bunyi berdebuk, tubuh membentur tanah.
“Hujani dengan anak panah dan peluru ketapel!” teriak Demang Saunggatang.
“Ser! Slep! Set!” kembali ratusan anak panah melesat dari pihak Ukur. Tiba di tujuan tak kurang-kurang serdadu Kompeni terpanggang anak panah itu. Kebanyakan anak panah itu menancap di leher akibat para serdadu terlalu bernafsu ingin mencari sudut bidik yang nyaman bagi moncong bedil mereka.
Sepasukan prajurit Ukur terlihat mendorong tiga gerobak berisi batang kayu jati keras yang ujungnya diruncingkan guna membedol pintu benteng. Begitu tiba di muka pintu, gerobak itu dimundurkan beberapa langkah untuk serta merta dengan kekuatan penuh dibenturkan ke daun pintu gerbang yang tebal itu, untuk membobolnya. Hal itu dilakukan berulang-ulang. Namun pintu itu masih tetap kokoh berdiri.
Di dalam benteng, Letnan Jacob van der Plaetten hilir mudik memberikan perintah kepada para serdadunya. Kebanyakan serdadu bayaran. Pemerintah Kerajaan Belanda menetapkan personel VOC sedapat mungkin direkrut bukan dari warga Belanda, kecuali para bekas narapidana atau tentara yang melakukan desersi. Alhasil mayoritas personel pasukan VOC memang para manusia yang hidup dari perang, dari membunuh manusia lain.
Tak hanya berisikan para ronin, samurai tak bertuan dari Jepang yang saat itu tengah bergolak, serdadu VOC juga dibangun dari para mardijker yakni para bekas budak yang dibebaskan, budak-budak dari Bali, pria-pria Ambon yang direkrut khusus, serta sekian ratus orang Tiongkok dengan taucang[5] yang melambai-lambai saat mereka bergerak. Van der Plaetten saat itu bertelanjang dada, hanya sempat meraih pistol dan pedangnya manakala ramai-ramai teriakan dan jeritan membangunkan tidurnya yang berpeluh.
“Jaga
jangan sampai ada seorang Mataram pun yang bisa naik dan masuk area benteng!”
teriaknya memerintah. “Siapkan meriam!” [bersambung]
[1][1] Datang, tepatnya, terlihat datang
[2] Setelah sebagian wilayahnya dibeli Cornelis Senen, wilayah itu berganti nama menjadi Meester Cornelis, sebelum kemudian pemerintah pendudukan Jepang memberinya nama Jatinegara.
[3] Formasi pasukan ala Kerajaan Sunda yang terbukti ampuh dalam peperangan kuno.
[4] Ketapel
[5] Kucir rambut yang biasa dipakai laki-laki Tiongkok sejak awal-awal zaman Dinasti Qing (1644-1911)







