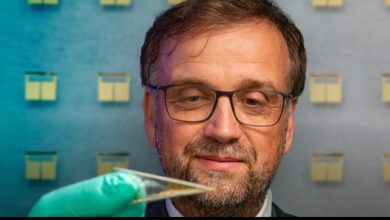Sastraku Jauh di Pulau

Dialog-dialog padat tanpa klise, ensembel akting yang memukau, panorama sebuah pulau kecil yang dikelilingi lautan, artefak-artefak sisa pendudukan Jerman, dan editing cut-to-cut yang rapi, membuat denyut kehidupan komunitas penyuka sastra sebelum datangnya komputer dan era digital ini mengundang badai nostalgia, ketika pada satu masa profesi penulis—yang medioker sekali pun—begitu penting bagi ruh sebuah komunitas.
Oleh : Akmal Nasery Basral
JERNIH– Lokasi Pulau Guernsey lebih dekat ke Prancis meski termasuk wilayah Inggris. Pada tahun 1941, tentara Jerman yang sedang meluaskan kekuasaan di Eropa Barat menduduki pulau itu.
Warga diawasi ketat, jam malam diterapkan. Empat orang penduduk ditangkap saat melanggar aturan karena masih berkeliaran di gelap malam. Ketika diinterogasi tentara, Elizabeth McKenna, yang merupakan perempuan termuda dari mereka menjawab tanpa takut, “Kami anggota Klub Sastra Guernsey dan Masyarakat Penyuka Pai Kulit Kentang yang baru selesai acara membahas satu roman,” katanya menahan cekikikan.
Adegan ini membuka 124 menit film ”The Guernsey Literature and Potato Peel Pie Society” (Sutradara Mike Newell, 2018) dari novel berjudul sama karya Mary Ann Shaffer dan Annie Barrows (2008) yang membawa penonton pada eksotisme dunia literasi di tengah suasana PD II.
Adegan berikutnya terjadi lima tahun kemudian, pada 1946, ketika seorang penulis pemula Juliet Ashton (diperankan aktris berwajah klasik Lily James) yang tinggal di London sedang mempromosikan buku terbarunya. Dia bukan penulis meteorik. Karya pertamanya tentang Anne Brontë—bungsu dari tiga bersaudari adik Charlotte dan Emily Brontë yang lebih masyhur—hanya terjual 28 eksemplar. Seakan mengetahui sejak awal akan nasib buruk karya debutannya, Juliet memakai nama samaran Izzy Bickerstaff.
Untuk bisa bertahan hidup, Juliet mengandalkan pendapatan sebagai penulis rubrik sastra The London Times. Di tengah kesibukannya itu dia menerima sepucuk surat dari Dawsey Adams, seorang peternak babi warga Guernsey yang minta tolong agar dibelikan sebuah buku karya Charles Lamb karena tak ada toko buku di Guernsey.
Buku itu dibutuhkan klub sastra mereka yang mulai aktif lagi bertemu setiap Jumat malam setelah Tentara Jerman hengkang karena kalah perang. Juliet menyanggupi permintaan Dawsey, sehingga terjadi korespondensi lanjutan.
Semakin banyak info yang diketahui Juliet tentang klub sastra unik itu (“mengapa nama klub menggunakan nama pai kulit kentang segala?”) membuatnya ingin mengunjungi Guernsey, sekaligus sebagai bahan liputan untuk The London Times. Keinginan sederhana itu tak mudah terwujud karena pacar Juliet, seorang diplomat AS bernama Mark Reynolds, ingin mereka segera bertunangan dan pindah ke New York City, tinggal di apartemen yang menghadap Central Park. Untungnya, Mark bisa memahami keinginan Juliet yang ingin lebih dulu berkunjung ke Guernsey sebelum mereka ke AS. Juliet pergi sendirian.
Di Guernsey, kondisinya jauh lebih buruk dari bayangan Juliet. Selain disambut Dawsey, anggota klub lain adalah seorang nenek ketus Amelia Maugery, seorang perempuan penjual miras oplosan Isolasi Pribby, dan seorang tukang pos tua bernama Eben Ramsay yang ahli membuat pai kulit kentang polos (“tanpa mentega, tanpa tepung,” ujarnya setiap ditanya resepnya). Eben punya cucu seorang bocah lelaki bernama Eli, penggemar karya-karya Kipling, dan Amelia punya seorang cucu perempuan yang masih balita bernama Kit.
“Di mana Elizabeth McKenna yang mendirikan klub ini?” tanya Juliet.
“Dia tak bisa ikut, karena sedang di luar pulau,” jawab Amelia.
Meski Juliet bukan penulis besar, namun di tengah kondisi Guernsey yang minus, kehadirannya disambut bak tokoh sastra terkemuka karena tempat itu bukan saja tak melahirkan penulis, juga sangat jarang dikunjungi penulis sungguhan.
Sambutan mereka yang ramah, dan misteri yang satu persatu datang menghampiri, membuat Juliet memutuskan tinggal lebih lama di sana sampai dia mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dengan McKenna, perempuan muda pemberani penyuka sastra yang tak ragu menghadang dan memaki-maki petinggi militer Jerman saat sedang berparade di jalan utama Guernsey.
Tayangan bolak-balik antara tahun 1946 (saat Juliet di Guernsey) dan tahun 1941 (ketika Tentara Jerman masih bercokol) menjadi tontonan mengasyikkan karena dialog-dialog padat tanpa klise, ensembel akting yang memukau (peran Juliet awalnya akan dimainkan Kate Winslet yang sudah tanda tangan kontrak, namun seiring perubahan jadwal produksi akhirnya Kate mundur dan Lily James menggantikan dengan kualitas akting berkilau), panorama sebuah pulau kecil yang dikelilingi lautan, artefak-artefak sisa pendudukan Jerman, dan editing cut-to-cut yang rapi, membuat denyut kehidupan komunitas penyuka sastra sebelum datangnya komputer dan era digital ini mengundang badai nostalgia ketika pada satu masa profesi penulis—yang medioker sekali pun—begitu penting bagi ruh sebuah komunitas. Meski jauh terpencil di sebuah pulau. Sangat layak tonton. [ ]
*Akmal Nasery Basral, wartawan, novelis dan cerpenis