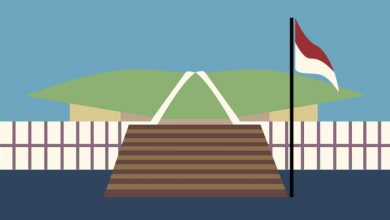Seperti dinyatakan salah satu anggota Divisi Atomwaffen yang sekarang sebagian besar sudah tidak berfungsi, “Orang-orang Yahudi adalah virusnya, orang kulit berwarna dan homoseksual, mereka adalah gejalanya.” Kedua musuh itu dipandang jahat dan pertanyaan bagi teroris bukanlah musuh mana yang harus hidup dan mana yang harus mati—keduanya pada akhirnya harus dilenyapkan—melainkan pengurutan, sehingga musuh mana yang harus dibidik terlebih dahulu.
Oleh : Jacob Ware dan Colin P. Clarke*
JERNIH–Komunikasi internal kelompok teroris sering kali mengungkapkan pertikaian atas berbagai masalah di antara mereka, mulai dari cara mengalokasikan sumber daya hingga ketidaksepakatan tentang personel dan keuangan. Satu area di mana teroris biasanya berbeda adalah pemilihan target, sebuah masalah yang mengganggu kelompok-kelompok di seluruh spektrum ideologis.
Kelompok-kelompok salafi-jihadi telah lama memperdebatkan cara yang paling bijaksana untuk mencapai tujuan mereka dalam mengusir kekuatan-kekuatan “imperialis” Barat seperti Amerika Serikat dan Israel, dan membangun kembali kekhalifahan yang hilang. Perdebatan ini secara tradisional dipecah menurut paradigma “musuh dekat” versus “musuh jauh”.
Konsep ini awalnya dikemukakan pakar Islam , Mohammed Abd al-Salam Faraj, yang berusaha meyakinkan sesama jihadis, termasuk sesama warga Mesir Ayman al-Zawahiri, untuk memprioritaskan penggulingan rezim Arab despotik yang mengatur kehidupan sehari-hari mereka—yang disebut Faraj sebagai “ musuh dekat”—sebelum mencoba menghadapi “musuh jauh” dari kekuatan “imperialis” seperti Amerika Serikat dan Israel. Faraj berpendapat bahwa para penguasa Arab (biasanya pro-Barat) ini telah mengizinkan “kafir” untuk campur tangan dalam urusan lokal, memfasilitasi intrik manipulatif kekuatan asing dalam budaya dan politik Timur Tengah. Oleh karena itu, menggulingkan para pemimpin ini dan menggantinya dengan penguasa Muslim sejati adalah kunci untuk mengakhiri imperialisme.
Pemimpin Al-Qaidah, Usamah bin Ladin kemudian membalikkan penekanan, dengan alasan bahwa “musuh jauh” adalah sumber perselisihan yang sebenarnya di dunia Arab dan Islam, yang secara langsung bertanggung jawab atas perang budaya, agama, dan ekonomi melawan rakyatnya. Bin Ladin, yang sangat marah dengan kehadiran militer AS di Arab Saudi, percaya bahwa mencoba untuk menggulingkan diktator lokal adalah sia-sia sementara mereka menikmati dukungan dari negara-negara Barat yang kuat. Karena itu, dia membantah dengan mengatakan bahwa para jihadis harus memprioritaskan menyerang Amerika Serikat, Eropa, dan Israel untuk meyakinkan mereka agar menarik dukungan itu. Begitu mereka melakukannya, rezim lokal, yang kehilangan dukungan akar rumput, akan jauh lebih mudah untuk digulingkan.
Ini bukan hanya debat teoretis, tetapi debat dengan konsekuensi yang sangat nyata—dan sangat berdarah—. Pandangan Faraj membawanya untuk memainkan peran penting dalam pembunuhan tahun 1981 terhadap Presiden Mesir Anwar Sadat, di mana Faraj dieksekusi pada tahun berikutnya. Dan, seperti yang diketahui dunia sekarang dengan sangat baik, preferensi bin Ladin untuk menyerang musuh jauh membuatnya melancarkan serangan yang menghancurkan kedutaan besar AS di dua ibu kota Afrika pada tahun 1998, di USS Cole di Teluk Aden pada tahun 2000, dan di New York City. dan Washington pada 11 September 2001.
Tetapi paradigma musuh dekat dan musuh jauh tidak eksklusif untuk kelompok jihad. Sebaliknya, teroris sayap kanan dan ekstremis juga mulai berpikir serupa. Seperti yang terjadi di kalangan jihad, perdebatan antara anggota sayap kanan tentang musuh mana, dekat atau jauh, yang harus dianggap sebagai ancaman yang lebih serius adalah memecah belah ideolog ekstremis dan mengarah pada perselisihan mengenai pemilihan target, taktik, dan strategi. Dan mengidentifikasi faksi gerakan mana yang lebih mungkin menyerang situs tertentu dapat membantu para profesional kontraterorisme melarang plot berikutnya atau setidaknya membantu kemungkinan menargetkan pertahanan yang didirikan.
Konsep “Great Replacement”—gagasan bahwa orang kulit putih kelahiran asli Amerika Serikat dan Eropa secara sengaja digantikan oleh imigran non-kulit putih—telah menjadi kekuatan ideologis pendorong yang memotivasi tindakan paling modern dari kekerasan sayap kanan. Seperti teori “genosida kulit putih” serupa, gagasan ini penting karena secara eksplisit mendefinisikan musuh internal dan eksternal dari mereka yang “menyerang” serta mereka yang diduga mengatur “invasi”.
Terlepas dari lokasi fisik, maka, musuh jauh bagi jihadis dan ekstremis sayap kanan adalah penyerbu yang dirasakan, dan musuh dekat adalah siapa pun yang mengizinkan atau memfasilitasi ‘invasi’ itu.
Dalam banyak hal, konsep ini mirip dengan pesan yang disampaikan Bin Ladin dan kepala propagandis al-Qaidah kepada para pengikut mereka: Barat sedang berperang dengan Islam dan adalah tugas Andalah melawan ancaman eksistensial itu. Dengan kata lain, terorisme adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang-orang Anda (bagi bin Ladin, ini berarti Muslim di seluruh dunia, atau umat, dan untuk ekstremis sayap kanan, itu adalah ras kulit putih) dari kepunahan.
Yang terpenting, dalam kedua kasus, perbedaan dekat dan jauh bukanlah geografis. Sebaliknya, ini simbolis, mengacu bukan pada kedekatan ekstremis dengan penindas yang mereka rasakan, tetapi pada peran penindas itu dalam “penggantian” budaya, agama, ekonomi, atau demografis klan ekstremis.
The Great Replacement telah dirujuk oleh beberapa teroris sayap kanan paling terkenal dalam beberapa tahun terakhir, termasuk Anders Breivik, Brenton Tarrant, dan Patrick Crusius—yang, masing-masing, menyerang gedung pemerintah dan kamp pemuda di Norwegia, sebuah masjid di Selandia Baru, dan toko Walmart di Texas—antara lain. Manifesto yang ditinggalkan oleh para ekstremis ini saling membangun dan merujuk satu sama lain, berusaha untuk memajukan ide-ide ini dan menso-sialisasikannya ke seluruh gerakan. Namun pemilihan target mereka berbeda, sebuah bukti bagaimana teroris sayap kanan, seperti rekan-rekan jihad mereka, mengembangkan persepsi yang berbeda-beda tentang musuh utama perjuangan mereka.
Mungkin tendangan voli paling menakutkan dalam gelombang terorisme sayap kanan saat ini yang melanda dunia Barat terjadi di Christchurch, Selandia Baru, pada tahun 2019. Pria bersenjata itu, seorang penganut supremasi kulit putih bernama Brenton Tarrant, memasuki dua masjid dan melepaskan tembakan, membunuh 51 jemaah yang tidak bersalah, dan menyiarkan langsung serangan pertama di Facebook. Manifesto Tarrant, yang berjudul “Great Replacement,” adalah bukti pelaksanaan rencana musuh jauh: “Kami mengalami invasi pada tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah,”katanya dalam sebuah pernyataan riang untuk membenarkan pembunuhan massalnya.
Penargetan musuh jauh berfokus pada kekerasan terhadap imigran nyata atau yang dirasakan, termasuk Muslim, Asia, dan Hispanik, tetapi juga, mungkin secara berlawanan, Afrika-Amerika. Meskipun kehadiran mereka selama berabad-abad di Amerika Serikat dan Barat, orang Afrika-Amerika biasanya masih digambarkan oleh supremasi kulit putih sebagai penjajah budaya dan sosial.
Dylann Roof, yang pada tahun 2015 membunuh sembilan pengunjung gereja di Gereja Mother Emanuel di Charleston, Carolina Selatan, dilaporkan memberi tahu para korbannya selama mengamuk, “Saya harus melakukannya. Kalian memperkosa wanita kami dan mengambil alih negara kami. Kalian harus pergi!” Bahasa serupa, yang merujuk pada penggantian etnis atau ras, sering digunakan terhadap komunitas imigran.
Serangan yang menargetkan musuh jauh sering kali merupakan “kanan-jauh” yang paling jelas karena mereka dengan sangat jelas menargetkan “liyan” secara etnis atau agama.
Faktanya, ‘far-enemy terrorist’ seringkali sangat membenci orang luar sehingga terkadang mereka gagal mengidentifikasi korbannya dengan benar. Dalam satu serangan di sebuah bar di Olathe, Kansas, pada tahun 2017, seorang imigran India dibunuh oleh seorang penyerang yang mengira dia orang Iran, yang menjadi target. Tentu saja, perintah yang dia berikan kepada para korbannya—“keluar dari negaraku”—tidak spesifik untuk ras atau asal negara mereka: Menjadi bukan kulit putih sudah cukup untuk membuat mereka mati.
Serangan far-enemy, dengan demikian, sangat cocok dengan citra pahlawan simbolis yang suka disampaikan oleh supremasi kulit putih tentang tentara kulit putih yang mengangkat senjata melawan gerombolan penjajah, semacam “barbarians at the gates.”
Terlepas dari persepsi yang dapat dimengerti bahwa terorisme sayap kanan terutama menargetkan etnis dan agama minoritas, insiden sayap kanan paling mematikan selama 30 tahun terakhir sebagian besar menargetkan rekan senegaranya, dengan penargetan musuh dekat sering melampaui pemikiran “ Great Replacement ” untuk melibatkan pertahanan yang lebih luas terhadap serangan yang dirasakan terhadap hak-hak penyerang.
Serangan Timothy McVeigh di Kota Oklahoma pada tahun 1995 ditujukan pada lembaga penegak hukum federal yang berkantor di Gedung Federal Alfred Murrah. Pemboman itu tetap menjadi serangan teroris sayap kanan modern paling mematikan di Barat, menewaskan 168 orang dan melukai hampir 700 lainnya.
Pada tahun 2011, neo-Nazi Norwegia Anders Breivik membunuh 77 orang dalam serangan kembar di kawasan pemerintah Oslo dan kamp musim panas yang diselenggarakan oleh sayap pemuda Partai Buruh Norwegia. Dan serangan tahun 2021 di Gedung Capitol, AS, menargetkan politisi dari kedua partai, mungkin terutama Wakil Presiden Republik Mike Pence, yang nyaris lolos dari kerumunan yang memintanya dihukum gantung.
Rencana “near-enemy” Breivik sebenarnya sangat rinci sehingga dia dengan cermat menguraikan kategorisasinya dalam manifestonya: kategori musuh A, B, dan C, mulai dari pemimpin politik dan media, hingga tokoh yang lebih periferal di ruang politik. Tetapi, yang terpenting, semuanya domestik. Selain itu, Breivik memohon para pengikutnya untuk tidak secara langsung menyerang komunitas imigran yang dia rasa sedang memberantas proyek Eropa: “Kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menggulingkan budaya Marxis jika kita membuang energi dan upaya kita untuk memerangi Muslim.” Ironisnya, keputusannya diabaikan oleh murid utamanya, Brenton Tarrant, meskipun yang terakhir menulis dalam manifestonya sendiri bahwa dia “hanya benar-benar mengambil inspirasi sejati dari Knight Justiciar Breivik.”
Ada elemen non-rasial yang signifikan dalam penargetan musuh, terutama jika ditujukan pada pemerintah. Dalam kasus tersebut, pemerintah dipandang memfasilitasi serangan yang lebih luas terhadap “hak” penyerang yang paling dihargai—seperti hak senjata, agama, atau dalam kasus 6 Januari, terpilihnya kembali Donald Trump.
“Near-enemy terrorist”, kemudian, akan memilih salah satu dari berbagai kemungkinan target. Politisi sering menjadi sasaran kebijakan kontroversial mereka. Orang-orang Yahudi juga menemukan diri mereka di garis bidik karena segudang obsesi konspirasi sayap kanan atas dugaan kontrol mereka atas masyarakat. Atau para ekstremis mungkin memfokuskan kekejaman mereka terhadap orang kulit putih yang dianggap acuh tak acuh atau berpuas diri, terutama apa yang mereka lihat sebagai “pengkhianat ras” dalam hubungan antar-ras.
Lainnya, termasuk kolaboratif neo-Nazi yang lebih baru seperti Divisi Atomwaffen dan The Base, telah menunjukkan kesediaan untuk menargetkan infrastruktur dalam tujuan mereka untuk “mempercepat” destabilisasi masyarakat.
Namun, teroris musuh dekat (near-enemy terrorist) masih sering dimotivasi oleh pemikiran “Great Replacement”. Mungkin tidak ada contoh yang lebih jelas daripada Robert Bowers, yang membunuh 11 orang di sinagoga Tree of Life di Pittsburgh pada tahun 2018. Bowers menargetkan sebuah sinagoga karena dia merasa mereka berpartisipasi dalam impor penduduk yang disebut “karavan migran” dari Amerika Latin. “Hebrew Immigrant Aid Society suka membawa penjajah yang membunuh orang-orang kita,” tulis Bowers di situs media sosial sayap kanan “Gab”.
“Saya tidak bisa ongkang-ongkang kaki melihat orang-orang saya dibantai.” Pesan-pesan yang membesarkan diri seperti itu mengisyaratkan citra dirinya sebagai seorang martir untuk tujuan yang lebih besar.
Kasus Pittsburgh mengilustrasikan bahwa garis antara dua kategori itu tidak jelas: ideologi, serta keluhan yang mendasarinya, melampaui kedua pengelompokan, dan keputusan penargetan biasanya sangat pribadi. “The near enemy of the far right”, dengan demikian, adalah sama dengan Salafi jihadis: rezim lokal dan gerakan politik yang memungkinkan, jika tidak dengan sengaja mendorong terjadinya infiltrasi para “penyerbu”—dalam hal ini, biasanya para imigran— atau terkikisnya hak-hak atau nilai-nilai ekstremis ultra-konservatif. Pembingkaiannya, dengan kata lain, sama, membedakan antara musuh dekat lokal yang memfasilitasi kerusakan budaya yang ditimbulkan oleh kekuatan luar, dalam hal ini diwakili oleh musuh jauh yang menyerang.
Atau, seperti yang dinyatakan oleh salah satu anggota Divisi Atomwaffen yang sekarang sebagian besar sudah tidak berfungsi, “Orang-orang Yahudi adalah virusnya, orang kulit berwarna dan homoseksual, mereka adalah gejalanya.” Kedua musuh itu dipandang jahat dan pertanyaan bagi teroris bukanlah musuh mana yang harus hidup dan mana yang harus mati—keduanya pada akhirnya harus dilenyapkan—melainkan pengurutan, sehingga musuh mana yang harus dibidik terlebih dahulu.
Sebagai latihan akademis, membandingkan paradigma “musuh dekat” dan “musuh jauh” di seluruh ideologi sangat menarik. Tapi dari segi praktis, apa sebenarnya artinya bagi penegak hukum dan badan intelijen? Bisakah itu membantu menginformasikan cara praktisi kontraterorisme dan pembuat kebijakan mendekati masalah ini?
Ketika kelompok teroris berbeda dalam pemilihan target, hal itu dapat menyebabkan perpecahan yang lebih luas. Sekali lagi, al Qaidah adalah instruktif dalam hal ini. Pada pertengahan 2000-an, muncul celah antara kepemimpinan al-Qaidah di Pakistan dan al-Qaidah di Irak, di mana cabangnya saat itu dipimpin oleh militan Yordania, Abu Musab al-Zarqawi. Sementara bin Ladin dan para pemimpin senior lainnya ingin terus memprioritaskan serangan ke Barat, Zarqawi terutama berfokus pada musuh dekat, bekerja untuk mengeksploitasi sektarianisme di Irak, menyoroti perbedaan antara Arab Sunni dan kepemimpinan mayoritas Syiah di Baghdad.
Prioritas target yang berbeda merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap krisis dalam jihadisme dan kemunculan ISIS beberapa tahun kemudian.
Di paling kanan, ada lebih sedikit perbedaan antara kelompok dan lebih banyak antara faksi, dengan kategori yang berbeda menyerang target yang berbeda. Seorang ekstremis anti-pemerintah akan jauh lebih mungkin untuk menyerang musuh dekat penguasa federal yang bertanggung jawab atas kebijakan yang tampaknya represif dan tirani yang membatasi hak senjata dan kebebasan sipil. Neo-Nazi juga tampaknya akan memprioritaskan penghapusan musuh dekat dalam kasus mereka kelas politik dan ekonomi Yahudi yang serba bisa.
Tetapi kaum rasis, xenofobia, dan neo-Konfederasi, yang lebih dimotivasi oleh keluhan etnis daripada pandangan politik apa pun, mungkin lebih menyukai musuh jauh, memberikan pukulan yang lebih nyata kepada mereka yang mereka rasa mengancam posisi istimewa mereka sebagai orang kulit putih. Karena sayap kanan lebih terdesentralisasi, perbedaan dalam penargetan mungkin memiliki dampak yang tidak terlalu merugikan, karena node yang berbeda dalam jaringan yang lebih luas terbiasa berfungsi secara independen satu sama lain, sebuah fenomena yang berlaku baik di tingkat taktis maupun strategis.
Secara praktis, pemilihan target yang berbeda juga dapat memengaruhi bagaimana kita harus bereaksi terhadap serangan segera setelahnya. Setelah kengerian di Christchurch, warga Selandia Baru berkumpul di sekitar komunitas Muslim. “Rasisme ada, tetapi tidak diterima di sini. Serangan terhadap kebebasan salah satu dari kita yang menjalankan keyakinan atau agama mereka tidak diterima di sini, ”kata Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern.
Tetapi kekerasan akibat “near enemy” sering merayap di sepanjang perpecahan politik, sebagaimana dibuktikan dengan menyakitkan oleh ketidakmampuan Amerika Serikat untuk bersatu ketika satu polisi terbunuh dan lebih dari 100 petugas terluka selama dan setelah 6 Januari. Format terakhir mungkin membutuhkan lebih banyak nuansa. reaksi, menarik kurang untuk nilai-nilai nasional daripada sensibilitas moral.
Amerika Serikat dan sekutunya telah menghabiskan sebagian besar dari dua dekade terakhir dengan fokus hampir secara eksklusif pada ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok jihad, bahkan ketika ekstremisme sayap kanan menyebar di tengah-tengahnya.
Akibatnya, ada kurva belajar yang curam dalam memahami perluasan gerakan ekstremis sayap kanan dan perbedaan ideologis yang penting dalam berbagai alirannya. Lebih jauh lagi, melihat ancaman melalui lensa paradigma “musuh dekat” dan “musuh jauh” menawarkan wawasan penting tentang pemilihan target sayap kanan dan tempo operasional, membantu alokasi sumber daya pasukan kontraterorisme dan memprioritaskan langkah-langkah defensif. [Foreign Policy]
Jacob Ware adalah rekan peneliti untuk kontraterorisme di Council on Foreign Relations dan asisten profesor di Edmund A. Walsh School of Foreign Service di Georgetown University.
Colin P. Clarke adalah direktur kebijakan dan penelitian di Soufan Group dan peneliti senior di Soufan Center.