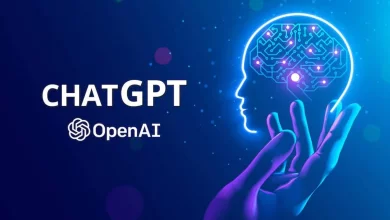Dunia kerja, sayangnya, masih terlalu terobsesi pada kompetensi: penguasaan software, sertifikasi, portofolio teknis. Kita dibentuk untuk menjawab pertanyaan “Apa yang bisa kamu lakukan?” Namun, di tengah revolusi digital yang mengguncang fondasi dunia kerja, kompetensi teknis semakin murah, dan semakin cepat usang.
Oleh : Priatna Agus Setiawan
JERNIH– Di dunia yang berlari lebih cepat dari detak jantung kita, satu pertanyaan menggema lebih keras dari sebelumnya: apa yang membuat manusia tetap relevan?
Kita hidup di era yang ditandai oleh loncatan besar teknologi. Kecerdasan buatan (AI) bukan lagi konsep masa depan, tapi realitas yang mengisi ruang kerja, ruang belajar, bahkan ruang ibadah kita. Mesin kini bisa menulis, mendiagnosis penyakit, menggambar, hingga membuat keputusan bisnis. Maka pertanyaannya menjadi makin tajam: apa yang membuat manusia tetap dibutuhkan?
Jawaban sederhananya—dan sekaligus paling kompleks—adalah: kapasitas sebagai manusia.
Kompetensi Penting, Tapi Tak Cukup
Dunia kerja, sayangnya, masih terlalu terobsesi pada kompetensi: penguasaan software, sertifikasi, portofolio teknis. Kita dibentuk untuk menjawab pertanyaan “Apa yang bisa kamu lakukan?” Namun, di tengah revolusi digital yang mengguncang fondasi dunia kerja, kompetensi teknis semakin murah, dan semakin cepat usang.
Hari ini Anda menguasai Python, besok AI sudah menulis kode lebih cepat. Hari ini Anda jago riset pasar, minggu depan ChatGPT bisa melakukannya dalam 10 detik. Kompetensi adalah tiket masuk, bukan jaminan bertahan.
Apa yang lebih penting? Kapasitas. Bukan sekadar “bisa,” tapi “siap.” Bukan cuma pintar, tapi tangguh. Bukan hanya tahu, tapi terus-menerus tumbuh.
Apa yang dimaksud dengan kapasitas? Ia bukan sekadar IQ tinggi atau nilai akademik. Ia adalah kemampuan menyikapi tekanan tanpa meledak. Kecekatan mengambil keputusan di saat krisis. Kemampuan memahami orang lain tanpa merendahkan diri sendiri. Ia adalah keberanian untuk berkata “saya tidak tahu” dan keteguhan untuk belajar dari nol lagi.
Dalam bahasa warung kopi, kapasitas adalah saat seseorang dibilang “napasnya panjang,” atau “bisa diajak mikir bareng.” Ia bukan orang yang banyak bicara, tapi orang yang bisa menyimak. Bukan yang hanya tampil saat rapat, tapi yang tetap bekerja saat semua bubar.
Dan yang terpenting: kapasitas tidak bisa diwariskan. Ia tidak bisa dibeli. Ia hanya bisa dibangun—dari luka, dari kegagalan, dari refleksi. Ia hanya bisa diperoleh oleh mereka yang mau menempuh jalan sunyi untuk bertumbuh.
Manusia Unggul di Era AI: Manusia yang Manusiawi
Di era algoritma, jangan berharap bisa menyaingi kecepatan mesin. Jangan pula mencoba meniru presisi mereka. Itu perang yang tidak bisa dimenangkan manusia. Tapi, jangan salah: ini bukan akhir manusia. Justru ini seleksi alam untuk manusia unggul.
Manusia unggul bukan yang “melek digital,” tapi yang “melek diri.” Mereka yang bisa:
-Mengelola emosi ketika data tak memberi jawaban,
-Mengambil keputusan dengan nilai, bukan sekadar angka,
-Berkolaborasi tanpa kehilangan jati diri,
-Belajar tanpa diperintah, dan tumbuh tanpa dipaksa.
AI bisa memproses ratusan jurnal dalam hitungan detik. Tapi ia tak bisa mencintai, tak bisa menyesal, tak bisa berdoa. Ia tidak mengenal empati, tidak tahu rasanya gagal dan bangkit dengan air mata.
Hanya manusia yang bisa merasakan makna.
Pertanyaannya sekarang bukan “Apa pekerjaan masa depan?” tapi “Siapa manusia masa depan?”
Apakah Anda hanya mengandalkan kompetensi teknis—yang akan segera diambil alih oleh mesin? Atau Anda membentuk kapasitas batin: untuk berpikir, bertahan, dan berubah?
Jangan salah paham: ini bukan retorika motivasi murahan. Ini soal keberlanjutan eksistensi Anda di dunia yang tak peduli pada ijazah Anda. Karena ujungnya bukan siapa yang paling tahu, tapi siapa yang paling siap belajar ulang. Bukan siapa yang paling banyak koneksi, tapi siapa yang paling kuat koneksi batinnya dengan diri sendiri.
Dan berita baiknya: kapasitas bisa dibentuk. Ia bukan takdir, ia adalah pilihan. Ia bukan warisan, ia adalah hasil kerja keras.
Di era AI, manusia tidak akan punah. Tapi manusia yang malas bertumbuh, akan tersingkir. Dunia tidak lagi memberi ruang bagi mereka yang hanya bisa mengeluh di kafe sambil menggenggam ponsel canggih.
Sebagaimana dikatakan Viktor Frankl, psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi: “Antara stimulus dan respons, ada ruang. Dalam ruang itu terletak kebebasan kita untuk memilih respons. Dan dalam respons kita terletak pertumbuhan dan kebebasan kita.”
AI akan memberi kita stimulus. Tapi hanya manusia sejati yang bisa memilih respons yang bermartabat. Dan dari sanalah kapasitas tumbuh. Maka jadilah manusia unggul bukan karena dunia menuntutnya. Tapi karena dunia akan berubah—dan hanya manusia dengan kapasitas yang akan tetap berdiri. []