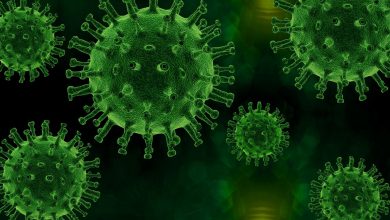5 PUISI DAHTA GAUTAMA

HUTAN DIPINGGIR KAMPUNG
Dulu, ada banyu yang terbit dari celah batu,
bergerak ke arah kampung.
Ngalir mengikuti siring besar berbentuk ular.
Orang-orang kampung mandi dan
menjala disana.
Alam melimpah. Kaya raya dan cerah.
Kini hutan dipinggir kampung, tinggal cerita.
Uang menebangnya,
dibangun perumahan manusia,
penginapan dan lapangan futsal.
Kampung tanpa pohon,
menjelma sebagai kota yang rapuh.
Tanpa pertahanan apa-apa,
jika hujan, tenggelam
sampai dada orang tua.
Hutan dipinggir kampung,
dulu mata anak-anak
menangkap hijau dan burung-burung.
Kilau embun
bergerak dari bawah daun.
Kini, anak-anak main futsal,
dan berenang ditengah jalan saat hujan.
Taman Gunter, 6 Maret 2025
*
CATATAN REDAKSIONAL
Dari Hutan ke Lapangan Futsal: Puisi yang Menegur Kita dengan Santun dan Tajam
Oleh Irzi Risfandi
Mari kita ucapkan selamat datang kembali kepada Dahta Gautama, penyair yang tidak hanya tahu cara menulis puisi, tapi juga tahu bagaimana caranya menyelipkan tamparan realitas ke dalam setiap larik tanpa kehilangan keelokan diksi. Puisi “Hutan di Pinggir Kampung” ini bukan sekadar sajak nostalgia; ini adalah surat protes yang dilayangkan dengan amplop embun pagi dan prangko kenangan masa kecil. Gaya Dahta yang tenang, tapi menghunjam, membuat puisi ini terasa seperti obrolan di beranda, tetapi setelah selesai membacanya kita ingin menyurati dinas tata kota dengan huruf kapital dan tanda seru ganda.
Larik pembuka sajak ini adalah sejenis portal magis ke masa lalu: “Dulu, ada banyu yang terbit dari celah batu…” – dan boom! kita langsung diseret ke dunia pra-pemukiman, pra-lapangan futsal, ketika banyu (air) bukan sekadar debit kubik, tapi sesuatu yang “bergerak ke arah kampung” seperti utusan alam yang penuh berkah. Tipografi sederhana dipilih Dahta, seolah ingin memantulkan keheningan hutan yang telah tiada itu. Ia bukan sekadar menggambarkan kehancuran ekologis, tetapi juga kehancuran imajinasi, meminjam istilah dari teori ekokritik. Kampung tanpa pohon menjadi kota rapuh—tidak hanya secara fisik, tapi juga secara identitas.
Puisi ini mengandung ekosentrisme halus: bukan manusia yang jadi pusat, tapi keseimbangan itu sendiri. Kita menyaksikan anak-anak yang dulu menangkap “kilau embun” kini justru bermain futsal dan “berenang di tengah jalan saat hujan”—sebuah ironi urban yang terasa begitu Jakarta, begitu Medan, begitu Indonesia. Bayangkan saja: hujan deras, jalanan tergenang, dan anak-anak yang tidak sadar sedang mewarisi dunia yang rusak. Dahta tidak menyalahkan mereka. Ia menyalahkan kita semua yang membiarkan hutan berubah menjadi penginapan dan lapangan futsal tanpa jeda untuk berpikir.
Secara bentuk, puisi ini menggunakan baris pendek, hampir prosaik, tanpa tanda baca, namun justru di situ kekuatannya: seperti hutan yang tak berpagar, setiap larik terbuka untuk ditafsir. Metafora “siring besar berbentuk ular” bukan hanya visual yang indah, tetapi juga menyiratkan keseimbangan dan kelicinan—simbol dari aliran air yang dahulu menghidupi, kini digantikan dengan properti yang membanjiri. Ini bukan hanya kritik lingkungan, tetapi juga satir terhadap kapitalisme pinggiran yang datang tanpa rencana, hanya insting menjual.
Dahta Gautama, yang kini seorang advokat, tidak kehilangan daya kritik sastranya. Ia pernah menjadi reporter, redaktur, direktur LSM, dan kini sedang menempuh program doktoral hukum—semuanya terasa seperti latar superhero yang diam-diam adalah penyair paling konsisten di sudut selatan Sumatra. Jika kita ingin tahu bagaimana puisi dapat menjadi pengacara bagi pohon dan sungai, “Hutan di Pinggir Kampung” adalah salah satu dokumen terbaiknya. Di tengah keriuhan puisi-puisi romantik yang tak selesai pada rindu, Dahta datang membawa pesan yang tak bisa lagi kita tunda: mari berhenti menukar hutan dengan parkiran. Dan hei, kalau Anda pernah berenang di jalan karena banjir, mungkin sudah saatnya membaca puisi ini di toa mushala atau di papan pengumuman RT. Anggap saja itu semacam deklarasi penyair buat revolusi kecil di pinggir kampung.
2025
*
BUNGUR TUA ITU TUMBANG
Ia pernah tegak dipinggir kali.
Pemancing suka benar meletakkan bahu
di batangnya.
Kalau musim kembang,
ia menerbitkan kemilau ungu.
Kemudian gugur dibawa arus.
Pada malam penuh hujan,
angin ribut keliling disekitar tubuhnya.
Akar-akarnya yang menjalar ke kali,
bikin tubuhnya goyang.
Bersamaan dengan kilat petir, ia tumbang.
Kali yang meluap menggeser letak tubuhnya.
Pelan-pelan ia hanyut.
Dahan-dahannya pecah dan patah.
Daun-daunnya rontok oleh benturan
lumpur. Akar yang cabut, membelah tanah.
Bungur tua itu, terhempas.
Kokohnya tuntas.
Riwayatnya tak pernah dicatat,
bahkan para pemancing
yang datang esok,
tak membicarakan apa-apa tentangnya.
Ia hanya pohon.
Taman Gunter, 6 Maret 2025
*
GAHARU
urat kayunya mengular ke arah
delapan penjuru mata angin.
coklat kehitam-hitaman,
menerbitkan wibawa dan pesona.
Wanginya manis,
aroma rantingnya cengkih.
Akar yang meranggas,
pada setiap serabutnya
menyentuh genang embun dikulit tanah.
Ajaib sebagai pohon surga.
Taman Gunter, 6 Maret 2025
*
INDONESIA HARI INI
Jaman ciptakan pemikiran-pemikiran.
produk dari pemikiran adalah industri.
Setiap waktu, jam yang bergerak,
serupa angin buritan,
mutar diselasar gedung dan taman kota.
Apa yang kita pikirkan tentang hidup hari ini,
adalah bentuk lain dari gaduh di kepala.
Dimana, pemikiran-pemikiran muara keinginan-keinginan.
Maka, orang-orang kota kehilangan penglihatan.
Mata mereka mencelat ke pemukiman-pemukiman banjir. Hanyut, nyangkut didapur perumahan subsidi.
Orang-orang desa,
telah menjadi petani tekun sejak lalu.
Tapi industri negara luar merusak panen mereka.
Orang desa nestapa, petani nelangsa.
Ini jaman, dimana tak ada tempat yang sah untuk merdeka.
Taman Gunter, 6 Maret 2025
Dahta Gautama
DUNIA KITA
Sejauh apa kita berjalan,
sebenarnya kita tak pernah sampai.
Kita hanya sedang berjalan,
tapi tidak sedang bergerak.
Orang-orang di negeri ini,
sebenar-benarnya paham.
bahwa dunia mereka cuma lingkar pendek.
Sejak bangun subuh, hingga lelap di ranjang pada dini hari, isi kepala cuma angan-angan.
Negara memberi kita merdeka untuk bicara.
Tapi merusak pita suara kita,
ketika kita mulai pintar.
Negara membuka lowongan kerja,
tapi tidak membuka universitas akal.
Itu sebabnya, kita hanya pegawai,
tak pernah sampai sebagai
manusia dengan julukan tuan.
Kalau sudah begini,
dengan cara apa kita
sanggup memiliki kemewahan.
Bukan pura-pura,
bukan pajangan untuk dipamerkan
kepada tamu negara.
Taman Gunter, 6 Maret 2025
BIODATA PENYAIR:
DAHTA GAUTAMA. Lahir di Hajimena, Bandar Lampung 24 Oktober 1974. Menekuni sastra sejak tahun 1990. Puisi-puisinya, dimuat disejumlah koran lokal dan nasional, antaranya: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika, Merdeka, Jawa Pos, Lampung Post, Sumatera Post, Trans Sumatera, Lampung Ekspres, dll. Buku puisi tunggalnya, Menjadi Camar (2002), Metamorfosis Mimpi (2005), Silsilah Keluarga Kutukan (2010), Ular Kuning (2011) dan Manusia Lain (2013).
Kini berprofesi sebagai advokat di Firma Hukum DG&Partners, pernah menjabat Pemimpin Redaksi Dinamika News (2005 – 2012), Direktur NGO Badan Logistik Informasi|BLI (2006 – 2012), Redaktur Pelaksana Majalah Demokratis (2002 – 2006), Reporter Antv (1996 – 1998), Ketua Komunitas Sastra Mata Angin (1995 – 1997). Saat ini sedang menempuh Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Borobudur.