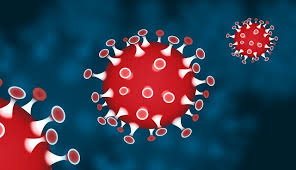Sementara tanpa diajari agama, orang-orang itu dengan gampang ditipu para penipu yang tak segan berkedok agama. Dan kesucian Mekkah sama sekali tak membuat gerombolan para penipu itu segan untuk mengelabui dan mencelakai saudaranya sesama Muslim.
Pengantar :
Indonesia pernah dikaruniai seorang ulama, yang tak hanya kharismatik, melainkan pula memiliki kedalaman dan luasnya ilmu. Namun bukan itu yang paling menonjol, melainkan karakternya yangtegas dan kukuh membela kebenaran yang ia yakini. Ulama itu bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA).—
Episode 16
Bab 10
Orang Alim dari Tanah Jawi
Tahun-tahun Malik menginjakkan kaki di Mekkah adalah tahun-tahun saat api semangat kebangkitan Islam tengah berkobar di dunia Muslim. Begitu juga api Pan Islamisme yang awalnya diangkat dan ditegakkan ulama besar dunia Sayid Jamaluddin Al-Afghani.
Mayoritas Muslim bergembira manakala Kemal Pasya sukses mendongkel kekhalifahan Turki Utsmani yang kian korup. Meski sebentar kemudian dunia Muslim pun terpecah mencermati Mustafa Kemal yang justru melakukan sekularisasi ekstrem sebagai jalan menuju ‘kemajuan’. Bagaimana tak bisa disebut ekstrem bila Mustafa Kemal bukan saja mengenalkan huruf Latin pada masyarakat Turki, tetapi juga mengganti huruf Arab yang selama ribuan tahun dipakai masyarakat Turki.
Bahkan hal yang tidak esensial pun dilakukannya. Kemal melarang masyarakat Turki menggunakan penutup kepala khas budaya Turki, tarbus, apalagi serban. Untuk memastikan perintah itu dipatuhi, Kemal tak segan menurunkan polisi untuk itu.
Kemal dalam waktu tak terlalu lama pun segera mencontoh rezim yang digulingkannya, menjadi korup dan otoriter. Yang membedakan kemudian semata label: dulu kekhalifahan yang dicitrakan kolot, kini republik yang dianggap modern.
Apalagi kemudian sukses di Turki itu diikuti keberhasilan perjuangan Emir Abdul Karim di Maroko, gerakan Sultan Athrasy di Syam (Suriah) atau yang langsung dirasakan Malik saat itu: kemenangan Ibnu Saud di tanah Arab. Di tanahnya sendiri, Hindia Belanda, kala itu segera berdiri Muktamar Alam Islam (MAI) cabang Hindia Belanda.
Warga Hindia Belanda yang berada di tanah Arab pun terbakar semangat untuk bergerak tersebut. Beberapa di antara mereka sering mengadakan pertemuan di Masjidil Haram, di saat-saat setelah shalat dilakukan. Malik cukup punya andil untuk mengatur pertemuan, menghubungi para peserta pertemuan dan sebagainya. Tugas itu membuatnya dengan cepat mengenal seluk beluk jalanan di Mekkah, tempat-tempat tinggal orang-orang Hindia Belanda yang terlibat pergerakan dan para aktivis.
Dalam pertemuan pertama saja segera mengemuka kekesalan para pimpinan warga Hindia Belanda di Arab, terutama pembodohan yang dilakukan para syekh pemberi tumpangan.
Dengan berbagai pengalaman yang dialaminya sendiri, Malik segera sadar betapa dekadennya watak para syekh itu. Sebenarnya terasa sudah, tak ada lagi niat untuk membantu para peziarah karena apa yang mengemuka tak lain hanya urusan uang untuk kepentingan diri mereka sendiri, para syekh itu. Omong kosong dengan berbagai dalih membantu para jamaah, tamu Allah!
Pada pertemuan kedua mengerucut kesimpulan perlunya memberikan pelajaran agama kepada pada jemaah haji atau umrah dari Hindia Belanda, sebagai bekal mereka untuk tak lagi mudah dibodohi, di tanah Arab terutama.
Barulah setelah sekian pertemuan, mereka sepakat mendirikan lembaga tempat berkiprah bersama, yakni Persatuan Hindia Timur. Nama itu diambil karena saat itu Serikat Islam dan Muhammadiyah pun masih memakai kata ‘Hindia Timur’ tersebut.
Pembentukan organisasi itu bukan tanpa gangguan. Ternyata kelompok SI Merah yang komunis sudah pula menginfiltrasi para jemaah haji. Kelompok ini kemudian mengganggu gerak laju organisasi baru tersebut dengan mempromosikan pemahaman komunis yang berbalut Islam. Seorang diantaranya bernama Mandar, seorang kader komunis dari Garut, Jawa Barat. Untung saja penciuman hidung polisi rahasia Ibnu Saud pun amat tajam.
Dengan bekerja sama melalui Vice Konsol Belanda di Mekkah, orang-orang komunis itu ditangkapi, lalu segera dikirim pulang via kapal pertama kembali ke Hindia Belanda. Mereka pulang sebelum selangkah pun mengerjakan ritual haji. Jika memang niat mereka berhaji, tentu saja itu merupakan kerugian yang sangat besar.
Ada pula organisasi Majelis Syura, yang didirikan Jalan Taib dan Muchtar Luthfie. Namun seringkali anggota kelompok-kelompok itu bergabung akrab satu sama lain di Masjid Haram, atau tempat-tempat berkumpul lainnya yang mereka sepakati, tanpa mempedulikan bendera organisasi masing-masing.
Anak-anak muda yang tergabung dalam kedua pergerakan tersebut boleh dibilang ‘gilagila’. Berbekal kabar betapa demokratisnya kehidupan Ibnu Saud dan anak-anaknya, terutama Pangeran Faisal yang menjabat Noibel ‘Am atau wakil tinggi mahkota untuk Hijaz, dengan bersemangat anak-anak muda itu menyusun delegasi untuk menghadap Pangeran Faisal.
Malik terpilih menjadi ketua delegasi. Dengan pakaian miliknya yang bahkan masih lebih buruk untuk dibilang sederhana, baju tutup drill hijau yang karena mahalnya air jadi jarang dicuci, bersarung pelekat usang, dia dengan yakinnya menjadi ketua delegasi, menghadap Pangeran Faisal. Malik diiringkan empat orang temannya yang berpakaian lebih baik dan gagah dibanding dirinya. Hanya saja, mereka berempat tak sefasih dirinya berbahasa Arab.
Saat itu Malik teringat kawan-kawannya sesama pemuda kala masih di Minang, yang selalu mengejeknya tak pandai Nahwu. “Ke sini kalian sekarang,” pikir Malik dengan dada penuh bangga. “Bertanding dengan awak soal bahasa Arab. Gumulilah nahwumu sepanjang waktu, toh awak juga yang duluan menghadap Pangeran Arab.”
Malik, si rakyat negeri jajahan yang di negerinya menghadap pejabat setingkat regent pun tak pernah, kini langsung menghadap seorang putera mahkota. Apalagi jabatan regent Padang pun dihilangkan sejak 1910, hanya dua tahun setelah kelahiran Malik. Posisi itu kemudian benar-benar jabatan yang diberikan kepada penjilat Kolonial Belanda. Lihat saja, bagaimanapun prestasi kepemimpinan dan cara mereka menjabat, dua pejabat regent Padang terakhir berada di kursi jabatan sampai mereka hampir mati ketuaan, masing-masing menjabat selama 34 tahun!
Disangka oleh Malik dan teman-teman itu mudah saja menemui Pangeran Faisal, sebagaimana kabar yang beredar tentang betapa demokratisnya mereka. Selama di Padang Panjang pun tak terhitung banyaknya artikel koran terbitan Jawa yang menuliskan betapa ramah tamahnya Ibnu Saud dan putra-putranya. Betapa demokratisnya mereka memperlakukan rakyat, berbeda dengan penguasa yang mereka gulingkan.
Nyatanya? Hampir saja anak-anak muda itu mundur dengan berlapis-lapisnya birokrasi yang harus mereka lalui. Untungnya, anak-anak muda itu memang ‘gila’ sejak awal. Tak masalah berapa banyak pintu harus mereka masuki dan pejabat antara yang harus ditemui, mereka pantang surut. Setelah mereka lalui sekian banyak ‘pagar’ itu, kini Amir Faisal akan menerima mereka di Balai Hamidiyah, bekas pusat pemerintahan Kekhalifahan Turki Utsmani saat menguasai Mekkah.
Pengawal kemudian memberi tahu bahwa mereka diizinkan masuk. Amir Faisal sudah berkenan menerima mereka. Darah para anak muda itu berdesir, dan tentu saja jantung ketua delegasi berdentam lebih cepat lagi. Kelima anak muda itu mengikuti seorang pengawal, di belakang mereka sekitar tiga pengawal mengiringkan mereka masuk.
Saat pintu besar ruangan itu dibuka, sontak Malik nyaris pingsan karena terkejut. Bukan apa-apa, majelis yang hadir di ruangan besar itu begitu hebatnya. Amir Faisal berdiri dari kursinya, demikian pula para pemuka ulama dan para pejabat tinggi Kerajaan Arab. Mereka berdiri menyambut tamu agung: lima orang ‘pemuka’ Islam dari Hindia Belanda!
Hampir saja Malik tak mampu berbuat apapun karena gugup. Apalagi saat Amir Faisal berjalan dari kursinya menyambut mereka, menggamit Malik dan mendudukkannya di sampingnya. Mulut Malik terkunci, lidahnya kelu mengalami pengalaman dahsyat itu.
Segala yang sudah ia persiapkan di benaknya, seketika hilang. Otaknya kosong. Dilihatnya Amir Faisal ternyata masih sangat muda, paling tinggi usianya Malik taksir 20 tahun.
Hanya terpaut satu tahun di atas dirinya.
Namun yang jelas, pandangan matanya yang dalam mencerminkan ketenangan hatinya. Kulitnya kuning langsat, janggutnya pun belum banyak tumbuh. Ia tampak sangat menyadari kegugupan anak-anak negeri jajahan bangsa Eropa itu saat menghadap raja negara berdaulat seperti dirinya. Belum lagi di sekeliling mereka kini duduk para alim ulama, pejabat penting yang duduk diam dengan begitu takzim.
Amir Faisal tak hendak membuat suasana mati. Ia mendahului menegur. Memang demikian lazimnya seorang tuan rumah.
“Kaifa halukum? Apa kabar?” senyumnya menenangkan dan tampak akrab.
“Bi khair, ya Sahibus Sa’adah.”
Entahlah, Malik sudah tak mau lagi berpikir, meski kesal kepada dirinya sendiri. Mengapa yang keluar dari mulutnya justru ‘sa’adah’ alias kebahagiaan? Mestinya yang paling mungkin ya ‘sahibul uzhmah’.
Namun karena Malik tak terus berkutat dalam kecewa karena salah, setelah Amir Faisal menanyakan maksud kedatangan mereka, Malik mulai tenang dan lancar. Ketua delegasi sudah mulai kedatangan rasa percaya dirinya lagi.
Malik menjawab, maksud kedatangan mereka ialah mengucapkan selamat dan rasa bahagia atas Kerajaan Saudi yang telah menjamin keamanan Tanah Hijaz, sehingga jamaah Hindia Belanda naik sebegitu besar. Lainnya mohon izin untuk mengajarkan ajaran agama Islam dan tata cara manasik haji bagi bangsa Hindia di Masjid Haram.
“Siapa yang akan mengajar nanti?” tanya Amir Faisal.
“Saya sendiri di antaranya,” kata Malik.
Sementara mereka berbincang, kahwa diedarkan para pelayan. Kahwa atau kopi Arab adalah kopi yang dicampur gardamunggu atau kapulaga. Tak ada rokok diedarkan, tak ada pula yang tampak merokok.
Setelah menyilakan para tamunya menikmati kahwa dan ia pun menyesap sejenak, Amir Faisal menjawab.
“Saya tentu saja senang sekali Tuan-tuan para pemuka agama dari Hindia Belanda berkenan datang ke mari dan bersilaturahmi. Tetapi untuk urusan mengajar agama di Masjid Haram lebih baik Tuan-tuan bicarakan dengan Imam Besar Masjidil Haram, Tuan Syekh Abu Samah. Urusan itu ada pada tangan beliau,” katanya.
Amir Faisal lalu tersenyum. Ajudan yang berdiri di dekat pintu memberi isyarat. Para pemuka agama dan pejabat tampaknya maklum, lalu berdiri. Amir pun kemudian berdiri dan memberikan tangan untuk bersalaman. Pintu besar kembali dibuka, dan ‘ketua delegasi’ pun keluar diikuti keempat temannya. Selama tadi pintu dibuka, mereka masuk, pintu ditutup, lalu dibuka kembali yang memungkinkan mereka keluar, tak ada dari mereka yang sempat duduk!
Malam itu juga ‘delegasi Hindia’ itu datang menghadap Syekh Abu Samah. Malik menerangkan maksud kedatangan mereka seraya menyatakan bahwa siangnya mereka telah menghadap Amir Faisal.
“Memang,” kata syekh bertubuh gemuk dengan suara lantang yang indah itu. Saat menjawab ia begitu sopan dan lemah lembut. “Urusan itu bukan lagi urusan Amir. Beliau telah menguasakan kepada saya.”
Tampaknya Syekh Abu Samah tergolong manusia yang tak pernah mengedepankan rasa curiga. Tak perlu lama, ia memberikan izin. Juga izin tertulis. Menurutnya agar mereka lebih nyaman mengajar. Syekh mengakui, dirinya memang melihat banyak jemaah awam dari Hindia yang kerap melakukan bid’ah. Mereka mengaku bermazhab Syafii, sementara dalam mazhab Syafii sendiri tak pernah ada amalan seperti itu. Hanya saja Syekh mengingatkan agar mereka tak menyentuh persoalan politik.
Malam berikutnya, usai shalat maghrib Malik sudah berdiri berpidato mengurai berbagai masalah agama. Ia memilih melakukannya di Bab Zuraibah di belakang makam Hanafi. Ia tak sendiri, berdua dengan kawannya, Abdul Jalil Mukaddasi. Berkumandanglah suaranya di masjid yang suci itu. Di depannya kini berkumpul beratus-ratus orang senegerinya yang datang dari berbagai pelosok Nusantara. Saat itu, seolah disengaja, melintaslah Syekh Abu Samah ke kerumunan itu. Begitu melihat Malik ia mengangguk kepala sambal tersenyum. Malik membalas anggukan dan senyuman yang segera membuat hatinya membesar itu.
Mulailah Malik berpidato, mengupas masalah-masakah agama yang sering ditemui dalam keseharian. Ia begitu antusias menerangkan. Dikutipnya ayat Alquran dan hadits.
Dicarinya metafora dan perbandingan, juga contoh yang memudahkan. Orang-orang senang mendengarkan pidatonya yang bersemangat. Nasihat-nasihatnya mendapatkan banyak perhatian. Kian malam, setelah bubar sebentar untuk melaksanakan shalat isya, tak juga orang-orang yang mengerumuninya bubar.
Selama berpidato itu beberapa jemaah datang mendekat dan memberi Malik sedekah.
Mereka menghampiri, menggenggamkan rupiah atau ringgit ke dalam tangannya, bahkan manakala ia tengah berbicara. Sedekah itu sedikit banyak membantu Malik menghadapi hari-harinya.
Sayang, belum juga sepekan berjalan, suatu pagi Syekh Amin Idris memintanya datang ke ruang tamunya. Ekspresinya wajahnya saat Malik datang terlihat bagai bagal susah buang air.
“Malik, ada laporan soal kegiatanmu beberapa hari ini di Masjidil Haram. Hentikan, jangan lagi kau lakukan. Saya tak suka karena itu merusak nama saya di hadapan syekh-syekh yang lain,” kata Amin Idris. Ia langsung ke sasaran, tak lagi bicara berputar-putar.
Malik kaget, tapi cara Amin Idris berkata-kata langsung, justru membuatnya tak lagi punya beban untuk bersopan-sopan.
“Saya berdakwah, Syekh, membantu para jemaah haji negeri saya yang pengetahuan agamanya kurang. Lain tidak!” kata Malik. “Hal apa yang membuat nama baik syekh saya rusak?”
Sejak awal datang pun dirinya memang tak menyukai syekhnya itu. Ia juga sadar, Syekh Amin Idris pun tahu ketidaksukaannya itu. Bukan sekali dua Malik tak mematuhi aturan di pemondokan itu yang beberapa di antaranya menurutnya tak masuk akal.
“Mengajar di masjid, apalagi di Masjidil Haram itu tak boleh dilakukan sembarang orang. Hanya ulama-ulama besar yang bisa. Kamu memang siapa?”
Mungkin Malik sudah banyak belajar, di Jawa maupun di tanah Mekkah. Pengalaman itu tentu saja membawa kedewasaan padanya. Namun masih saja ia anak muda yang bisa segera keluar temperamen aslinya kalau amarahnya terpicu. Mempertanyakan dirinya, adalah sumbu yang mudah tersulut.
“Malik! Aku Abdul Malik, sebagaimana kukatakan di hari pertama kita bertemu,” kata Malik, suaranya tinggi. Suara Malik yang setengah berteriak itu tak urung membuat Syekh Amin terkejut. Jelas, sang syekh juga tak ingin persoalan jadi ramai dan urusan ini menjadi tontonan orang-orang sebangsa Malik. Ia terkesiap dan diam sejenak. Namun tak lama.
“Bukan itu maksudku. Tapi siapa yang mengakuimu sebagai ulama yang boleh mengajar di sana?”
“Saya tak pernah diakui, tak pernah pula minta diakui sebagai ulama. Tetapi kalau soal saya mengajar agama di Masjid Haram, saya punya izin. Ini!”
Malik dengan agak gusar membuka tas kain yang selalu dibawa-bawanya. Dikeluarkannya surat yang diberikan Syekh Abu Samah. Ia bentang surat itu di depan Amin Idris. Saat Amin Idris mau mengambilnya, Malik menarik tangannya, melipat surat itu dan memasukkannya kembali ke dalam tas.
“Anda akan punya persoalan besar kalau mencoba merobek surat saya,” kata Malik. Ia kemudian keluar ruangan, menuju kamarnya untuk beres-beres. Dia tahu, dirinya tak bisa lagi tinggal di pondokan ini.
“Hai, kembali kau Malik! Kita belum selesai!” kata Amin Idris. Ia pun bangkit dari kursi yang sejak tadi didudukinya. Tapi selangkah pun Malik tak terlihat surut.
“Mulai malam ini, kau tak boleh lagi mengajar di Masjid Haram,” teriak Amin Idris. “Masih banyak ulama besar, kau tak harus belagak hebat!”
Teriakan itu sama sekali tak digubris Malik. Bukan anak muda itu sombong. Namun tak ada alasan masuk akal dari syekhnya itu untuk melarangnya mengajarkan ilmu agama. Di tempat istimewa lagi, Masjidil Haram. Untuk mengajar di tempat itu Malik bersedia menggelandang selama dirinya tak punya bekal.
Sementara tanpa diajari agama, orang-orang itu dengan gampang ditipu para penipu yang tak segan berkedok agama. Dan kesucian Mekkah sama sekali tak membuat gerombolan para penipu itu segan untuk mengelabui dan mencelakai saudaranya sesama Muslim.
Padahal mereka juga tahu, saudara-saudara Muslim peziarah itu datang dari seluruh pelosok dunia. Tak kurang-kurang dari mereka yang hanya berbekal dana seadanya setelah memiliki karcis perjalanan dengan kapal.
“Tugasmu hanya menyediakan unta, ya Syekh. Yang menentukan siapa yang boleh mengajar di Masjidil Haram itu Syekh Abu Samah, imam besar Masjid Haram,” teriak Malik tanpa menoleh. Kalimat yang kasar sekali. Ia sudah nekat, tak bisa lagi dirinya bersabar menghadapi orang seperti Amin Idris.
Sejak itu kehidupan Malik boleh dikata semi nomaden. Nomaden karena ia benar-benar tuna wisma, tak punya tempat berteduh. Disebut semi karena ia hanya berputar-putar sekeliling Masjidil Haram, berapa pun jauhnya jarak ia menumpang sementara itu dari pintu-pintu masjid, yang setiap malam ia datangi untuk mengajar ilmu agama kepada peziarah dari tanah Hindia itu.
Untunglah ia pandai membawa diri dan supel bergaul. Itu yang membuat Malik tak mati kelaparan di tanah orang. Banyak orang yang menolongnya kalau hanya sekadar berbagi makan.
Sekian bulan ia merasakan kepahitan akibat kemiskinan yang membelenggunya. Rajab, Sya’ban, lalu berganti Ramadhan. Tetapi semua ia lalui dengan besar hati. Ia pikir, kalua toh saat mengajar ia pingsan kelaparan, mana mungkin orang-orang tak memberinya makan.
Semua yang terjadi disadarinya sebagai buah dari tekadnya pergi ke luar dari ranah Minang, tanahnya sendiri yang menjanjikan kalau sekadar makan. Tapi ia sendiri sering merenung, dan dari renungannya itu ia yakin, kalau hidup hanya sekadar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekadar kerja, kerbau di sawah juga bekerja! Harus ada yang membedakan, karena ingin dipandang sebagai manusia.
Ramadhan pun dijalaninya dengan prihatin. Untuk bertahan ia pergi dari satu teman ke teman lain sekadar menumpang makan. Hari ini menumpang ke temannya sesama orang Padang, hari lain ia tertolong karena temannya asal Lampung. Besoknya temannya dari Jawa menolongnya. Tetapi yang ia suka adalah teman-teman orang Sunda. Mereka umumnya sangat mau berbagi.
Tak berbilang lagi ia sahur hanya dengan roti kering dan air, demikian pula saat berbuka. Biasanya itu kalau ia telat atau tengah tak bisa datang berbuka puasa di masjid Haram.
Ramadhan sebenarnya cukup menolongnya, karena orang-orang banyak yang berbagi makanan saat buka puasa. Tinggal bagaimana caranya membagi makanan yang ia dapat saat berbuka itu sebagian untuk shahur.
Ketika tiba perayaan Idhul Fitri, 1 Syawal, teman-teman Malik kembali mendaulat dirinya untuk mencoba meminta menghadap petinggi Arab Saudi. Ke siapa? Kali ini langsung ke Ibnu Saud sendiri. Kembali, Malik pula yang jadi ‘ketua delegasi’. Sayang, kali ini mereka dipermainkan ajudan dan pelayan raja, seorang budak Habsy. Sempat dipersilakan menunggu di ruang Dewan Almuluk, Balai Kerajaan di Jijad yang sempat menjadi tempat Kongres Dunia Islam. Sempat pula menikmati sirop manis dengan es batu yang melunaskan dahaga tanah Arab keenam anggota delegasi ‘Hindia Belanda’ itu. Namun tunggu punya tunggu, ternyata Baginda Raja berangkat tanpa menemui mereka!
Keberanian Malik dan teman-temannya itu tak urung membawa untung. Mereka akhirnya sempat berkenalan dengan beberapa orang serdadu kerajaan. Para serdadu yang begitu kukuh memegang ajaran Wahabi. Mereka inilah yang beberapa kali membawa Malik ke tangsi untuk ikut makan cara Badawi. Kepada teman-temannya si serdadu teman Malik itu mengenalkan Malik sebagai ‘orang alim dari Tanah Jawi’ yang teguh memegang mazhab Wahabi.
Sempat Malik berkenalan dengan bedil-bedil yang mereka pegang. Malik sempat bertanya, buat apa itu bedil. Mereka akan antusias menjawab,”Buat tembak orang-orang Inggris!”
Di beberapa kesempatan Malik berkali-kali bertanya soal kegunaan bedil-bedil itu. Jawabannya selalu sama,” Buat menembak orang-orang Inggris!”
Dua bulan sebelum pelaksanaan haji teman-teman Malik sebagian besar sudah berangkat ke Madinah. Ia sendiri belum bisa berangkat. ‘Fulusy mafisy’ alias dang hadong hepeng atau tak berduit! Malik sebentar pusing: teman-temannya berangkat ke Madinah untuk berhaji, kemana kini dia akan minta bantuan kalau kepepet?
Saat berjalan tak punya tujuan ke Kampung Quffal, dilihatnya sebuah percetakan yang ternyata dimiliki tuan Hamid Kurdi. Hamid Kurdi adalah putra Majid Kurdi, mertua Syekh Ahmad Chatib Minangkabawi yang terkenal. Masuklah Malik dan meminta pekerjaan.
Kebetulan percetakan saat itu kekurangan orang yang bisa mengerjakan percetakan dalam bahasa Melayu.
Pekerjaan itu benar-benar sebuah pertolongan bagi Malik. Masuk pagi, ia bekerja sampai setelah ashar. Shalat Dhuhur dan Ashar dikerjakannya di tempat kerja. Makan siang dan sore pun ia dapat sebagai hak bekerja di sana. Dua kali makan terjamin sudah! Sarapan juga sebenarnya, karena Malik pun akhirnya tinggal di percetakan itu. Di sana Malik mengenal Zubair, seorang pekerja asal Pulau Penang. Di pekerjaan itu pun ia bekerja sama dengan Ammi Abbas, Abbas kecil dan seorang kepala tukang set yang berasal dari Suriah.
Hampir dua bulan Malik bekerja di percetakan itu. Banyak benar manfaat yang ia dapat. Ia bisa mengenal kehalusan budi dan adat para bangsawan Hijaz. Pagi-pagi usai subuh, Syekh Hamid telah duduk di tengah-tengah majelis. Janggutnya yang memutih panjang mencapai dada, nyaris sewarna dengan bajunya yang hampir selalu berwarna putih. Roti panas dan kacang Arab tersedia, juga kahwa yang akan diedarkan pelayannya. Wajahnya tenang, jernih berseri-seri.
Biasanya akan datang anak-anaknya, Kamil dan Adil, yang satu persatu mencium tangan ayahnya. Biasanya mereka akan saling bertanya soal kesehatan masing-masing, lalu saling mendoakan. Malik senang sekali melihatnya. Benar-benar penuh adab.
Para pekerja kemudian mendapatkan giliran. Satu persatu mendatangi Syekh Hamid, saling berjabat tangan dan mendoakan kesehatan masing-masing. Lalu datanglah yang ditunggu-tunggu Malik dan pekerja lainnya: makan pagi dengan roti, kacang Arab, kismis dan kahwa yang harum lezat. Cara makan siang dan sore pun sama, hanya tanpa ritual saling bersalaman. Biasanya kalau siang atau sore menunya khas: roti keping yang lebar, nasi, kambing guling, kadang kari kambing, minyak samin dan muluchia[1], sekenyang-kenyangnya.
Biasanya sejak pukul dua siang pekerjaan sudah banyak berkurang. Malik pun sudah bisa masuk gudang buku, membaca di sana sepuasnya sekitar satu jam. Hal itu memang diizinkan oleh Syekh Hamid.
Suatu saat masuklah Syekh Hamid ke gudang itu, diam-diam. “Hai, Abdul Malik. Kau di sini?” Tentu saja Malik terkejut. Syekh mendekatinya, meminta buku yang tengah ia baca dan melihatnya dengan seksama. Kebetulan yang sedang dibaca Malik adalah As-Siasat ul-Usbu’iyah, terbitan Mesir. Isinya tentang politik, cukup berat. “Engkau yakin memang bisa membaca buku-buku ini?”
“Sanggup juga sedikit-sedikit ya Syekh,” jawab Malik.
Syekh Hamid mengangguk-angguk. Matanya berbinar-binar. Senang sekali ia ada pegawainya yang membaca buku-buku bermutu.
“Meskipun mungkin hari ini apa yang kau baca belum sepenuhnya kau pahami, teruskan membaca, ya Abdul Malik. Terus dan sungguh-sungguh. Insya Allah kau akan maju,” kata Syek Hamid.
“Saya berharap begitu, Syekh.”
Syekh Hamid bertanya di mana Malik belajar bahasa Arab. Saat Malik menjawab belajar dari ayahnya, Haji Rasul, yang terhitung murid Syekh Ahmad Chatib Al Minangkabawi, Syekh Hamid kontan mengucap nama Allah.
“Subhanallah! Saya kenal baik Haji Rasul. Ya, beliau dulu belajar di sini. Alhamdulillah…” tak hanya sekali Syekh Hamid mengucap syukur.
“Begini, tinggallah terus di sini. Belajar yang tekun, bekerja siang hari. Insya Allah Allah membuka jalan hidupmu.”
Alhasil dari rumah itulah, rumah yang pernah pula disinggahi ayahnya berpuluh tahun lalu saat belajar di Mekkah, Malik mendapatkan banyak kemudahan selama hidup di Mekkah.
Di sana ia bisa bekerja dan mendapatkan gaji. Di sana pula ia bisa membaca sebanyak mungkin bacaan-bacaan bagus yang jarang bisa ditemukannya di seantero Mekkah. Di sana pula ia bisa makan enak dan rutin tiga kali sehari, plus belajar tata krama dan kesopanan khas Padang Pasir.
Ketika waktu haji datang, Syekh Hamid datang kepadanya, bertanya soal niatnya berhaji. Tatkala dikatakan bahwa memang itulah niat awal Malik berangkat ke Tanah Suci, Syekh Hamid lebih jauh bertanya tentang kesiapan dana yang dimilikinya. Ia menambahkan sejumlah uang, lebih dari cukup untuk melakukan ibadah haji. Apalagi Malik sendiri punya gaji yang utuh, hanya dipakai sedikit-sedikit karena makan sehari-hari sudah sangat terjamin.
Saat
dirinya siap berangkat berhaji dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga orang-orang
salih itu, tak terasa air mata Malik mengalir. Dan benar pula ia meminta waktu Syekh
untuk menerimanya hari itu, karena sekembali dari Arafah pun Malik tak sempat lagi
berkunjung kepada syekh yang baik itu, yang tak hanya menyelamatkannya dari kelaparan
di saat ia tak punya akar untuk bergantung. Di sana Malik mendapatkan banyak ilmu
dari apa yang ia baca, mendapatkan tata krama dari apa yang ia lihat
sehari-hari.[bersambung]
[1] Makanan khas Mesir