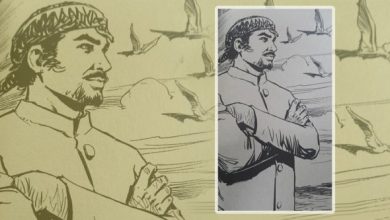UKUR

Ia pun seharusnya malu tak berkabar bahwa pasukannya segera memasuki Jakatra karena memang awalnya dia berharap bisa menaklukan kota itu dengan pasukannya sendiri, akibat bermimpi mendapatkan banjir pujian dan hadiah dari Kanjeng Sultan untuk dirinya sendiri. Kini, setelah semua gagal, barulah ia teringat akan Ukur dan menimpakan seluruh kesalahan kepadanya.
Oleh : Darmawan Sepriyossa
Pengantar:
Setelah jatuhnya Kerajaan Majapahit, ratusan tahun kemudian kerajaan-kerajaan taklukan di seluruh Nusantara bangkit memupuk kekuatan. Yang paling mencorong adalah Kerajaan Mataram, pengklaim pewaris kekuasaan Majapahit. Sementara kekuatan asing yakni Portugis, Belanda dan Inggris, mulai pula datang menancapkan kuku kekuasaan mereka. Masing-masing dengan kerakusan dan kekejamannya sendiri. Pada saat itu, di Tanah Sunda muncul kekuatan yang mencoba menolak penjajahan, dipimpin seorang bernama Dipati Ukur.—
Episode -22
TUMENGGUNG Bahureksa sedang dalam puncak kemarahannya. Ia sama sekali tak menyangka kekuatan Kompeni di balik benteng itu begitu kuatnya. Tak pernah terlintas sedikit pun di kepalanya, betapa mudahnya pasukan berani mati yang ia kepalai dipukul mundur, dicerai-beraikan dan hampir seratusan orang dibuat perlaya saat itu juga.
Andai saja sebelumnya ia tak sesemberono itu. Bagaimana pun, menyerang di terangnya matahari lewat lapangan terbuka untuk mencari-cari musuh yang bersembunyi di rapatnya benteng, memang pekerjaan ceroboh, kalau tak mau dibilang pilon. Itulah yang kemudian ia sesali.
Tetapi bagaimana pun manusia adalah makhluk yang selalu mencari pembenaran atas kesalahan yang ia lakukan. Di tengah kecewanya, selintas pikiran Bahureksa berkata bahwa semua ini tak mungkin terjadi kalau Dipati Ukur dan pasukannya tidak mangkir di Karawang. Mangkirnya Ukur yang tak memungkinkan untuk membuat serangan bersama di hari itu, menjadikan serangan pasukannya jadi begitu mudah dipatahkan.
Lama-lama, pikiran yang cenderung mengkambinghitamkan Ukur yang awalnya hanya serupa tunas itu, dengan sekian banyak laporan terus-menerus para anak buahnya tentang kehilangan nyawa prajurit dan kekalahan memalukan, membuat soal ketidakhadiran Ukur pun tiba-tiba berkembang menjelma menjadi alasan pokok.
“Kurang ajar Si Ukur,” teriak Bahureksa. Pikiran itu kini tidak lagi hanya berputar di kepalanya, melainkan sudah tercetus keluar mulut. Para perwira dan prajuritnya serentak bersiap.
“Coba kalau Si Ukur, pengecut dari nagri Sunda itu bergabung, lalu kita menyerang dari banyak sektor, sore ini kita tak akan jadi pihak pecundang,” kata Bahureksa berteriak. Dadanya kembeng kempis menahan amarah.
“Karena kepengecutan dialah maka sekian banyak teman-teman kita hari ini menjadi layon, tertembus peluru, punting hancur lebur dihajar peluru meriam..”
Lupalah Bahureksa, dirinyalah yang gagal menepati janji untuk bertemu di Karawang, alias gagal pula menyatukan pasukan sejak dari sana. Dia pun tak juga mengutus caraka untuk menegaskan kapan dan di mana mereka akan berkumpul setelah pertemuan Karawang itu gagal. Yang paling jelas, ia pun seharusnya malu tak berkabar bahwa pasukannya segera memasuki Jakatra, karena memang awalnya berharap bisa menaklukan kota itu dengan pasukannya sendiri, akibat bermimpi mendapatkan banjir pujian dan hadiah dari Kanjeng Sultan untuk dirinya sendiri. Kini, setelah semua gagal, barulah ia teringat akan Ukur dan menimpakan seluruh kesalahan kepadanya.
Pandangan mata Bahureksa berkeliling ke seantero penjuru, menatap mata para perwira dan prajurit-prajuritnya. Tentu saja para perwiranya, apalagi prajurit, tak kuasa menatap pandang penuh amarah itu. Mereka tak ingin mencari persoalan, bahkan bisa saja kematian hanya karena dianggap tak loyal pada pimpinan. Apalagi di saat seperti ini, manakala sang pimpinan tengah menderita kekalahan memalukan.
Mereka memilih menunduk, tak bersuara untuk menghindari salah paham. Bagaimana pun Bahureksa adalah bawahan Sinuhun mereka, Kanjeng Sultan Agung. Sikap dan sifat Sultan Agung yang gemar memberikan hukuman keji pada anak buahnya, tentu saja menurun kepada Bahureksa, karena dia sendiri pun punya peluang dihukumi dengan kejam. Ibarat pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, begitulah umumnya yang terjadi dalam kepemimpinan.
“Juru tulis, ke sini!” tereak Bahureksa, setelah jalan hilir mudik dalam tendanya, setengah menunggu ada suara iseng perwiranya. Lumayan buat korban gampar atas rasa kesalnya. Tapi memang tak ada seorang pun perwiranya yang berkomentar. Semua mengkeret ketakutan.
Teriakan Bahureksa itu tak banyak guna, sebenarnya. Juru tulisnya hampir tak pernah jauh darinya, untuk menuliskan apa pun yang menjadi laiknya sabda dari dirinya. Siapa yang mau digampar saat ketahuan tak berada di dekatnya mana kala diperlukan?
“Sendika, Gusti Tumenggung,” kata Juru Tulis, segera ke depan menghampiri Bahurekso.
“Buat dua surat. Pertama untuk Si Ukur. Minta dia segera datang ke mari. Katakan, jangan bawa pengawal. Kalau pun bawa, jangan lebih dari lima. Tak usah kau tuliskan apa keerluannya, kecuali suruh saja dia kemari. Besok pagi aku tunggu di sini pada saat matahari sepenggalah, “kata Bahureksa memerintah.
“Yang kedua untuk Adipati Wiraguna yang memimpin sector selatan. Katakan segera gunakan meriam besar kebanggaan Mataram, Kyai Setomo dan Nyai Setomi. Hajar Benteng Batavia sampai jebol, bagaimana pun caranya. Aku tak mau tahu kecuali besok sore benteng itu sudah kita kuasai.”
“Sendika, Gusti!” kata Juru Tulis, menyembah.
“Jangan lebih dari satu jam mendatang, kedua surat itu sudah harus terkirimkan!”
“Sendika, Gusti!” hanya itu ke itu saja jawaban para abdi mataram. Dan memang sejatinya itu pula yang hanya bisa dikatakan para adipati dan bangsawan semacam Bahureksa kepada Kanjeng Sihunun Sultan Agung.
Esok harinya, sementara pasukannya bergerak menggempur kembali Benteng Batavia, Tumenggung Bahureksa menunggu kedatangan Ukur di tenda komandonya. Sejak pagi dia bahkan sudah mempersiapkan kalimat-kalimat yang akan digunakannya untuk medesak Ukur, menyalahkannya terkait pertemuan di Karawang. Dia akan berkukuh, pasukan Sunda yang menjadi bawahan Mataram seharusnya setia menanti sampai kapan pun pasukan induk datang. Bukannya malah langsung menuju Jakatra dan menyerang sendirian. Ia akan menekan Ukur hingga adipayi Sunda itu mengakui kesalahannya yang menjadi pangkal sebab utama kekalahan Mataram sampai kemarin.
Tapi yang ditunggu tak juga kelihatan batang hidungnya.
“Kurang ajar Si Ukur!” Gigi geligi Bahureksa berkerot-kerot menahan marah. Darahnya sudah pasti naik ke ubun-ubunnya, karena wajahnya pun berubah merah padam. Sebentar Bahureksa seolah sempoyongan kehilangan pegangan. Untunglah dengan cepat ia meraih pegangan kursi dan langsung menjatuhkan pantatnya untuk duduk. Sambil duduk terengah-engah bahureksa menarik nafasnya berkali-kali untuk dihembus-hembuskannya lagi sebagaimana disarankan tabib pribadinya. Ia ingat, tabib bilang dirinya harus menjauhi rasa marah, atau rasa pusing yang menggigit otaknya seperti yang tadi ia rasakan akan terus menyerangnya.
“Kuuu..raaang..aaa..jaaar…” serunya lambat-lambat dalam sebuah dengusan. Ia merasa harus mengeluarkan dulu amarahnya, tapi terkontrol, sebagaimana yang barusan ia lakukan.
Setelah diteguknya air teh dingin dari mug besar yang khusus disajikan untuknya, Bahureksa berdiri. Dimintanya pengawalnya menyiapkan kuda kesayangannya. Ia akan memimpin langsung serangan, menguatkan serangan Adipati Wiraguna yang akan menggempur Benteng Batavia.
Hari itu giliran pasukan Kompeni yang terperanjat. Mereka tak menyangka pasukan Mataram pun bahkan membawa serta gajah-gajah dalam pasukan mereka. Gajah-gajah dari wilayah taklukan Mataram di Palembang, dan memang dipawangi juga oleh orang-orang Palembang. Gajah-gajah itu menarik beberapa Meriam, termasuk Kyai Setomo, Nyai Setomi, Kubarawa, Kadal Buntung dan Segara Wana.
Manakala Si Segara Wana yang disulut sebagai pembuka serangan meriam berdentum, Kapten George, pimpinan pasukan Artileri Kompeni terperanjat. Suara dentumannya sangat ia kenal karena memang lama bergaul dengan benda yang sedang marah itu.
“God verdom, zeg![1] ” teriaknya. Dia kemudian berlari ke ruangan Coen Murjangkung dan melapor.
“Yang Mulia, mereka menembaki kita dengan meriam kita sendiri!”
Coen hanya gelagapan, tanpa memberikan respons apa pun.
“Kalau begitu, yang menyerang dari sektor barat itu pasti pasukan dari Pati. Mataram pernah mengambil-alih Pati yang sempat kita kuasai, dan merampas banyak Meriam. Salah satunya yang barusan berbunyi,” kata Kapten George melanjutkan.
“Walah George. Kowe orang malah cerita-cerita kesenangan, saporti cerita soal kenangan. Balik ke tempatmu, dan serang balik dengan kita orang punya Meriam!” Akhirnya datang juga ketenangan Coen.
Hari itu Mataram menggempur seolah tak akan punya hari lain untuk menyerang. Mereka bisa merobohkan satu sisi benteng di sebelah selatan. Gerowong tertembus peluru besi meriam. Namun benteng itu masih jauh dari roboh. Sementara orang-orang Kompeni yang sadar bahwa leher mereka terancam, juga berperang mati-matian. Bahureksa diam-diam mengagumi keberanian Jacques Lefebre, komandan seluruh pasukan Kompeni. Tanpa jeri ia terus mengomandoi pasukannya bertahan dan sesekali menyerang. Belakangan, justru pasukan Kompeni yang lebih banyak melakukan serangan dengan tembakan-tembakan Meriam. Jarang lagi terdengar dentuman Kyai Setomo, Nyai Setomi dan teman-temannya yang tadi sempat merajai atmosfer peperangan.
Ternyata, orang-orang Kompeni mendapat berita bahwa ledakan-ledakan Meriam Mataram itu lebih banyak menghajar wadya bala mereka sendiri. Kesatuan-kesatuan Mataram seperti Kesatuan Priyataka, Nyutra, Nungsapratanda, Kepedak, Brajanala, Wirabraja, dan sebagainya, lupa bahwa mereka pun punya Meriam. Alhasil, kesatuan-kesatuan itu maju mendekati dinding benteng. Jadi manakala meriam-meriam Mataram meletus, tak jarang yang kena hajar malah pasukan mereka sendiri!
Sebaliknya, berita yang datang ke Mataram hari itu justru buruk. Tak hanya tentang serangan meriam yang menghajar kawan sendiri. Datang pula kabar dari telik sandi bahwa di pelabuhan Jakatra telah merapat dua kapal besar Kompeni dengan persenjataan penuh. Kedua kapal itu adalah kapal ‘Mauritius’ dan ‘Hollandia’, yang baru saja pulang dari perjalanan ke Afrika.
“Ladalah,” dengus Tumenggung Bahureksa kecewa. “Makin kuat saja kini Kompeni sialan itu.”
Dengan datangnya dua kapal itu Bahureksa menghitung, kekuatan Kompeni kini tak kiurang dari empat brigade, dengan senjata bedil panjang dan Meriam. Dipastikan ada lagi Meriam tambahan dari dua kapal besar tersebut.
Segera Bahureksa ingat apa yang harus ia lakukan.
“Gorap dan kapal-kapal kita, segera mundur menjauhi Marunda,”katanya memberi perintah. Serentak tiga caraka segera melompat ke punggung kuda untuk menyampaikan perintah tersebut.
Sehari kemudian sebuah berita buruk lagi makin melengkapi kesedihan bahureksa. Anak sulungnya yang memimpin serangan dari arah barat benteng, dikabarkan menemui ajal. Pecahan peluru meriam menembus perutnya, memburaikan isi perutnya hingga ia meninggal di tempat. Tak jelas, apakah itu peluru meriam Kompeni atau justru peluru dari meriam Mataram sendiri.
Segera
Sang Tumenggung merasa lunglai. Ia bahkan harus dipegangi pengawalnya karena
nyaris terjungkal pingsan. [bersambung]
[1] Kayaknya itu serapah Belanda yang paling banyak saya baca di buku-buku lama.