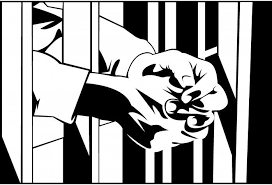GAR, McCarthyisme, dan Kematian Akal Sehat Kita

Rakyat AS berhasil mengalahkan McChartyisme karena mereka bertahan untuk mengatakan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka adalah bangsa yang waras.
Oleh : Darmawan Sepriyossa
JERNIH—Hingar bingar seputar Gerakan Anti Radikalisme (GAR)—yang seringkali dikaitkan dengan sebuah perguruan tinggi teknologi terhormat di Tanah Air—dengan gampang membawa ingatan kita kepada McCarthyisme yang sempat membawa topan badai ke dalam kehidupan sosial Amerika Serikat pada kurun 1950-1956. Satu keganjilan yang dalam common sense sempat kita perkirakan akan lenyap dari Indonesia segera setelah Reformasi 1998.

McCarthyisme, yang bagi generasi saya pun hanya dikenal dari sejarah, dalam Wikipedia diartikan sebagai “praktik membuat tuduhan subversi atau pengkhianatan tanpa mempertimbangkan bukti”. Wiki juga menambahkan arti “praktik membuat tuduhan tak adil atau menggunakan teknik penyelidikan tak adil untuk mencegah penolakan dan kritik politik” untuk terma ini.
Praktik buruk kesewenang-wenangan yang entah bagaimana bisa mengerucut menjadi lembaga yang direstui Senat dan bernama House Un-American Activities Committee (HUAC) itu dalam sejarah tercatat menelan ribuan korban. Ada banyak nama popular seperti komedian Charlie Chaplin, aktris Lucille Ball, komponis Leonard Bernstein, penulis Bertolt Brecht, novelis pemenang Nobel Thomas Mann, esais Arthur Miller, pemenang Nobel Kimia Linus Pauling, bahkan fisikawan Albert Einstein. Banyak di antara para korban ini kehilangan pekerjaan atau karier yang mereka bangun hancur berantakan. Beberapa di antaranya bahkan sampai dipenjara.
Bukan kebetulan kalau pentolan gerakan ini adalah Joseph McCarthy, senator Republikan dari Wisconsin. Hingga kini, sosok yang telah terkubur tanah berdekade-dekade itu namanya hanya diingat publik Amerika dan dunia sebagai momok dan horor. Namanya selalu terangkai dengan praktik dan keyakinan hitam penuh kebencian dan dengki. Era itu akan diingat warga AS sebagai era paling memalukan dalam sejarah mereka yang biasanya rasional dan waras.
Lalu, di millennium baru, setelah rangkaian perjuangan rakyat menumbangkan rezim Orde Baru yang seringkali melakukan cara-cara serupa itu, hal yang kongruen dengan McChartyisme justru muncul kembali ke tengah kehidupan kita. Menuding, mencerca, membenamkan orang-orang tanpa jelas kesalahan mereka kepada terungku. Tentu saja, membiarkannya berkembang hanya akan menjadikan warga Indonesia laiknya pengecut yang lari dari pengalaman buruk, hanya karena takut.
Di Amerika, tudingan mengerikan itu ‘komunis’. Di kita pada saat ini tak lain dari ‘radikal’, ‘intoleran’. Sebagaimana kaburnya kriteria ‘komunis’ dalam McChartyisme, istilah ‘radikal’ dalam perkembangan baru yang tengah marak pun abu-abu.
Bukan karena tak ada ahli bahasa yang bisa membuat definisi tegas dan pasti. Tetapi gerakan-gerakan ganjil seperti itu memang lebih memerlukan ketidakjelasan dibanding hal-hal yang presisi dan tepat. Ukuran, penanda, penera yang pasti, hanya akan membuat gerakan sejenis itu layu sebelum berkembang karena kehilangan justifikasi logisnya.
Barangkali, kalau kita tetap mengutamakan berbaik sangka (husnuz dzan), para GAR—yang dari daftar yang beredar luas ternyata diisi oleh para alumni angkatan jaduuuul—melihat apa yang mereka lakukan sebagai bentuk partisipasi aktif dan sumbangan mereka terhadap negeri ini. Suatu bentuk sumbangan yang melihat senioritas mereka–kalau saja bukan seperti yang kini mengemuka—harus kita apresiasi. Sudah senior masih berpikir buat negeri, bukankah amat baiknya?
Yang barangkali harus kita sesali adalah ajakan negara berupa pemolisian oleh masyarakat untuk mendeteksi dini adanya ekstremisme. Aturan dalam bentuk Perpres Nomor 7 Tahun 2021 itu sebenarnya riskan karena rawan memecah-belah masyarakat. Dan tak harus berbilang tahun, di hari-hari ini kita telah melihat dan merasakan tarikan ke arah itu.
Rakyat AS berhasil mengalahkan McChartyisme karena mereka bertahan untuk mengatakan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka adalah bangsa yang waras. Salah seorang waras itu, Richard Cohen, menulis di Washington Post, dan berkata,” Untuk menghadapi sebuah ancaman, seseorang harus terlebih dahulu menemukannya.” Menurut Cohen, McCharty jelas berbohong. Namun—itulah– tuduhan oleh mereka yang tengah punya kuasa (atau dekat dengan kekuasaan) kadang tak perlu bukti untuk bisa menghancurkan kehidupan mereka para tertuduh.
Apalagi kemudian Presiden Dwight Eisenhower, meski berasal dari kubu Republik sebagaimana McCarthy, menolak cara-cara barbar dalam mendiskreditkan lawan-lawan politiknya itu. “Aku tak mau masuk selokan bersama orang ini,” kata Eisenhower, seperti ditulis History.com.
Tinggal kita bertanya, mampukah kewarasan kita untuk menjaga ikatan tak tampak bernama nasionalisme ini bisa bertahan di tengah semua cobaan yang entah untuk apa dihadirkan ke tengah-tengah kita saat ini? Kalau perekat sebuah bangsa, sebagaimana kata Ernest Renan, hanyalah rasa kesetiakawanan yang agung—yang tentu sangatlah ringkih karena abstraknya—sebenarnya yang harus kita lakukan berkali-kali bukanlah mengujinya. Melainkan memperkuatnya dengan sekian banyak hal dan cara untuk menegaskan bahwa kita “satu”, “senasib”, dan sebagainya.
Kita bukanlah para warga negara pengikut Ku Klux Klan, yang percaya bahwa persatuan hanya akan terbangun jika dan hanya jika ada musuh bersama yang dihadapi. Bukan pengikut Carl Schmitt yang percaya bahwa bangunan politik bernama negara itu hanya akan tetap ada dan ditentukan keberadaan permusuhan itu. Kita bukan mereka yang percaya bahwa negara diatur oleh kemungkinan konflik yang tak [ernah hilang, yang selamanya berada di tengah ketidakpastian. Kita lebih percaya bahwa semua warga negara, dan semua negara dalam tatanan yang lebih luas, bisa maju bersama dalam harmoni. In harmonia progressio..
Negeri ini punya banyak sisi gelap yang harus dihadapinya sendiri, ketimbang ikut latah menghadirkan semacam McChartyisme lokal sebagaimana yang tengah kita hadapi. Demokrasi kita dalam sati decade ini banyak dipertanyakan. Dan itu memerlukan urun rembug bersama agar Indonesia ini bisa bertahan ada. Agar negeri ini tak jatuh kepada sistem lain yang kurang memberikan tempat kepada manusia dan rasionalitas.
Demokrasi, kata pemikir Prancis Alexis de Tocqueville, penting karena ia merupakan proses belajar bersama, yang tak habis-habis—proses yang bermula dari kesadaran bahwa presiden dan para legislator bisa salah. Tapi toh kita semua bisa belajar dari kesalahan. Itu jauh lebih berharga ketimbang memberikan cek kosong kepada seorang figur absolut, tentu.
Jadi, mari kita niatkan untuk terus mengambil pelajaran da memperbaiki. Cara itu akan otomatis pula menjadi cara untuk merawat (keberadaan) negeri ini. Bukan justru terus bereksperimen, dengan niat semata keuntungan kelompok atau bahkan lebih kecil lagi. [ ]